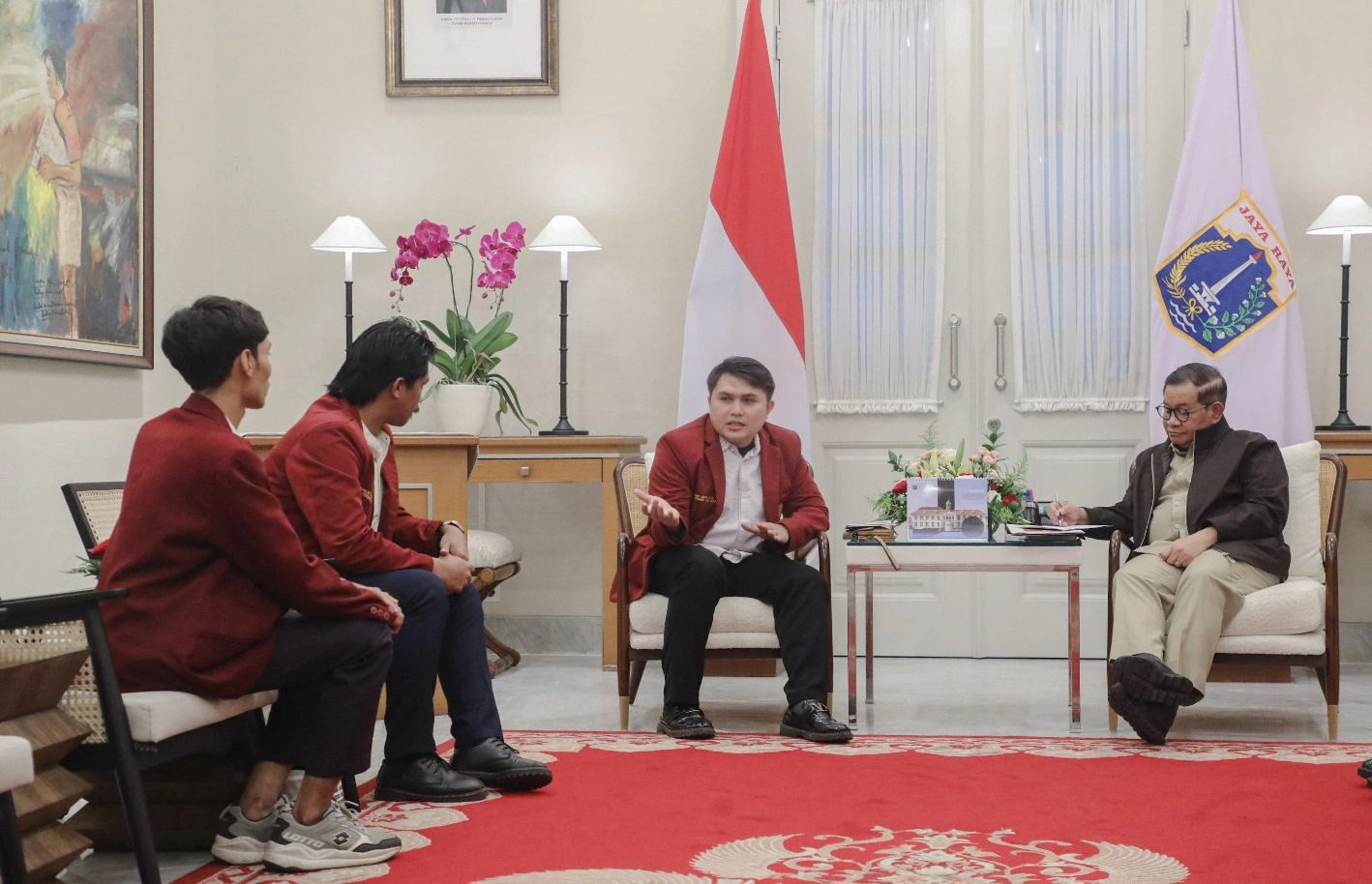Oleh: Imam Sopyan
Redaktur Majalah Risalah
Mahasiswa Program Magister
Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana, UGM
Isu pertama yang menjadi misi Menteri Agama yang baru ini adalah isu radikalisme. Isu global yang kemudian menjadi isu nasional di negara-negara yang mengalami kebangkitan gerakan keagamaan seperti Indonesia. Dengan demikian, dalam konteks isu radikalisme-lah (deradikalisasi), berbagai pernyataan dan kebijakan Menteri Agama bisa kita pahami, termasuk kebijakan mengenai PMA Majelis Taklim.
PMA Majelis Taklim yang baru saja disahkan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi, menuai kontroversi di kalangan umat Islam. Meskipun pihak Kementerian Agama berdalih bahwa PMA ini telah melalui serangkaian pembahasan bersama dengan unsur masyarakat (ormas dan organisasi yang secara khusus mengelola Majelis Taklim), produk kebijakan ini mendapat respon yang kurang positif dari berbagai tokoh. Berbagai kritik terhadap PMA Majelis Taklim bermuara pada sisi motif (urgensi), kerangka administratif (prosedur), dan cakupan regulasi (mengapa hanya umat Islam). Tulisan ini ingin melihat PMA Majelis Taklim dalam konteks yang lebih luas tentang bagaimana negara berhubungan dengan masyarakata. Sejauh mana negara harus terlibat dalam kehidupan warga negaranya? Seberapa efektif PMA Majelis Taklim akan berfungsi sebagai alat deradikalisasi, jika memang PMA Majelis Taklim ditujukan secara jangka panjang untuk memetakan dan mematahkan potensi radikalisme di tubuh umat Islam?
Peraturan Menteri Agama tentang Majelis Taklim yang baru saja disahkan tidak dapat dilepaskan dari mata rantai kebijakan dan berbagai pernyataan kontroversial Menteri Agama sejak beliau dilantik akhir Oktober lalu. Sebelumnya, Menteri Agama juga menuai kontroversi dengan pernyataannya yang berencana membuat regulasi mengenai larangan celana cingkrang dan cadar di lingkungan kantor pemerintahan. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi tidak hanya karena pernyataan ini cenderung tendensius dengan menarget kelompok Islam tertentu, tetapi juga mencederai sikap saling menghormati berbagai perbedaan pandangan keagamaan di internal umat Islam itu sendiri. Di samping itu, kita juga tidak boleh lupa pesan pertama Presiden Joko Widodo kepada Fachrul Razi dalam upacara pelantikan 20 Oktober 2019 lalu. Sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Jowo Widodo berpesan,”Bapak Jenderal Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Ini urusan berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, saya kira terutama haji berada di bawah beliau.”
Struktur Regulasi Majelis Taklim
Pengaturan terhadap majelis taklim tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2019. Peraturan ini berisi 6 Bab dan 22 Pasal. Keduapuluh dua pasal tersebut secara kategoris dapat kita bedakan ke dalam beberapa tahap pengaturan majelis taklim sebagai berikut.
1. Tahap Pendaftaran (Bab II Pasal 5 hingga Pasal 10)
Dalam bagian ini, pemerintah menentukan kriteria tertentu untuk sebuah perkumpulan kajian keagamaan agar bisa disebut sebagai Majelis Taklim (keanggotaan, kepengurusan, domisili, dll.). Ujung dari tahap pendaftaran ini adalah penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
2. Tahap Penyelenggaraan (Bab III Pasal 11 hingga Pasal 17)
Tahap penyelenggaraan adalah tahap pelaksanaan kegiatan majelis taklim itu sendiri—yang diasumsikan ‘dapat dilaksanakan’ setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah. Pasal-pasal dalam bab ini merinci unsur-unsur yang ada dalam sebuah kegiatan majelis taklim atau pengajian, yaitu pengurus, penceramah, jamaah, tempat, dan materi kajian.
3. Tahap Pembinaan (Bab IV Pasal 18 hingga Pasal 19)
Tahap pembinaan majelis taklim berisi tentang siapa saja pihak yang secara administratif akan bertugas melakukan pembinaan, yaitu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Pembinaan ini meliputi aspek pengelolaan lembaga, sumber daya manusia, dan materi kajian. Dalam konteks pembinaan bagi majelis taklim yang sudah terdaftar—memiliki SKT, majelis taklim yang bersangkutan juga melaporkan kegiatan majelis taklim dalam jangka waktu satu tahun. Laporan ini diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Laporan ini meliputi aspek kegiatan majelis taklim dan pendanaan majelis taklim.
4. Pendanaan (Bab V Pasal 20)
Pasal ini menjelaskan sumber pendanaan yang mungkin didapatkan oleh majelis taklim, yang berasal dari dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber pendanaan lainnya.
Korporatisme Negara sebagai Upaya Deradikalisasi
Mari kita posisikan kebijakan pengaturan majelis taklim ini dalam konteks yang lebih luas dan dalam. Konteks yang lebih luas akan memberikan gambaran yang utuh pada kita mengenai perilaku pemerintah saat ini, khususnya terhadap umat Islam. Pemahaman yang lebih dalam akan mampu mengungkap asumsi-asumsi tersirat yang melatar belakangi keluarnya kebijakan seperti ini. Apakah penjelasan seperti ini terlalu berlebihan? Tentu saja tidak. Sebab upaya seperti ini memberikan kesempatan bagi kita untuk keluar dari analisa sempit yang hanya terbatas pada konten regulasi tersebut tanpa melihat dimensi yang lebih luas.
Dalam konteks ini, karya Donald J. Porter, Managing Politics and Islam in Indonesia mampu memberikan inspirasi analisis terhadap realitas politik saat ini, khususnya ketika membaca perilaku negara terhadap umat Islam. Melalui pendekatan korporatisme negara, Porter membaca sejarah politik Orde Baru dalam konteks relasi negara-masyarakat (state-societal relationship). Mengutip Douglas A. Chalmers, Donald J. Porters menjelaskan bahwa korporatisme terdiri dari beberapa praktek sebagai berikut.
- Korporatisme bermula dari institusi negara dan berusaha mengidentifikasi berbagai kelompok kepentingan dan hubungannya dengan negara itu sendiri.
- Korporatisme tidak hanya melihat kepentingan negara, tetapi juga mempertimbangkan kondisi-kondisi struktural yang menentukan hubungan-hubungan tertentu antar berbagai kelompok kepentingan dan birokrasi.
- Korporatisme tidak melihat negara sebagai entitas tunggal dengan satu kepentingan, tetapi sebuah institusi yang terbentuk dari berbagai jenis hubungan yang berbeda-beda dengan kelompok-kelompok kepentingan ekonomi dan profesi. Negara tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakatnya.
Dengan membaca kembali sejarah Islam politik Orde Baru—bagaimana pemerintahan Orde Baru ‘menangani’ umat Islam—melalui kaca mata korporatisme negara, kita dapat mendudukkan eksistensi berbagai lembaga yang hingga saat ini masih beroperasi sebagai bentuk korporatisme negara terhadap umat Islam dan derivasinya—berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam tubuh umat Islam.
Institusi Korporatis dalam Sejarah
Ada beberapa institusi keagamaan yang berafiliasi ke umat Islam yang didirikan pada masa Orde Baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan bentuk inkorporasi negara terhadap para ulama di Indonesia; Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) merupakan bentuk inkorporasi negara terhadap masjid; Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (BAKOMUBIN) dan Majelis Dakwah Indonesia (MDI) merupakan bentuk inkorporasi negara terhadap para penceramah; Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) merupakan bentuk inkorporasi negara terhadap perkumpulan organisasi perempuan Islam; dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai bentuk inkorporasi negara terhadap para cendekiawan muslim di Indonesia. Dalam konteks pengaturan majelis taklim, kita akan melihat penjelasan Donald J. Porter di atas dalam bukunya Managing Politics and Islam in Indonesia mengenai institusi korporatis yang menangani masjid (DMI dan BKPRMI) dan penceramah (BAKOMUDIN dan MDI).
Dewan Masjid Indonesia (DMI) merupakan organisasi tingkat nasional yang dibentuk rezim Orde Baru untuk mengatur aktivitas-aktivitas masjid yang berpusat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Didirikan pada 1972—dan saat ini masih beroperasi—DMI bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, dan merepresentasikan semangat kebangsaan. DMI berkewajiban untuk mengingatkan masyarakat atas “kewajiban kolektifnya kepada negara”. Demikian diungkapkan oleh Z.H. Noeh, Ketua Umum DMI saat ini dalam wawancara dengan Porter.
Porter secara bernas menjelaskan bahwa DMI adalah ....one of the various corporatist institution co-ordinated by the Department of Religion or Golkar, which was instrumental to the state’s expanding jurisdiction over religious association through the propagation of an ‘official Islam’......it became a tool in the regime’s strategy to co-opt and neutralise anti-regime Islamic organizations and activists by channelling them into social acitvities. (DMI merupakan salah satu institusi korporatis yang berada di bawah koordinasi Departemen Agama atau Golkar yang mampu memperluas cakupan dominasi negara melalui kampanye ‘Islam resmi’. DMI menjadi strategi rezim untuk mengkooptasi dan menetralisir ormas dan aktivis Islam yang anti-rezim dengan menghubungkan mereka kepada kegiatan-kegiatan sosial).
Dalam konteks ‘kooptasi dan netralisasi’ kelompok-kelompok anti-rezim ini, dibentuklah sebuah lembaga yang khusus menangani kelompok pemuda dan remaja Islam, yaitu BKPRMI yang secara institusional berada di bawah koordinasi DMI. BKPRMI menjadi sayap organisasi DMI yang tentu saja memiliki sifat yang sama dengan induknya sebagai organisasi korporatis. Hal ini, misalnya, nampak dalam isu mengenai asas tunggal pada pertengahan dekade 1980-an. Di tengah pro dan kontra mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap perkumpulan di Indonesia, BKPRMI secara mantap menerima asas tunggal sebagai asas organisasi. Di samping itu, ketua BKPRMI saat itu, Toto Tasmara, dipilih sebagai sekretaris perusahaan PT. Humpuss Group yang merupakan perusahaan milik Tommy Soeharto. Perusahaan ini juga menjadi penyandang dana dan pendamping beberapa kegiatan BKPRMI itu sendiri. Sifat korporatis kedua organisasi jelas sekali jika dilihat dalam proses pendirian dan pengelolaannya.
Tidak cukup mengkooptasi masjid, pemerintah Orde Baru juga merasa perlu melakukan kooptasi terhadap para penceramah dengan mendirikan organisasi BAKOMUBIN dan MDI. Didirikan pada pertengahan dekade 1970-an, BAKOMUBIN didirikan dalam sebuah pertemuan para penceramah dari 27 provinsi dari seluruh Indonesia—saat itu provinsi di Indonesia masih berjumlah 27 provinsi dan Toto Tasmara terpilih menjadi Ketua Umum pertama. Pertemuan nasional pertama ini dihadiri oleh perwakilan resmi dari Departemen Agama—sekarang Kementerian Agama—yang menyampaikan sambutan; bahwa seorang muslim memang harus fanatik terhadap keyakinan agamanya, tetapi tidak boleh ekstrem dalam berpolitik. Sambutan ini mengingatkan kita pada ungkapan M. Natsir; bahwa Islam beribadah itu akan dibiarkan. Islam berekonomi akan diawasi. Islam berpolitik itu akan dicabut seakar-akarnya. Meskipun secara normatif institusi ini tidak akan terlibat dalam urusan politik, rezim Orde Baru tetap memanfaatkan BAKOMUBIN—sebagaimana yang dilakukan Orde Baru terhadap institusi lainnya—untuk tujuan-tujuan politik, salah satunya adalah memobilisasi suara umat Islam agar mendukung pencalonan Soeharto sebagai presiden.
Rezim Orde Baru juga berperan aktif dalam pendirian organisasi Majelis Dakwah Islam (MDI) dan Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD) melalui tangan Golongan Karya. Didirikan pada 1978, MDI secara khusus ditujukan untuk menandingi penetrasi para penceramah dari kalangan Nahdhatul Ulama (NU) yang berafiliasi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang cenderung kritis terhadap pemerintah dalam ceramah-ceramahnya. Secara umum, MDI memiliki misi—merujuk pada wawancara terhadap kepala sekretariat MDI saat itu, Hidayat—untuk memoderasi kelompok ‘muslim ektrem’ dan menariknya ke dalam keluarga besar Golongan Karya (Golkar). Untuk tujuan ini, MDI kemudian bergabung dengan sebuah konsorsium, Forum Komunikasi Organisasi Islam (FKOI) yang beranggotakan 31 organisasi Islam, yang terdiri dari organisasi muslim moderat, konservatif, maupun ekstrem. Konsorsium ini, selain bertujuan untuk memoderasi anggota-anggotanya, FKOI bertugas untuk memobilisasi dukungan dari umat Islam terhadap Golongan Karya (Golkar) pada masa pemilihan umum.
Meskipun dikelola oleh masyarakat atau representasi dari ormas, berbagai organisasi ini dikenal sebagai organisasi semi-plat merah yang dapat dibedakan—meskipun agak samar-samar—dengan organisasi yang murni lahir dari rahim dinamika umat Islam itu sendiri, misalnya ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, dan seterusnya. Jika ormas-ormas Islam yang disebut belakang lahir secara dari bawah, maka organisasi-organisasi korporatis lahir dari atas yang di awali dari pemetaan atas berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam tubuh umat Islam. Organisasi-organisasi korporatis ini, selain memang dibentuk untuk menjadi tempat berkumpul sejumlah kelompok kepentingan sejenis, juga dapat berfungsi sebagai katalisator pencapaian kepentingan penguasa. Mereka bisa saja menjadi alat pemerintah untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kepentingan politik saat masa pemilihan umum ataupun saluran-saluran sosialisasi kebijakan pemerintah.
Regulasi Majelis Taklim sebagai Kebijakan Korporatis
Dengan berkaca pada sejarah perilaku pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam, regulasi PMA Majelis Taklim ini, pada satu sisi, merupakan upaya awal dan langkah halus (soft) yang sedang ditempuh pemerintah untuk melakukan inkorporasi—kooptasi kelompok-kelompok kepentingan ke dalam kepentingan negara—simpul-simpul kajian keagamaan. Di sisi lain, isu deradikalisasi yang menjadi tugas utama Menteri Agama saat ini merupakan kerangka besar yang menjadi latar disahkannya regulasi Majelis Taklim ini. Dalam konteks ini, Silvio Duncan Baretta dan Hellen A. Douglas telah mengidentifikasi tiga tujuan utama dari model korporatisme negara sebagai berikut; (1) Korporatisme sebagai alat kontrol atau dominasi terhadap kelompok-kelompok sosial; (2) Korporatisme sebagai saluran komunikasi antara berbagai organ negara dengan kelompok-kelompok sosial; (3) Korporatisme sebagai cara untuk mengamankan dukungan terhadap rezim tertentu.
Tanpa bermaksud memberikan spekulasi yang berlebihan, implementasi dari regulasi PMA Majelis Taklim ini memiliki potensi untuk bekerja dalam kerangka tiga tujuan utama korporatisme negara sebagaimana diidentifikasi oleh Baretta dan Douglas di atas. Agenda pembinaan yang diatur dalam PMA ini bisa saja menjadi upaya kontrol bahkan dominasi negara terhadap dinamika kajian-kajian keagamaan yang sudah berkembang secara organik di masyarakat. Apakah kontrol ini seluruhnya bersifat negatif bagi perkembangan kajian-kajian keagaman tersebut? Tentu saja tidak, tetapi sifat represif (menekan), koersif (memaksa), dan birokratis dari perilaku negara membuat intervensi negara ini nampak tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan kajian keagamaan di internal umat Islam.
Pola insentif finansial yang dijanjikan kepada setiap majelis taklim yang terdaftar juga berpotensi menjadi ‘alat kontrol’ dan ‘dominasi’ negara terhadap majelis taklim itu sendiri. Bukan tidak mungkin pola insentif finansial ini ke depannya akan berkaitan dengan erat dengan regulasi mengenai materi kajian dan kategori penceramah dalam majelis taklim tersebut. Jika kita memandang regulasi ini sebagai upaya deradikalisasi, maka bisa saja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, akan menetapkan tema-tema tertentu yang diperbolehkan menjadi tema kajian majelis taklim terdaftar. Jika suatu majelis taklim terbukti memberikan materi kajian yang berbeda dengan ‘standar pemerintah’ atau tema-tema yang ditafsirkan pemerintah sebagai tema-tema dengan pemahaman radikal, maka aspek pendanaan bisa menjadi disinsentif bagi majelis taklim tersebut, misalnya dengan pemberhentian pendanaan atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Sebagai sebuah saluran komunikasi antara berbagai kelompok kepentingan dengan negara, regulasi ini memang memiliki fungsi positif sebagai kanal alternatif bagi sosialisasi kebijakan pemerintah. Namun, sebagaimana disinyalir oleh Baretta dan Douglas di atas, kanal alternatif ini juga bisa menjadi alat pengamanan dukungan terhadap rezim yang sedang berkuasa. Hal ini misalnya terjadi dalam kasus pembentukan perkumpulan berbasis profesi pada masa Orde Baru, seperti Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) atau Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Melalui dua organisasi ini, misalnya, rezim Orde Baru mampu memastikan dukungan unsur pegawai negeri sipil dan guru—sebuah sebuah kelompok kepentingan—terhadap rezim Orde Baru, baik dalam masa-masa pemilihan umum maupun sikap-sikap kelompok ini terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Bentuk Inkonsistensi
Sesaat setelah dilantik sebagai Menteri Agama, Jenderal Fachrul Razi mengatakan bahwa dia bukan Menteri Agama Islam, melainkan menteri semua agama yang diakui di Indonesia. Pernyataan ini, meskipun menandakan bahwa Jenderal ini tidak begitu paham sejarah pembentukan Kementerian Agama itu sendiri, namun bisa kita pahami sebagai upaya untuk merangkul semua umat beragama di Indonesia demi intergasi bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fachrul Razi menyatakan,”Saya kan bukan menteri agama Islam, saya menteri agama Republik Indonesia yang di dalamnya ada lima agama.” Pernyataan ini nampak merupakan basa-basi (lip service) saja jika kita bandingkan dengan berbagai pernyataan dan kebijakan Menteri Agama sejak dilantik hingga saat ini.
Kita belum mendapatkan pernyataan dan kebijakan Menteri Agama yang secara umum ditujukan atau berlaku untuk semua agama di Indonesia. Sejak isu cadar dan celana cingkrang hingga majelis taklim, tidak pernah Menteri Agama memberikan pernyataan yang memberikan perhatian khusus kepada dinamika keagamaan di luar Islam. Majelis Taklim sendiri secara gramatikal maupun historis adalah fenomena khas umat Islam. Jadi PMA Majelis Taklim ini adalah bentuk pengingkaran Menteri Agama terhadap pernyataannya sendiri. Sebab jika Menteri Agama konsisten dengan pernyataannya, seharusnya PMA ini mengatur kajian keagamaan di seluruh agama yang ada di Indonesia. Kajian-kajian keagamaan sejenis barangkali ada dalam tradisi agama lainnya, tetapi aturan PMA tentang Majelis Taklim ini jelas sekali hanya ditujukan pada umat Islam saja. Tidak ada satupun kata atau klausul yang menyinggung eksistensi agama lain atau menyebut istilah kajian keagamaan dalam tradisi agama lain, baik Katholik, Protestan, Hindu, Budha, maupun Konghucu.
Kita patut bertanya mengapa. Jawabannya tentu saja tidak terlalu sulit. Sebab sasaran tembak deradikalisasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Agamanya ini adalah umat Islam. Sebab radikalisme yang dimaksud adalah radikalisme umat Islam. Itulah mengapa aturan seperti ini, dan bisa jadi aturan selanjutnya yang sejenis, akan ditujukan khusus kepada umat Islam—terlepas pernyataan Jenderal Fachrul Razi bahwa beliau adalah bukan Menteri Agama Islam saja.
Memetakan dan Mematahkan Radikalisme?
Jika agenda pertama dan utama Menteri Agama di Kabinet Kerja Jilid 2 ini adalah program deradikalisasi (umat Islam), maka PMA Majelis Taklim ini bisa didudukkan sebagai tahapan pemetaan (mapping) terhadap sebaran majelis taklim berdasarkan materi-materi kajian yang dibahas dalam majelis taklim tersebut. Hal ini biasanya berangkat dari asumsi dasar bahwa aksi-aksi radikal dan teroris berawal dari pandangan yang radikal terhadap ajaran agama Islam, misalnya bolehnya melakukan bom bunuh diri, anti-NKRI, dan seterusnya. Pemetaan ini tentu saja penting bagi pemerintah untuk memiliki informasi yang utuh terhadap situasi umat Islam dan dinamika internalnya. Praktek pemetaan ini kemudian terimplementasi dengan prosedur pendaftaran majelis taklim dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Bagaimana dengan dalih pembinaan dan insentif finansial yang akan menjadi tindak lanjut program dari pemetaan ini? Justru dalam tahap pembinaanlah agenda deradikalisasi yang menjadi pesan Presiden akan dikerjakan. Insentif finansial yang dijanjikan kepada setiap majelis taklim justru memberikan ambivalensi sikap pemerintah dalam regulasi ini.
Di satu sisi, pemerintah tidak akan memberikan sanksi apapun kepada majelis taklim yang tidak mendaftarkan diri kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Di sisi lain, insentif finansial ini—secara administratif—hanya akan diberikan kepada majelis taklim yang telah mendaftarkan diri hingga mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dalam konteks ini, kita dapat melihat pernyataan bahwa regulasi ini bersifat tidak mengikat bagi semua majelis taklim sebenarnya merupakan upaya menutupi sifat memaksa dari setiap kebijakan pemerintah. Sifat memaksa dari kebijakan pemerintah ini terwujud dalam bentuk bantuan pendanaan bagi majelis taklim yang mendaftarkan diri saja, sehingga majelis taklim yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri kepada pemerintah tidak akan mendapatkan akses bantuan finansial dari pemerintah.
Cara seperti ini mengingatkan kita pada strategi stick and carrot (tongkat dan wortel) yang memang biasanya dipilih negara untuk memberlakukan suatu kebijakan tertentu. Ketika sebuah kebijakan diberlakukan, pemerintah akan memberikan stick (pukulan/hukuman) kepada warga negara yang tidak mengikuti kebijakan tersebut. Sementara itu, pemerintah akan memberikan carrot (wortel) ketika warga negara dapat mengikuti regulasi tersebut. Cara ini, misalnya, dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur di Xinjiang agar mereka dapat ‘berintegrasi’ dan ‘berdamai’ China, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Mengapa majelis taklim yang disasar sebagai upaya untuk memetakan radikalisme umat Islam? Barangkali pemerintah percaya bahwa radikalisme berawal dari pandangan keagamaan tertentu yang mendorong tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama, anti-negara bangsa, dan seterusnya. Untuk itulah, pemerintah merasa perlu terhadap data majelis taklim; pengelolanya, penceramahnya, materinya, sekaligus nominal dana yang terkumpul.
Dalam tradisi teori politik tentang radikalisme, sebenarnya tumbuh suburnya radikalisme memiliki banyak aspek yang menjadi latar belakang, salah satunya aspek pemikiran. Artinya, aksi-aksi radikalisme tumbuh subur karena memang pemikiran-pemikiran radikal tersemai secara konsisten di berbagai simpul-simpul masyarakat, dalam hal ini di kantung-kantung kajian keagamaan. Namun pandangan ini hanya satu dari beberapa pandangan lain yang mencoba memberikan penjelasan sekaligus obat yang berbeda dengan pandangan pertama ini, yang dikenal dengan pandangan primordialis.
Pandangan lain adalah pandangan yang mencoba melihat aktor-aktor yang memanfaatkan aksi-aksi radikalisme ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik politik maupun ekonomi. Pandangan ini dikenal dengan pandangan instrumentalis. Artinya, aksi-aksi radikal ini dibuat dan direkayasa sedemikian rupa untuk menimbulkan kondisi tertentu di masyarakat sehingga pihak-pihak yang berada di balik aksi-aksi tersebut mampu memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Dalam khazanah teori politik, aktor ini dikenal dengan sebutan political entepreneur (wirausahawan politik). Bagi para instrumentalis, seseorang atau sekelompok orang bisa saja memiliki pandangan keagamaan moderat, namun ketika para wirausahawan politik telah merakayasa sedemikian rupa situasi sosial politik di negara tertentu, maka aksi-aksi radikal dimungkinkan terjadi.
Pandangan selanjutnya adalah pandangan institusionalis. Pandangan institusionalis terhadap radikalisme menyatakan bahwa fenomena radikalisme merupakan bentuk kegagalan pengelolaan berbagai institusi-institusi dalam melakukan upaya-upaya preventif terhadap aksi-aksi radikalisme itu sendiri. Institusi terbesar yang bertanggungjawab adalah negara itu sendiri sebagai pihak yang memiliki seperangkat alat dan kekuatan untuk melakukan langkah dan mengambil kebijakan apapun untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi warga negaranya.
Oleh karena itu, jika memang majelis taklim dipahami sebagai salah satu sumber radikalisme di Indonesia—sebagaimana pandangan primordialis—maka sebaiknya pemerintah juga memahami aspek lain yang bisa saja menjadi penyebab tumbuh suburnya aksi radikalisme di Indonesia. Misalnya, jika kita mempertimbangkan pandangan instrumentalis, bukankah tidak mungkin jika aksi-aksi radikalisme di Indonesia merupakan hasil kerja-kerja dari aktor-aktor tak kasat mata yang mendapatkan keuntungan-keuntungan dari situasi yang timbul dari aksi radikalisme itu sendiri? Lebih telak lagi, jika kita mempertimbangkan pandangan institusionalis, maka sebenarnya menjamurnya aksi kekerasan dan radikalisme seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi kinerja negara sendiri sebagai institusi raksasa yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban warga negaranya. Jika hal ini dipahami oleh pemerintah, maka langkah yang diambil dalam upaya deradikalisasi tidak akan sekedar pemberlakukan regulasi yang akan sangat birokratis, tidak subtansial, dan menimbulkan polemik di masyarakat.
Kita berharap perilaku rezim saat ini, khususnya dalam menghadapi dinamika umat Islam mampu mengedepankan sikap-sikap yang matang dan ‘inklusif’. Dalam kasus yang juga kontroversial lainnya—penghapusan materi jihad dan khilafah, misalnya, pemerintah nampak tidak cukup dewasa untuk menangani dinamika umat Islam saat ini. Alih-alih memberikan ruang integrasi yang inklusif terhadap peran umat Islam secara utuh ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah justru memilih kebijakan yang eksklusif dan nampak belum bisa belajar dari sejarah bangsa ini sendiri.
***
Sumber foto: https://kastara.id