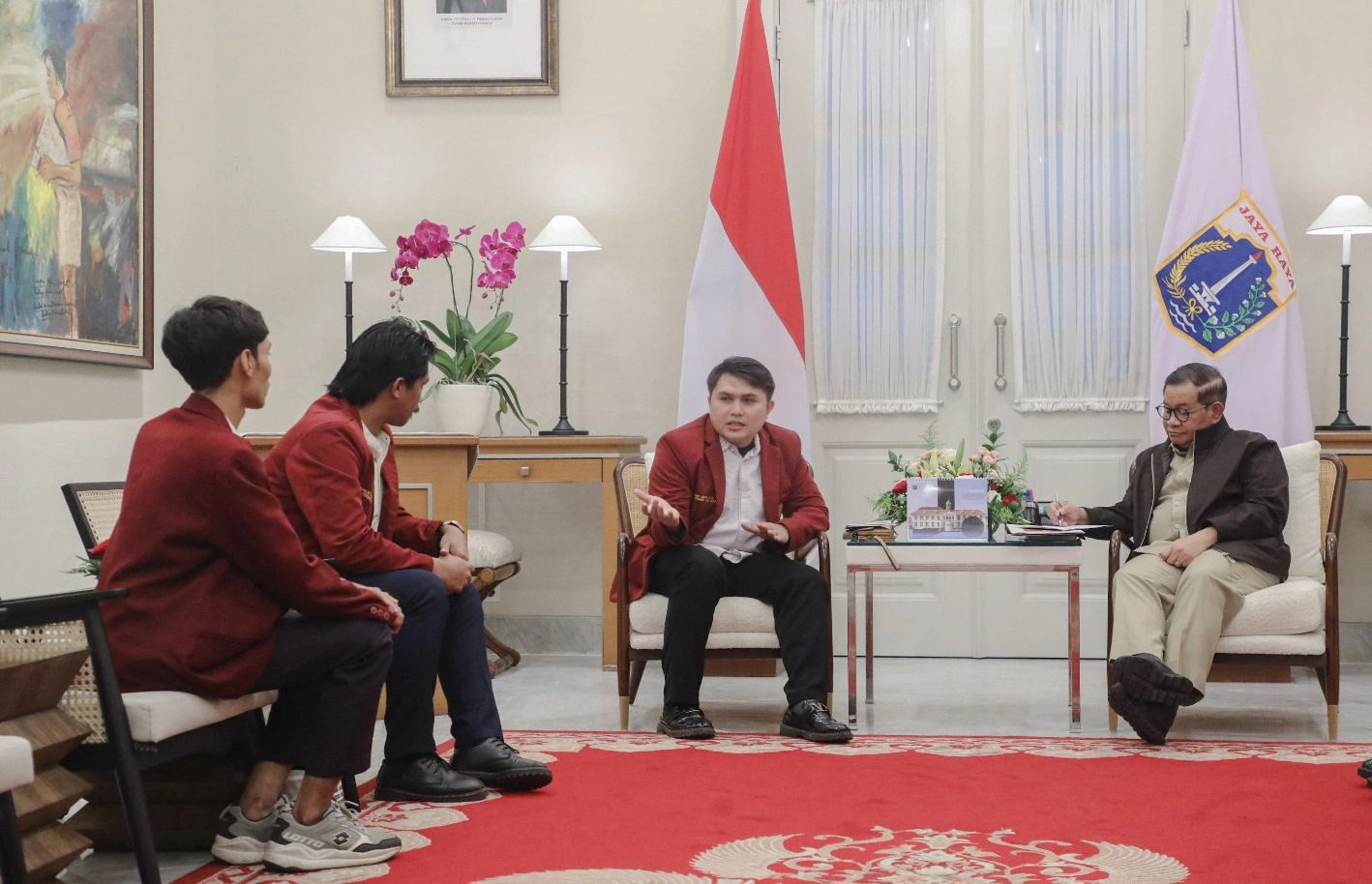Bandung - persis.or.id, Sudah menjadi pengetahuan umum tentang tidak seragamnya penentuan awal bulan-bulan Hijriyah di Indonesia. Masing-masing memiliki dalil dari sudut pandang sendiri-sendiri yang dianggap paling kuat dibandingkan dengan dalil yang dimiliki pihak lain. Bahkan, semakin kemari kecenderungan beragamnya semakin tidak terkendali. Mula-mula perdebatan adalah soal apakah mesti rukyat atau boleh hisab hingga muncul mazhab rukyat dan mazhab hisab. Rupanya dalam setiap mazhab ini berkembang pula perbedaan-perbedaan yang lebih rumit, terutama pada mazhab hisab. Ada yang berpatokan pada wujudul-hilal. Ada pula yang mengkompromikannya dengan rukyat sehingga lahir mazhab imkanur-rukyat. Masalah rupanya tidak berhenti sampai di situ. Soal imkanur-rukyat ini pun tidak sepaham dalam soal berapa ukuran “mungkin dilihat itu?” Ada yang berpendapat—dalam bahasa awam—bahwa kemungkinan bisa dilihat itu apabila sudah setinggi 2 derajat. Ada juga pendapat baru harus minimal 4 derajat; bahkan menurut data ilmiah yang akurat adalah 6 derajat.
Mazhab Rukyat yang kelihatannya lebih objektif dan terlibat langsung juga tidak luput dari perbedaan-perbedaan. Misalnya soal penentuan mathla’, apakah rukyat di satu tempat berlaku untuk seluruh dunia atau hanya berlaku di tempat bersangkutan. Dari sini lahir mazhab rukyat global dan rukyat lokal. Selain pembelahan metodologis semacam itu, pada teknisnya pelaksanaan rukyat juga bukan tanpa masalah. Kecanggihan penggunaan alat bantu rukyat akan menentukan juga tingkat akurasi dalam menentukan mana hilal mana yang bukan. Oleh sebab itu, bisa jadi muncul perbedaan dalam melihat ada dan tidaknya hilal. Perbedaan itu tentu saja akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula, walaupun satu mazhab.
Saya sendiri sebagai yang awam dalam masalah ini tentu bukan pada tempatnya untuk membahas mazhab mana yang paling baik. Dibutuhkan tarjîh oleh para ahlinya untuk sampai ke sana. Menganggap kuat satu pandangan dan melemahkan pandangan lain adalah hal lumrah dalam masalah-masalah fiqhiyyah-ijtihadiyah. Cara-cara inipun sesungguhnya sangat positif dalam menumbuhkan ilmu pengetahuan dalam bidangnya. Kita menyaksikan betapa luar biasanya perkembangan berbagai ilmu ketika dihadapkan pada perbedaan-perbedaan pandangan. Satu sama lain akan saling mengritik dan mempertahankan argumen masing-masing. Tentu saja untuk itu dibutuhkan argumen-argumen baru yang pasti akan mendorong sang ilmuwan untuk terus memperdalam ilmunya guna mempertebal argumen yang dibangunnya.
Hanya saja, di samping perbedaan pandangan berdampak positif bagi perkembangan ilmu, dia juga bisa berekses negatif ketika bersentuhan dengan perkara-perkara lain yang berada di luar dirinya. Perbedaan penentuan awal bulan Shafar misalnya. Metode penetapannya sesungguhnya sama saja dengan penetapan awal bulan lain sehingga potensi perbedaannya pun cukup tinggi. Akan tetapi, karena perbedaan-perbedaan itu tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, maka perbedaan yang ada hanya menjadi sekedar intellectual exercise. Tidak ada orang yang menjadi ribut gara-gara berbeda dalam menetapkan awal bulan Shafar. Akan tetapi, ketika yang dibicarakan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ceritanya sama sekali lain. Keramaian akan segera tersaksikan.
Masalahnya bukan semata-mata masalah metodologi yang juga sama digunakan untuk menentukan bulan Shafar. Akan tetapi, masalahnya pada bulan-bulan itu terdapat ibadah-ibadah kolosal yang meyangkut banyak orang, antara lain: shaum wajib sebulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha serta Haji. Pada bulan-bulan lain pun terdapat ibadah yang butuh penanggalan seperti shaum bulan purnama penuh (ayyâmul-bîdh), shaum tasu’a dan ‘asyura pada bulan Muharram, dan sebagainya. Akan tetapi, karena ibadah-ibadah pada bulan lain cenderung berdimensi pribadi dan tidak banyak melibatkan orang lain secara kolosal, maka penentuan-penentuan awal bulan tidak terlalu dipermasalahkan. Ada yang kembali berpegang pada mazhabnya masing-masing; dan paling banyak hanya ikut saja kalender umum yang ditetapkan pemerintah.
Seandainya tidak menjadi masalah berbeda awal Ramadhan dan berbeda menjalankan dua Shalat Ied, mungkin perbedaan-perbedaan kesimpulan penetapan tanggal juga tidak akan bermasalah seperti pada bulan-bulan lain. Akan tetapi, justru masalahnya ada di sini, dalam perkara yang bukan substansi ijtihadnya itu sendiri. Masalah yang muncul adalah dari hubungan antar-masyarakat atau masalah-masalah sosial; dan bahkan mungkin bisa berkembang menjadi masalah politis. Mari kita lihat kegaduhan yang sering terjadi di masyarakat akibat perbedaan-perbedaan penetapan tanggal ini.
Setiap memasuki Ramadhan setiap masjid pasti berbenah untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan sejak awal Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri tiba. Umumnya semua dipersiapkan berdasarkan kalender yang dipegang masing-masing. Ketika kalender yang dipegang setiap masjid berbeda-beda dalam memprediksi awal bulan Ramadhan dan Syawal, persoalan yang akan segera timbul adalah “kebingungan” kalangan awam. Sebagian jamaah atau pengurus akan mempertanyakan mengapa bisa sampai berbeda memulai puasa. Padahal mereka tinggal di kampung yang sama. Kalau pertanyaan ini sampai kepada orang-orang yang paham masalah ijtihadiyah di dalam fikih, mungkin efeknya tidak telalu besar. Masalah akan didudukkan sebagaimana umumnya persoalan khilafiyah. Hanya saja, di kalangan awam hanya sedikit; bahkan boleh dikatakan minoritas, yang memahami masalah perbedaan ini sebagai wilayah ijtihadiyah.
Ketika di kalangan awam pemahaman masalah ijtihadiyah ini rendah, maka yang terjadi adalah potensi disintegrasi sosial. Sebab, ada yang memahaminya sebagai masalah pokok yang meyebabkan sah dan tidak sahnya puasa yang dijalankan. Yang memulai puasa lebih dahulu dianggap berpuasa sebelum waktunya. Yang berpuasa lebih lambat dituduh telah melewatkan satu haru puasa pada bulan Ramadhan. Saling tuduh ini bahkan bukan hanya di kalangan jamaah awam, seringkali pangkalnya dari para penceramah Ramadhan yang kelihatannya ingin memaksakan hanya pandangannya yang benar dengan menyalahkan pandangan lain, padahal ranahnya jelas-jelas masalah ijtihadiyah. Kalau si penceramah itu hanya menjelaskan apa yang diyakininya, sambil menoleransi yang lain, mungkin akan lebih baik. Akan tetapi, banyak penceramah yang bermodal ilmu pas pasan hingga semakin memperkeruh suasana. Persengketaan dalam suasana yang keruh dapat pula naik ekskalasinya menjadi bibit konflik yang lebih besar lagi bila ada kepentingan-kepentingan duniawi yang masuk.
Saat yang berbeda adalah awal Ramadhan, mungkin kekisruhan hanya seputar masalah perbedaan pandangan seperti di atas. Dari segi amaliah, karena puasanya sendiri bersifat sangat individual, tidak begitu kentara antara yang berpuasa lebih dahulu dan yang belakangan. Lain halnya ketika penentuan Idul Fithri. Di Indonesia, perkara Lebaran ini bukan hanya soal ibadah, melainkan ada dimensi sosial yang sangat melekat padanya. Idul Fithri alias lebaran ini identik dengan mudik yang sangat kolosal, silaturahim antar-kelurga, makanan khas lebaran, dan yang paling pokok adalah pelaksnaan shalat ‘Id. Perbedaan menetapkan Idul Fithri sangat terlihat membelah masyarakat. Perdebatan seperti halnya penentuan awal puasa sudah pasti tidak bisa dihindari. Lebih dari itu, perbedaan Idul Fithri mempertontonkan fenomena yang cukup menyesakkan bagi yang menyaksikannya, baik dari jauh maupun dari dekat.
Saat Idul Fithri atau Idul Adha berbeda, segera terlihat ada dua shalat Ied pada hari yang berbeda di kampung yang sama. Silaturahim antar-tetangga dan sanak saudara juga menjadi tidak khidmat karena saat sebagian sudan ‘Idul Fithri, yang lain masih berpuasa. Begitu juga pembangian zakat fitrah, tidak dapat dilakukan serentak. Pada saat berbeda Idul Ahda pun sama. Akan ada dua gelombang pelaksanaan shalat ‘Id dan pelaksanaan pemotongan hewan qurban. Semuanya terlihat begitu jelas di depan mata semua orang karena ibadah-ibadah itu bersifat kolosal dan sosial. Oleh sebab itu, jelas sekali terlihat keterbelahan masyarakat gara-gara perbedaan penetapan Idul Fithri dan Idul Adha ini.
Alasan-alasan di atas memang tidak bisa dijadikan alasan tentang bagaimana seharusnya penetapan hilal yang tepat dan benar. Akan tetapi, alasan-alasan di atas dapat dijadikan salah satu acuan untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para fuqoha dalam memilih jalan yang tepat untuk keluar dari perbedaan pandangan ini, sesuai anjuran suatu kaidah fiqih al-khrurûj minal-khilâf mustahab (keluar dari perbedaan adalah dianjurkan). Kaidah ini mendorong satu titik temu dalam perbedaan pendapat tersebut. Alasan-alasan di atas dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk menemukan strategi yang baik.
Persoalan publik seperti di atas mengisyaratkan bahwa penyelesaian ikhtilafnya tidak bisa dengan berdebat menetapkan satu metodologi tertentu yang harus dipegang semua. Selain hingga saat ini tdak pernah ada kemauan dari masing-masing kelompok untuk merevisi metodologinya, memaksakan untuk hanya menggunakan satu metode dan mengharamkan yang lain justru akan menghambat perkembangan kajian dalam bidang ini. Artinya, ilmu pengetahuan akan mandek. Akan tetapi, di sisi lain perlu ada penyatuan kalender ini agar terwujud al-jama’ah (kebersamaan) di antara kaum Muslim dalam menjalankan ibadah kolosalnya.
Karena ini menyangkut kepentingan umum (publik) yang pengurusannya menjadi tanggung jawab pemerintah, maka kaidah yang paling tepat dijadikan landasan adalah “hukmul-hâkim yarfa’ul khilâf” (penetapan oleh pemerintah dapat menghilangkan perbedaan pendapat). Oleh sebab itu, yang paling tepat adalah semua kelompok yang berbeda-beda metodologi dalam menetapkan hilal ini sebaiknya berkumpul dengan wasitnya pemerintah. Mereka boleh mengemukakan pendapat dalam forum tersebut mengusulkan apa saja kepada pemerintah. Akan tetapi, ujungnya semua harus menerima keputusan apapun yang diambil dan ditetapkan pemerintah. Di luar itu, kelompok-kelompok tersebut tidak diperkenankan untuk mengeluarkan pengumuman dan ketetapan sendiri. Kalaupun mereka membuat kalender harus diberi catatan bahwa momen-momen tertentu kalender dapat direvisi sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Ketika pemerintah dapat menetapkan satu tanggal yang dipegang bersama, maka dengan demikian tindakan pemerintah yang selalu harus bersandar pada prinsip kemaslahatan telah tepat. Kaidah fikih mengatakan Tasharruf al-imâm ‘alâ ra’iyyatihi manûthun bil-mashlahah (perbuatan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan prinsip maslahat). Kemaslahatan dalam penetapan kalender adalah kesamaannya sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kekacauan bagi umat. Oleh sebab itu, sudah tepat apabila persoalan kalender yang berhak memutuskannya adalah ulil amri. Wallâhu A’lam.
Penulis: Dr. Tiar Anwar Bachtiar.