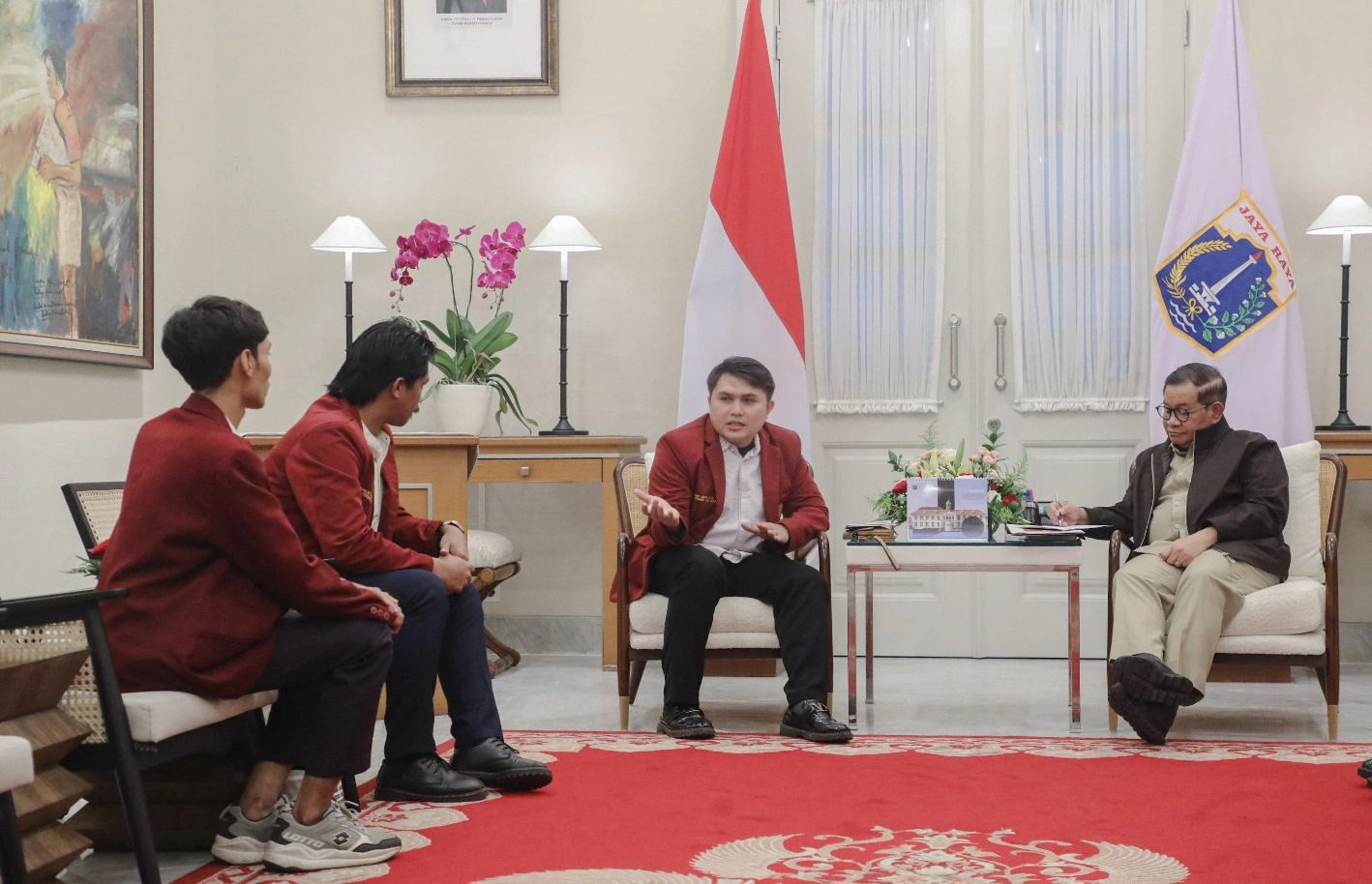Imam Sopyan
Ditembaknya 6 orang pengawal rombongan Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh aparat polisi pada 7 Desember 2020 lalu di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 50 menyisakan sejumlah kontroversi. Tindakan yang diduga keras merupakan extrajudicial killing (pembunuhan di luar prosedur hukum) ini rasanya menjadi penutup yang buruk bagi kinerja rezim petahana pada tahun 2020. Publik Indonesia tentu saja tidak tinggal diam. Hampir setiap elemen masyarakat, baik personal maupun kelompok, telah menyampaikan protes, kritik, tuntutan, hingga pertanggungjawaban dari pihak pemerintah, khususnya kepolisian, atas peristiwa pembunuhan ini. Sayangnya, ada juga sebagian pihak yang justru memberikan dukungan terhadap tindakan penembakan tersebut dengan dalih pemberantasan radikalisme.
Dalam hal ini, Dewan Tafkir Pimpinan Pusat Persis, yang dikomandoi oleh Dr. Muslim Mufti, yang juga seorang dosen ilmu politik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berinisiatif menyelenggarakan diskusi publik dengan menjadikan kasus ini sebagai topik pembicaraan utama. Diskusi yang diselenggarakan secara daring ini menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Dr. Latief Awaludin, pakar hukum dan politik Islam, juga pengurus Pimpinan Pusat Persis; Chusnul Mariyah, Ph.D., pengajar ilmu politik di FISIP UI, Drs. H. Muhammad Yamin, MH., Direktur Kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum (KKBH) Persis, Prof. Din Syamsudin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2015-2020, dan Prof. Asep Warlan Yusuf, guru besar hukum tata negara dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung. Tulisan inimerupakan rangkuman dari beberapa pernyataan penting dari para pembicara tersebut di atas yang diiringi refleksi sisipan dari penulis sendiri.
Tidak Adil dan Sewenang-wenang
Tampil sebagai pembicara pertama, Dr. Latief Awaludin menyampaikan bahwa peristiwa penembakan ini telah menyakiti rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Lebih jauh lagi, dalam perspektif hukum Islam, proses pembunuhan hanya bisa dibenarkan dalam dua kondisi, yaitu dalam kondisi perang dan dalam konteks vonis hukuman mati—yang tentu saja setelah melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 6 orang pengawal rombongan keluarga HRS ini merupakan tindakan kejahatan ketika nanti mampu dibuktikan di dalam persidangan. Oleh karena itu, proses pengusutan kasus ini harus dipimpin oleh tim independen.
Rasa keadilan yang dimaksud tersebut di atas tentu saja bisa kita kaitkan dengan konteks peristiwa penembakan ini. Peristiwa ini berawal dari proses pengintaian—yang menurut keterangan polisi adalah bagian dari proses penyelidikan—terhadap HRS yang didakwa telah melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam acara yang diselenggarakan di Petamburan yang menyebabkan terjadinya kerumunan—belakangan HRS juga didakwa dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Lalu, dimana kita menemukan rasa ketidakadilan? Kita akan menemukannya dengan membandingkan sikap aparat kepolisian terhadap keluarga dekat Presiden Joko Widodo yang juga menyebabkan timbulnya kerumuman dalam proses kampanye Pilkada—anaknya di Pilkada Walikota Solo dan menantunya di Pilkada Walikota Medan. Mengapa sikap yang sama tidak ditujukan pada dua kasus kerumunan tersebut? Mengapa ada tindakan yang berbeda? Terlepas dari konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak kepolisian, masyarakat tentu mampu merasakan sendiri bahwa perbedaan sikap ini telah menunjukan bahwa pemerintah telah berlaku tidak adil dalam menegakan hukum.
Mengapa HRS yang diusut dalam kasus pelanggaran kerumunan ini? Chusnul Mariyah memberikan penjelasan politiknya. Bagi salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu langsung pertama pada 2004 ini, insiden penembakan ini sangat kuat unsur politik (politically driven). Peristiwa ini, lanjut Chusnul, tidak bisa kita pisahkan dari rangkaian peristiwa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, baik aksi protes 411, 212, hingga Pilpres 2019 lalu. Memang, sebagaimana kita ketahui bersama, HRS menjadi salah satu sosok yang fenomenal dan berpengaruh dalam wacana dan aksi sosial-politik umat Islam setidaknya dalam lima tahun terakhir. Dia menjadi salah satu ikon ‘perlawanan’ dan ‘kritik’ terhadap rezim petahana hingga saat ini. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif politik, tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap HRS memang tidak semata-mata dilakukan atas dasar penegakan hukum itu sendiri. Ada unsur-unsur non-hukum yang melatarbelakangi, dan bisa jadi lebih dominan, dijadikannya HRS sebagai target.
Bagi Chusnul, dalam alam demokrasi, persoalan yang ada tidak hanya bisa dilihat dan ditangani dengan pendekatan hukum saja (legal-based approach), tetapi juga bisa dilakukan dengan pendekatan-politik kekuasaan (politic-based approach). Dalam kasus HRS ini kan jelas, lanjut Chusnul. HRS sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah atas dakwaan pelanggaran peraturan PSBB di Petamburan. Lalu mengapa masih dikejar? “Inilah mengapa saya tidak percaya—bahwa ini masalah, red.—hukum. Ini ada hubungannya dengan peristiwa 411, 212, dan hal-hal yang berkaitan.”
Sementara itu, Prof. Dr. Din Syamsudin menilai bahwa penembakan dan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) terhadap 6 orang pengawal HRS ini merupakan pelanggaran HAM berat. Tindakan tersebut, lanjut Din, harus kita kecam; siapapun pelaku dan korbannya; dari manapun organisasinya; apapun agamanya. Sehingga bagi Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode ini, ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan tersebut, maka hal ini menandakan adanya kedikatoran konstitusional (constitutional dictatorship) dan kepemimpinan yang rusak. Sayangnya, Din tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksud dengan dua hal tersebut. Apakah itu merujuk pada rezim petahana saat ini? Namun, Din kemudian berpesan agar umat Islam harus terus melakukan gerakan amar ma’ruf dan nahyi munkar yang dalam konteks kasus ini adalah dengan mengusut tuntas penembakan 6 orang ini.
Pembicara diskusi selanjutnya adalah Prof. Asep Warlan Yusuf. Prof. Asep mengawali pandangannya dengan menyampaikan tanggungjawab negara untuk menjalankan hukum. Dalam konteks ini, pemenuhan hak-hak asasi warga negara merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Di dalam masyarakat kita, lanjutnya, masih ada sebagian orang yang tidak tahu ketika hak-haknya dilanggar; atau ada yang tahu haknya dilanggar, tetapi tidak tahu bagaimana memperjuangkan agar hak-haknya bisa dipenuhi atau tidak dilanggar; ada juga yang tahu bagaimana memperjuangkannya tetapi tidak mampu. Ketidakmampuan ini, menurut hemat penulis, tentu saja bisa dipahami sebagai hambatan-hambatan yang seringkali berasal dari penegak hukum dan pemerintah itu sendiri. Ketidakmampuan seperti ini, lanjut Prof. Asep, dikhawatirkan akan membuat generasi selanjutnya takut memperjuangkan hak-hak tersebut.
Prof. Asep kemudian menyanyangkan tidak adanya—hingga acara diskusi ini berlangsung—satu patah katapun dari Presiden, sebagai personifikasi dari institusi negara, terkait insiden ini. Padahal, menurut penulis, respon masyarakat terhadap insiden ini begitu besar, dan memang aspek dugaan pelanggaran hukumnya juga berpotensi fatal. Oleh karena itu, lanjut Prof. Asep, kita perlu mengadakan dialog dengan Presiden untuk menegur sikapnya tersebut. “Ada potensi keterpecahan bangsa.” demikian prediksinya. Pria kelahiran Bandung ini juga mendukung dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang unsur-unsurnya telah mendapatkan kepercayaan publik. Jika pengusutan kasus ini tidak tuntas, Prof. Asep bahkan mengusulkan agar kita melibatkan lembaga-lembaga internasional untuk ikut terlibat, khususnya Organisasi Konferensi Internasional (OKI) yang memang merupakan lembaga internasional yang berkepentingan pada isu-isu umat Islam dari pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya. (Bersambung)