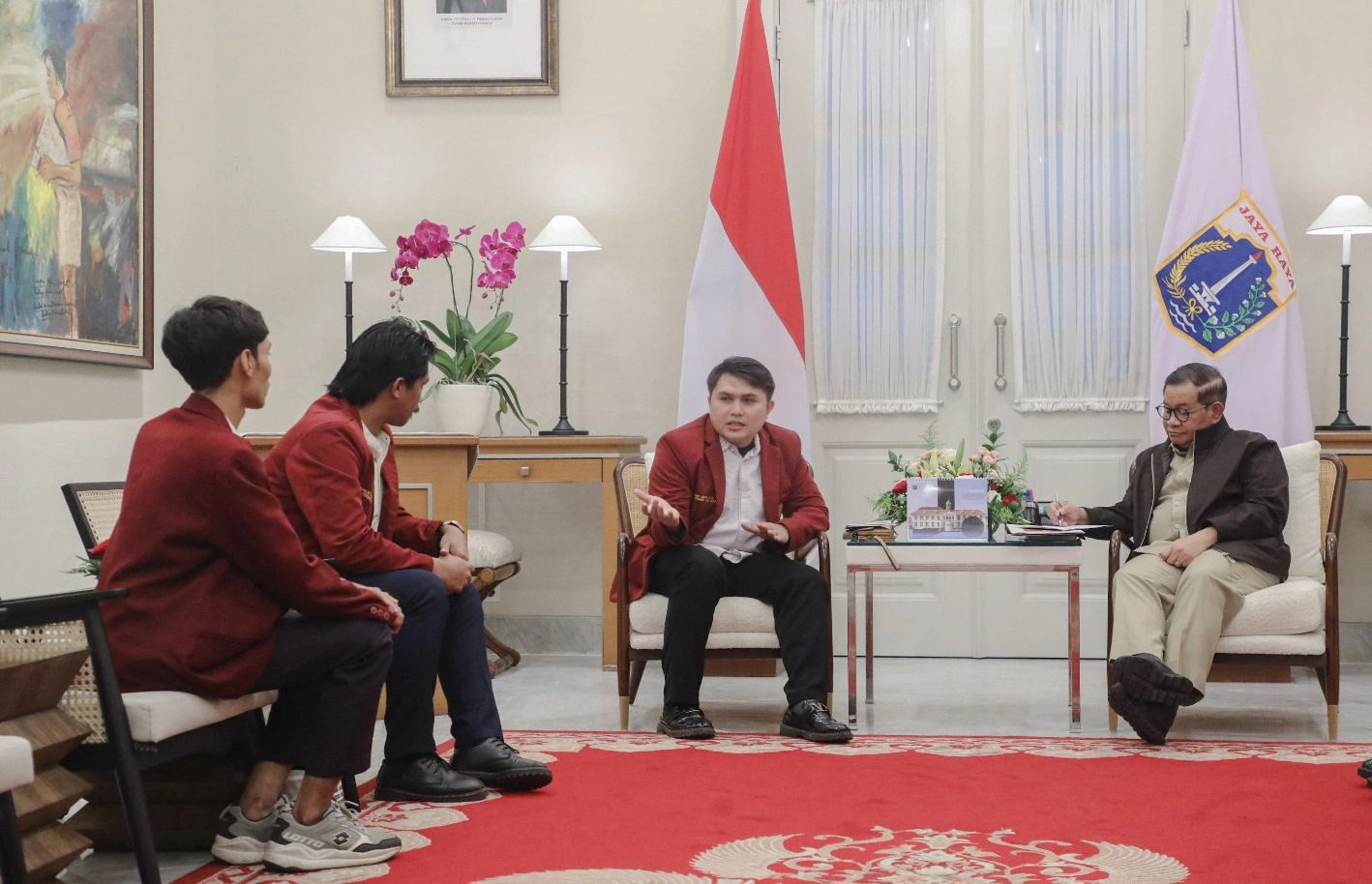Jikalau kita bertanya pada orang-orang tentang apa yang terjadi pada Ramadan hari ini, mungkin mereka semua akan serempak untuk menjawab; tak sedikitpun terlintas dalam fikiran, akan melalui bulan itu dengan situasi yang sangat sempit dan begitu himpit.
Bayangkan saja, datangnya Ramadan merupakan sesuatu yang paling ditunggu dan dinanti oleh segenap umat Islam. Bulan yang dijuluki sebagai mulkul asyhar ini memiliki berbagai macam keutamaan; Dari mulai pintu surga yang terbuka sangat luas, neraka yang tertutup rapat-rapat, sampai “tidur siang” yang bernilai ibadah. Semua keutamaan itu seolah menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum muslimin, di manapun mereka berada.
Apalagi ketika berbicara tentang Muslim Indonesia. Selain tertarik dengan pahala dari ritual Ibadah yang menggiurkan, umat Islam Indonesia terkadang lazim untuk melaksanakan tradisi-tradisi khusus untuk menyambut dan mengiringi rangkaian amalan pada bulan Ramadan. Eksisnya tradisi itu bak dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seolah, tanpa hal ini, Ramadan terasa hambar untuk dilalui.
Satu hari sebelum masuk Ramadan, biasanya masyarakat begitu riak bergembira dan menyambutnya dengan “makan bersama”. Dalam tradisi sunda, kegiatan ini terkenal dengan istilah “munggahan”. Ketika malam pertama selepas pelaksanaan tarawih, di belahan daerah lain mereka menyambutnya dengan pawai obor sambil berkeliling kampung. Sedangkan pada waktu sahur, sering terdengar teriakan “sahur…sahur” dari anak-anak muda yang bergema memecah keheningan.
Sambil menunggu waktu buka tiba, beberapa orang menghabiskan waktu dengan ngabuburit sambil hunting tempat terbaik untuk berbuka. Sebagian lagi berjalan-jalan atau menghabiskan waktu di luar. Selepas berbuka, mesjid ramai dikunjugi orang. Mereka melaksanakan shalat tarawih berjamaah dilanjutkan dengan tilawah bersama-sama. Begitulah, keadaannya terus seperti itu sampai bulan Ramadan benar-benar habis.
Beberapa hari sebelum Ramadan berakhir, masyarakat Indonesia begitu sibuk mempersiapkan perayaan idul fitri. Belanja barang-barang serba baru maupun bahan-bahan makanan menjadi aktifitas yang nampak mustahil untuk ditanggalkan. Bagi sebagian orang, mudik menjadi prioritas utama. Jika tidak, kumpul bersama sanak keluarga dan silaturahmi merupakan hal wajib yang mesti dilaksanakan.
Namun sayangnya kali ini benar-benar berbeda. Karena sebuah tragedi, bayangan pelaksanaan tradisi-tradisi Ramadan seperti di atas tampak seperti lamunan semata. Pandemi yang merebak di seantero negri membuat siapapun mesti berdiam di rumah, termasuk bagi orang-orang muslim yang sedang menjalani ibadah shaum.
Oleh karena itu, jangan sampai berfikir akan ada pemandangan takbir keliling, pawai obor, buka bersama, jalan-jalan sore ngabuburit maupun kegiatan pesantren kilat. Untuk melaksanakan tarawih dan tadarus berjamaah di masjid saja sudah dilarang. Pada akhirnya tradisi-tradisi Ramadan tak lagi bisa dilaksanakan seperti biasa, sehingga bagi sebagian orang malah membuat suasana Ramadan menjadi kurang menarik.
Tetapi, karena statusnya yang “kurang greget” untuk dilalui, setidaknya muncul dari fenomena itu beberapa pertanyaan mendasar; sebenarnya, apa yang menyebabkan kita selama ini begitu bersemangat untuk menyambut Ramadan? Apakah karena tradisi-tradisi khusus yang mengitarinya, atau justru memang karena bulan Ramadan sendiri memiliki banyak keutamaan?
Lalu, apabila kita melewati Ramadan dengan terlepas dari tradisi yang biasa dilaksanakan, mungkinkah kalimat marhaban ya Ramadan yang sering diucapkan dengan penuh semangat akan tetap bergema seperti Ramadan di tahun-tahun sebelumnya? Atau malah berkurang, kemudian merasa bulan ini tak istimewa layaknya bulan-bulan biasa saja? Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu setidaknya dapat menjadi renungan, untuk mengukur kadar keikhlasan ketika melalui hari-hari dalam bulan Ramadan selama ini.
Menguji Keikhlasan Lewat Situasi yang Tidak Menyenangkan.
Suatu ketika imam al-Ghazali pernah bercerita tentang penyesalannya, karena waktu itu pernah belajar dan mengajar dengan embel-embel materi ataupun kesenangan duniawi. Padahal, amalan yang Ia kerjakan merupakan amalan akhirat. Sebuah amal yang mestinya berbuah pahala besar apabila benar-benar dilakukan dengan penuh keikhlasan.
Curhatannya Ia tulis dalam munqidz mina dhalal. Mungkin karya itu mirip seperti autobiografi perjalanan intelektual pada masa sekarang. Setidaknya apa yang Ia ceritakan dapat memberi gambaran bahwa, bisa jadi amalan baik yang kita lakukan sehari-hari tidak benar-benar lillah, tapi ada maksud lain yang menjadi alasan untuk bersemangat dalam mengerjakannya.
Apa yang Imam al-Ghazali dahulu alami mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk selalu mempertahankan keikhlasan. Berat memang, tetapi harus diusahakan. Jika al-Ghazali pernah bersemangat mengajar karena menginginkan jabatan dan penghormatan, maka tanpa disadari, mungkin selama ini kita juga sering bersemangat untuk menyambut datangnya Ramadan karena serangkaian kegiatan yang mengitarinya, bukan karena esensi Ramadannya itu sendiri.
Apabila keadaannya sudah seperti itu, keikhlasan kita dalam menjalani syahru siyam benar-benar menjadi sorotan. Meski melalui Ramadan dengan minus tradisi, harusnya semangat dan sambutan kita tidak boleh berubah sama sekali. Seolah virus itu mempertegas kenapa bulan ini mesti ditunggu; bukan karena sensasi yang menyenangkan, tetapi untuk fokus beramal apapun keadaannya.
Oleh karena itu, walau sebagian besar masjid tidak mengadakan shalat tarawih, jangan sampai justru kita menjadi malas untuk shalat dengan alasan “tidak lagi berjama’ah”. Pun juga dengan khataman al-Quran. Ketika biasanya tadarus al-Quran menjadi agenda wajib yang dilakukan selepas tarawih berjama’ah, maka kegiatan itu harus tetap dilakukan, meski kembali tidak dilakukan secara bersama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Jika biasanya orang-orang ramai belajar Islam melalui pesantren kilat selama Ramadan, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk digelarnya kegiatan itu, maka jangan sampai kegiatan untuk mendalami ilmu agama berhenti begitu saja. Juga apabila kita sering menyisihkan sebagian harta, bershadaqah untuk memberi takjil berbuka puasa ke mesjid-mesjid, maka semangat memberi ini mesti terus dilakukan, meski dengan bentuk yang berbeda karena kebanyakan masjid tak lagi “buka”.
Keikhlasan dalam menjalani Ramadan juga dapat teruji dari aspek lain, seperti ketika kita berbicara tentang tema yang sensitif seperti “pendapatan materi”. Apabila biasanya di beberapa kota besar pendapatan para pemuka agama cenderung naik karena sering mengisi kajian, seminar maupun tarawihan, maka jangan sampai ada kata-kata keluhan yang keluar dari dalam lidah karena materi tak sebanyak seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Mengenai hal ini, mungkin patut kita bertanya, berintrospeksi dalam diri; apakah mungkin, selama ini kita senang ketika memasuki Ramadan karena job yang berlimpah-ruah? Tentu, semoga keadaannya tidak seperti itu.
Adanya pandemi ketika Ramadan tiba di satu sisi memang begitu mempersempit dan mempersulit kita dalam beribadah, tetapi dari sisi lain hal itu bisa berarti positif. Alasannya sangat sederhana; karena kesulitan akan selalu mengajarkan arti dari keikhlasan. Termasuk kesulitan dalam menjalani hari-hari di tengah ketakutan akan virus yang menyebar dengan begitu cepat.
Sekali lagi, berbicara tentang keikhlasan memang selalu berat untuk diamalkan. Namun bukan berarti mustahil untuk diusahakan. Jikalau memang suatu saat semangat kita menurun, sehingga banyak mengeluh karena tidak bisa “menikmati sensasi” dalam bulan ini, maka mungkin pertama kali yang mesti kita lakukan adalah, kembali meluruskan jarum hati untuk kembali ikhlas dan menerima, apapun kejadian yang telah Allah tetapkan dalam suratan-Nya.
*essai ditulis oleh Fachri Khoerudin