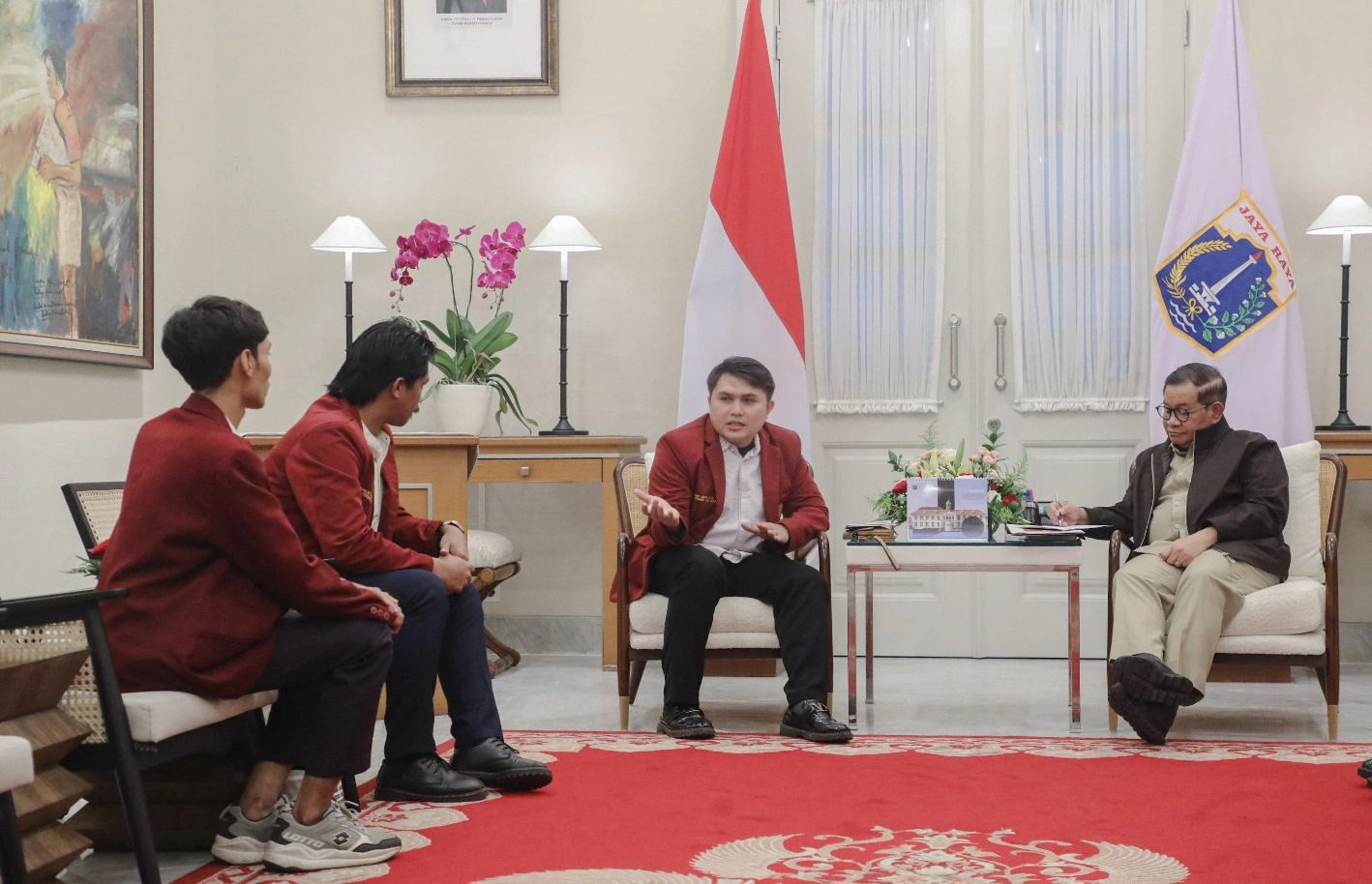Wacana disrupsi mulai popular ketika guru besar Harvard Business School, Clayton M. Christensen menulis sebuah buku pada tahun 1997 dengan judul “Innovatior Dilemma”. Buku tersebut menceritakan banyak hal tentang persaingan dalam dunia bisnis, terutama fenomena bagaimana perusahaan-perusahaan besar malah justru kalah oleh perusahaan-perusahaan kecil, padahal dengan kemampuan kapital yang tidak terbatas, mudah saja bagi perusahaan besar untuk mengalahkan ceceran perusahaan-perusahaan kecil. Bagi Cristensen ia memiliki jawaban sendiri, penyebabnya yaitu sebuah gelombang perubahan besar yang kini lebih dikenal dengan istilah disrupsi.
Selanjutnya Anthony Giddens menandai era disrupsi dengan liquiditas zaman, yaitu di mana semua kehidupan masyarakat mengalami ketiadaan bentuk, sifat, serta sulit untuk diprediksi perubahannya. Pada titik ini perubahan bersifat spontan dan massif, sehingga satu budaya dengan lainnya bisa saling meniadakan, mengadopsi, dan memodifikasi. Hal ini yang melatarbelakangi lahirnya budaya artificial, yaitu budaya yang lahir tanpa akar yang jelas sehingga cepat juga budaya tersebut hilang terganti oleh budaya rapuh lainnya. Dengan sifat liquiditas tersebut, semua hal menjadi cepat berubah dan menuntut manusia untuk selalu mendefinisikan ulang semua hal.
Berbeda dengan Giddens, Ulrick Beck memilih aspek perkembangan ekonomi yang menjadi penanda era disrupsi. Disrupsi adalah zaman di mana dunia didominasi oleh kecenderungan kapitalis dan gagasan kebebasan mutlak yang menjadi penyangganya. Pandangan Beck tersebut menggamparkan pemikiran monokausal dan linier. Budaya, politik, hingga sosial telah keliru dan secara nyata direduksi oleh kecenderungan syahwat kapital setiap individu. Dengan logika pasar yang hadir dalam setiap benak setiap individu, maka lahirlah masyarakat komoditas aktif, yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif untuk mengkomersialisasi apa pun, termasuk informasi, budaya bahkan agama.
Disrupsi dunia modern dipandang berperan dalam menafikan dimensi inner manusia. Hal ini membawa implikasi secara serius terhadap sisi-sisi kemanusiaan. Dengan kata lain angan-angan limpahan materi sebagai bagian dari ciri kebahagiaan mutlak kehidupan modern, ternyata tidak mampu memuaskan manusia seutuhnya. Dalam gemerlap modrnitas, diam-diam manusia mulai kehilangan kedamaian batin dan kesyahduan hidup.
Sesuatu yang hilang tersebut diidentifikasi dengan sebutan spiritual, alih-alih menggapai kehidupan paripurna, malah kekosongan yang dirasakan, padahal, dengan modernitas zaman, manusia justru telah mencapai keberlimpahan material. Fakta ini seolah mengajarkan betapa kebahagiaan yang selama ini manusia cari tidak terletak di sana, melainkan terletak di bagian yang lebih bersifat rohani, yaitu spiritual. Barangkali hal ini yang melatarbelakangi maraknya fenomena hijrah, modernitas zaman tidak lantas membuat manusia semakin jauh meninggalkan fitrahnya, malah justru melahirkan gelombang kesadaran, agar manusia mendefinisikan ulang tujuan kehidupannya masing-masing.
Untuk itu, kecenderungan spiritual sebagai fitrah manusia, tidak ubahnya seperti kampung halaman, sebagai tempat di mana individu pernah dibesarkan. Sejauhmana pun ia berpetualang, ia selalu merasa perlu untuk kembali pulang. Tak penting sejauh mana kehidupan ini telah berkembang, faktanya manusia selalu merasa perlu untuk kembali pada tempat di mana semuanya berawal. Lantas fa aina tadzhabuun.?
***
Penulis:
Dede Irawan
Pemuda Persis PC. Cileunyi
Mahawsiswa Program Doktor Kajian Media dan Agama, UIN Bandung.