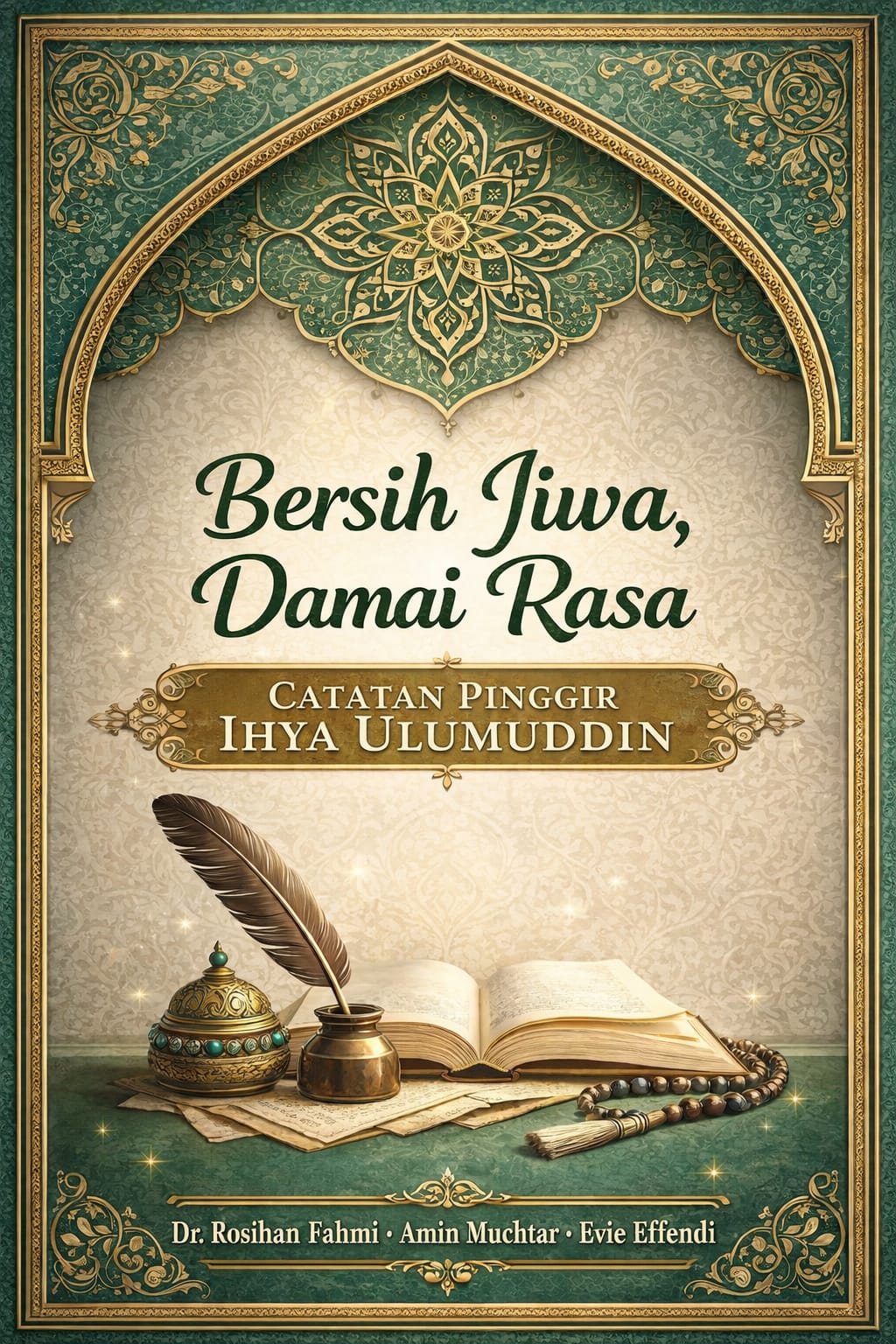Islam, Agama, dan Kebudayaan
Tiar Anwar Bachtiar
Pada tulisan sebelumnya kita sudah mendefinisikan kebudayaan sedemikian rupa. Pertanyaan selanjutnya yang penting untuk diajukan adalah bagaimana hubungan kebudayaan ini dengan agama? Dalam pengamatan antropolog, agama adalah salah satu produk dari kebudayaan. Dalam agama, terlihat ada sistem nilai tentang sesuatu yang dianggap “adikodrati” di luar diri manusia, lalu mewujud menjadi sistem ritual yang dimaksudkan agar manusia dapat berhubungan dengan kekuatan tersebut; terkadang diperlukan juga benda-benda tertentu untuk keperluan tersebut. Misalnya, orang-orang Islam membuat masjid, lalu sholat di dalamnya. Ketika ditanya kenapa mereka melakukan itu, jawabannya, “menyembah Allah Swt.” yang oleh umat Islam dianggap sebagai Tuhan Pencipta dan Pengatur kehidupan ini. Ini adalah perwujudan sempurna dari apa yang disebut sebagai “kebudayaan”. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila para peneliti itu melihat “Islam” sebagai “produk kebudayaan”; Islam adalah kebudayaan.
Pernyataan ini bisa benar bisa juga tidak bergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Agama (Islam), dalam keyakinan umat Islam dan dibuktikan dengan berbagai argumen, memiliki sumber ajaran yang menjadi petunjuk utama dalam menjalankan agama yang bukan merupakan produk pikiran dan perbuatan manusiawi. Sumber ini disebut “wahyu”. Wujudnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. yang kemudian dikodifikasi menjadi mushaf Al-Quran dan berjilid-jilid kitab riwayat Sunnah Nabi Saw. Sisi-sisi kemukjizatan dari kedua bentuk wahyu ini telah membuktikan bahwa keduanya berada di luar kemampuan manusia untuk mewujudkannya. Butuh seuatu kekuatan adikodrati yang dapat mengadakan wahyu ini. Kesanggupan manusia tidak sampai ke sana. Wahyu bukanlah ide dan produk simbolik manusia. Di antara cirinya yang paling jelas hingga saat ini adalah kemampuan wahyu ini untuk tidak mengalami perubahan. Padahal tidak ada kebudayaan di dunia ini yang tidak mengalami perubahan. Ciri utama kebudayaan adalah karakternya yang selalu berubah. Selain itu, banyak ide dan pengetahuan yang jauh melampaui zamannya. Zaman itu belum ada sains yang ditemukan tentang tahap-tahap penciptaan manusia di dalam perut ibu, tapi Al-Quran dan hadis Nabi Saw. sudah dapat menceritakan itu dengan detail. Ini tentu bukan merupakan produk normal manusia. Zaman itu juga belum berkembang ilmu geologi yang meneliti gunung-gunung, tapi Al-Quran sudah berbicara tentang karakter gunung yang baru diketahui lebih dari seribu tahun sesudah kedatangan Al-Quran. Berbagai contoh kasus semacam ini diurai dengan sangat baik, luas, dan mendalam dalam kajian tentang kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. (I’jâz Al-Qur’ân wa As-Sunnah).
Bagi yang tidak mempercayai wahyu sebagai berasal dari Allah Swt. akan menganggap bahwa wahyu tetaplah produk manusia, berasal dari perkataan dan perbuatan Muhammad. Kemukjizatan yang tampak dari wahyu dianggap hanya sebagai keyakinan subjektif umat Islam, bukan dianggap sebagai hal yang objektif. Padalah bila mau sedikit membuka hati dan pikiran, serta jujur terhadap ilmu yang benar, maka penolakan terhadap wahyu sebagai semata pikiran Muhammad seharusnya tidak terjadi. Kalau wahyu itu pikiran Muhammad, seharusnya ada proses kultural yang menungkinkan Muhammad Saw. memiliki pengetahuan sehebat dan sedalam apa yang ada di dalam Al-Quran. Semua bukti sejarah tentang masa lalu Muhammad Saw. sebelum menjadi Nabi mengarah pada kesimpulan bahwa Muhammad Saw. tidak pernah mengikuti program belajar apapun dan kepada siapapun selain aktivitas mengembala, berdagang, dan menjalani kehidupan sebagai anak yatim awam biasa. Seharusnya secara kultural, tidak mungkin Muhammad Saw. sepandai itu saat telah menerima wahyu dari Allah Swt. Akan tetapi, bila hati sudah tertutup penolakan terhadap agama Allah Swt. sulit untuk dapat menerima kenyataan atas kemukjizatan wahyu Allah Swt. ini.
Dari segi Al-Quran sebagai Kalam Allah Swt. yang disampaikan kepada Rasul-Nya, maka agama (Islam) bersifat non-kebudayaan. Akan tetapi, wujud wahyu yang berupa gagasan (petunjuk, perintah, larangan, pengabaran baik-buruk, balasan surga-neraka, kisah penurut dan pembangkang, dan bentuk gagasan lainnya) pada tahap interaksinya dengan manusia akan mempengaruhi cara berpikir manusia yang meyakininya. Pada tahap inilah tidak menutup kemungkinan bersama dengan wahyu ini ada terselip pikiran-pikiran manusia. Misalnya, ketika Allah Swt. memerintahkan untuk sholat. Manusia lantas berpikir bagaimana sholat itu dilakukan. Ada petunjuk praktis yang jelas dan terang-benderang seperti shalat wajib lima waktu, menghadap ke kiblat, mengangkat tangan sewaktu takbir, membaca Al-Fatihah, dan seterusnya hingga diakhiri dengan salam. Praktik itu diajarkan oleh Rasulullah Saw. secara langsung berdasarkan petunjuk Allah Swt. tanpa melibatkan pikiran manusia dalam hal bentuk-bentuk perbuatan dan do’a-do’a yang dibaca. Hal semacam ini tidak diragukan lagi bahwa unsur wahyu non-kebudayaannya sangat kuat. Akan tetapi, ada sebagain praktik lain yang tidak diberikan penjelasan detail dalam wahyu. Misalnya saat diperintahkan untuk menutup aurat, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Wahyu yang bukan kebudayaan membincangkan mengenai batas-batas aurat. Ada perdebatan “fiqih” yang bersumber dari perbedaan informasi dan pemahaman atas sumber informasi tersebut. Ikhtilaf-nya adalah bagian dari pengaruh kemanusiaan, akan tetapi bahwa sumber topik yang dibicarakan tersebut adalah wahyu tidak diragukan. Oleh sebab itu, boleh dikatakan bahwa batas-batas aurat adalah urusan wahyu untuk pertama kalinya. Selanjutnya, tidak ada keterangan dengan apa aurat harus ditutup. Hal yang dibiarkan semacam ini akan menjadi bagian dari peran dan pengaruh kebudayaan. Oleh sebab itu, kita akan menemukan perbedaan cara-cara orang menutup aurat dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu zaman ke zaman lain. Tidak diragukan pula bahwa bagian semacam ini membentuk suatu “budaya Islam” yang khas di berbagai tempat. Sejauh sebagai produk kebudayaan, cara-cara menutup aurat akan mengikuti perubahan-perubahan kebudayaan sebagaimana layaknya suatu kebudayaan.
Dalam hal ini, wahyu yang non-kebudayaan itu berfungsi ikut membentuk dan mengarahkan budaya manusia. Dengan begitu, kata sifat “Islam” di belakang kebudayaan (kebudayaan Islam) memiliki makna yang ajeg sepanjang sejarah, yaitu suatu kebudayaan yang dalam pembentukan dan pembinaannya diarahkan oleh “wahyu” sebagai sumber pokok agama dalam Islam. Kebudayaan ini bukan bermakna semata-mata kebudayaan yang diciptakan oleh orang yang “mengaku Islam”. Sekalipun yang menciptakan kebudayaan ini orang yang mengaku Islam, tetapi kalau secara prinsip bertentangan dengan agama (Islam), kebudayaan tersebut bukan merupakan kebudayaan Islam. Misalnya ada komunitas manusia yang mengaku Muslim, tetapi mereka memiliki tradisi bertransaksi utang-piutang secara ribawi. Contohnya praktik meminjam padi pada masa lalu di masyarakat Sunda-Muslim. Biasanya bila ada kebutuhan mendesak, seseorang akan meminjam padi yang tersimpan di leuit (lumbung) sebagai tabungan masyarakat selepas panen. Saat mengembalikannya adalah pada waktu panen musim mendatang. Akan tetapi kalau meminjam 1 ton, harus dikembalikan dengan kelebihan tertentu yang disepakati misalnya 1,2 ton. Walaupun mereka Muslim, praktik semacam ini dianggap suatu kewajaran yang biasa, sekalipun Islam mengategorikannya sebagai “riba” yang diharamkan. Praktik budaya semacam ini, walaupun dilakukan oleh masyarakat Muslim, tetapi bukan merupakan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam, selain dipraktikkan oleh kaum Muslim, juga harus dibentuk dengan pengaruh wahyu Allah Swt.
BACA JUGA:Mengenal Identitas Kebudayaan (Bagian Satu)