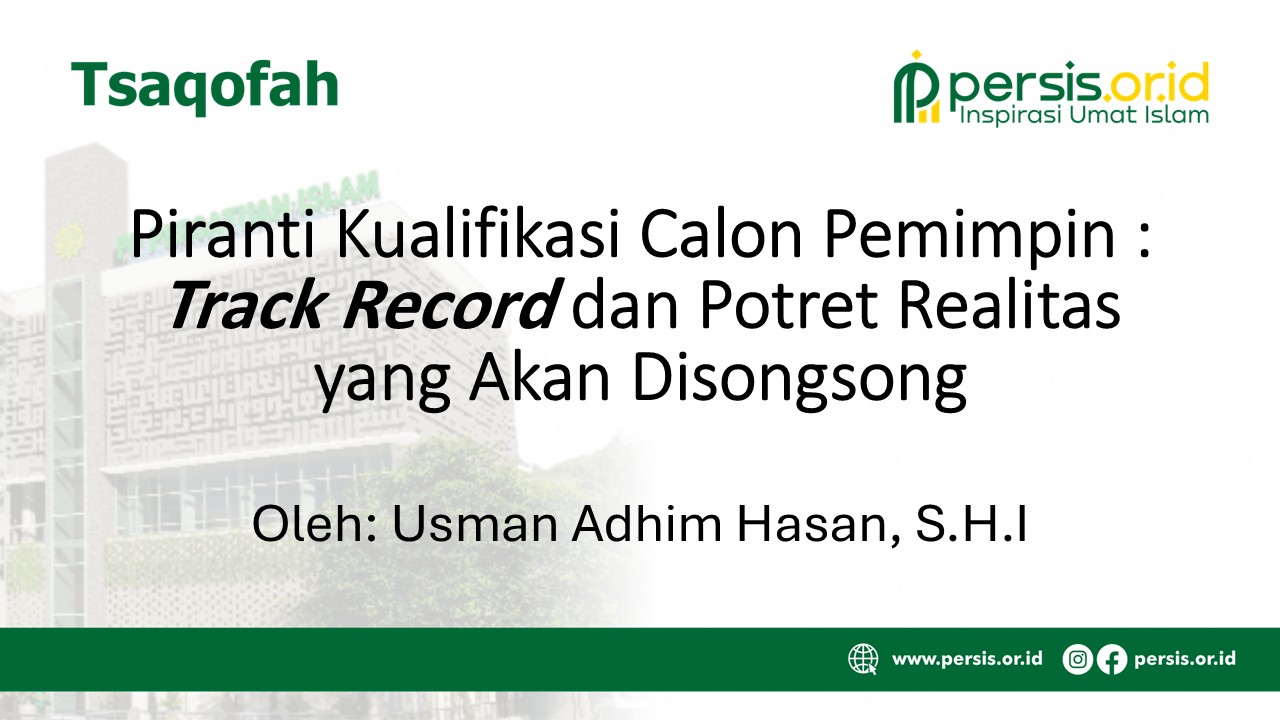PILKADA DIPILIH RAKYAT LEBIH MERAKYAT DIBANDING DIPILIH DPRD
Disusun oleh Dr. Muslim Mufti. MSi
Bidgar Siyasah dan Kebijakan Publik
Demokrasi memiliki dua dimensi yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, yaitu dimensi substansial (pemerintahan rakyat) dan dimensi prosedural (proses pemilihan). Dalam kaitanya dengan persoalan substansial posisi rakyat menjadi sangat sentral, atau menentukan, itulah sebabnya kesadaran politik masyarakat menjadi sangat penting dalam memberi arah dari demokrasi itu sendiri.tingkat kesadaran politik masyarakat yang dalam studi perilaku pemilih diidentifikasi sebagai rasionalitas pemilih menjadi kata kunci dari perwujudan demokrasi substansial tersebut. Ketika pemilih masih terkungkung oleh berbagai aspek yang menjadikan dirinya tidak independen atau otonom dalam menentukan pilihanya dapat dipastikan kualitas demokrasi mengalami persoalan. Itulah sebabnya Samuel P. Huntington menekankan perlunya authonomous participation (partisipasi otonom) bagi pemilih, bukan sebaliknya sebuah partisipasi yang dimobilisasi. Dalam prakteknya tidak jarang partisipasi politik masyarakat begitu tinggi tetapi secara kualitas sebenarnya sangat rendah, karena yang terjadi bukan partisipasi otonom, tetapi partisipasi yang dimobilisasi. Kenyataan demikian, terjadi selama pemerintahan Orde Baru yang tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 80 persen, tetapi dalam prosesnya otonomi pemilih menjadi tanda tanya. Meskipun dalam pemilu-pemilu selama pemerintahan Orde Baru diberlakukan azas luber (langsung, umum, bebas dan rahasia), tetapi dalam prakteknya tidak ada kebebasan memilih, terutama bagi rakyat kecil di pedesaan yang senantisa dapat ditekan oleh aparat pemerintah. Pemilih tidak memiliki otonomi untuk menentukan pilihan politiknya sesuai dengan yang diyakini. Dalam konteks demokrasi yang lebih luas, pada era tersebut dapat dikatakan sebagai demokrasi minus kebebasan politik, sehingga yang muncul adalah sebuah partisipasi yang dimobilisasi, sebuah demokrasi tanpa kontestasi.
Disamping persoalan substansi terdapat aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan pemerintahan oleh rakyat (government by the people) dan pemerintah untuk rakyat (government for the people) tersebut, yaitu penyelenggaraan proses pemilihan itu sendiri. Dalam hal ini menyangkut perencanaan kegiatan, sosialisasi kebijakan dan pelaksana dan pengawasnya itu sendiri. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan pilkada 2029, nampaknya Pilkada dikembalikan ke DPRD akan dikembalikan, dengan pilkada melalui perwakilan ini sangat membutuhkan pengkajian dan analisis secara akademik dan fakta-fakta dilapangan.
Berangkat dari pra anggapan bahwa demokrasi analog dengan pasar, dimana para kandidat tersebut berupaya untuk memperjuangkan kepentinganatau aspirasi politiknya. Agar dalam memperjuangkan kepentingan tersebut lebih nyaman, lebih manusiawi, maka berbagai fasilitas pendukung untuk penyampaian aspirasi tersebut disediakan.
Demokrasi merupakan miniatur ruang publik, yang fungsinya untuk menekan, memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui pembentukan opini publik. Melalui miniatur ruang publik ini, rakyat dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan yang penting bagi rakyat, sehingga makna demokrasi tidak sekedar government by the people, tetapi juga goverment for the people. Demokrasi tidak hanya dapat didefinisikan sebagai pemerintah oleh rakyat (government by the people) tetapi juga, dalam rumusan Presiden Abraham Lincoln yang sangat terkenal, sebagai pemerintah untuk rakyat (government for the people) yaitu, pemerintah yang selaras dengan pilihan rakyat. Kepentingan rakyat harus menjadi pemandu bagi proses dan output kebijakan publik, yang diputuskan oleh elite-elite politik baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Relasi rakyat yang diwakili dan pejabat publik yang mewakili harus berada dalam kerangka hubungan yang kondusif bagi semakin akuntablenya kebijakan publik yang dihasilkan. Bukan sebuah relasi dominasi sebagaimana dalam sistem otoritarian atau masyarakat feodal, tetapi relasi egaliter yang memungkinkan bagi proses deliberasi antara rakyat dan pejabat publik.
Asumsi-asumsi teoritik tersebut sejalan dengan penjelasan David Held (2007) tentang demokrasi sebagai “mekanisme yang memungkinkan diterimanya keinginan-keinginan rakyat biasa, sambil mempercayakan pembuatan kebijakan publik yang sebenarnya kepada segelintir orang yang berpengalaman dan memenuhi syarat.”[1] Artinya dalam relasi yang egaliter tersebut, rakyat biasa juga dapat menyampaikan keinginan-keinginannya,sehingga proses politik yang terjadi tidak tergelincir dalam mekanisme elitis, yang hanya melibatkan beberapa orang saja. Dengan demikian, diperlukan instrumen politik yang di satu sisi dapat menjembatasi hubungan rakyat dan elite, di sisi lain mengeliminasi berbagai kecenderungan elitis tersebut. Instrumen tersebut dapat berupa kelengkapan teknologi komunikasi, dapat pula berupa “ruang publik” sebagai sarana penyampaian aspirasi secara terbuka.
Sebuah pemerintah demokrasi yang ideal adalah sebuah negara yang tindakan-tindakannya selalu dalam keselarasan yang sempurna dengan keinginan seluruh rakyatnya. Pemerintah dengan responsivitas yang sempurna tersebut belum pernah ada dan mungkin tidak akan pernah dapat dicapai, tapi bentuk tersebut dapat menjadi sebuah cita-cita bagi rezim demokrasi. Pemerintah ideal tersebut juga dapat dianggap sebagai sebuah ukuran tingkat responsivitas demokrasi dibanding dengan berbagai rezim yang lain. Suatu kharakteristik kunci dari demokrasi adalah kontinuitas pertanggung jawaban dari pemerintah terhadap preferensi dari warga negara, dengan pertimbangan selama adanya kesederajatan politik.[2] Demokrasi disamping untuk meningkatkan responsivitas pejabat publik, juga merupakan sarana kontrol kekuasaan, agar kebijakan-kebijakan yang diproduksi menjadi lebih akuntable.
Menjadikan pemerintahan responsif dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah menempatkan para pengambil keputusan selalu dalam suasana terkontrol oleh publik. Suara-suara publik harus senantiasa hadir di ruang-ruang parlemen. Pemerintaha daerah tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri dalam memproses kebijakan publik yang diperuntukkan bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Itulah sebabnya, kehadiran rakyat di dalam pemilihan menjadi sebuah keniscayaan. Pemisahan rakyat dari parlemen, akan berdampak pada semakin jauhnya suara rakyat dari proses pengambilan keputusan di parlemen. Sebuah gejala yang dapat mengarah pada demokrasi elitis, atau oligarkhi partai politik, karena dalam sistem demokrasi partai politik memegang peran yang sangat penting dan menentukan.
David Betham dan Kevin Boyle menyatakan bahwa betapapun baiknya niat penguasa, jika mereka menafikan pengaruh atau kendali rakyat, maka ada dua kemungkinan buruk yang terjadi. Pertama, kebijakan-kebijakan mereka (penguasa) tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat, dan kemungkinan kedua, yang lebih buruk, yaitu kebijakan-kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa itu sendiri.[3]
Pernyataan David Betham dan Kevin Boyle mempertegas bahwa dalam sistem politik demokrasi, aspirasi rakyat tidak dapat dinafikan. Rakyat harus diberikan ruang kebebasan yang lebih luas untuk bebas menyampaikan keinginan-keinginan politiknya. Ruang publik yang diperlukan bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi politik, tetapi juga menjadi alat kontrol publik, ketika ruang publik yang ada juga merupakan arena bagi bertemunya berbagai kepentingan untuk kemudian mengemuka menjadi opini publik. Meskipun dalam hal efektifitas peran opini publik sebagai alat kontrol kebijakan publik akan sangat bergantung pada media massa dan moralitas pejabat publik itu sendiri. Moralitas penyelenggara negara akan menentukan komitmen dan kepedulian para pejabat publik untuk mendengar suara rakyat. Semakin tinggi tingkat moralitas pejabat publik semakin tinggi pula kepedulian dan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Maswadi Rauf menjelaskan tentang dua konsep dasar yang menjadi prioritas dalam mendefinisikan demokrasi, yakni kebebasan/ persamaan (freedom/equality) dan kedaulatan rakyat. Dua konsep dasar ini menjadi indikator utama dalam membangun demokrasi.[4] Konsep kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia melahirkan beberapa persyaratan yang penekanannya pada individu, persetujuan sebagai dasar dalam hubungan antar-manusia, persamaan semua manusia, keanekaragaman, hak suara yang luas, dan kebebasan berbicara dan berkumpul. Konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, rule of law, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala, dan kompetitif, pemerintah yang tergabung pada parlemen, dan pengadilan bebas.[5]
Dalam kaitanya dengan konsep kebebasan dan kesetaraan, akan menjadi persoalan ketika porsi yang diberikan tidak berada dalam keseimbangan yang tepat. Kebebasan akan dapat mengarah pada persaingan yang kurang sehat, dan ketika model demokrasi yang dikembangkan lebih mengarah pada demokrasi pluralis, maka munculnya kecenderungan elitis akan menguat. Beberapa individu yang memiliki keunggulan akan menjadi pemenang dan mengalahkan yang lain, seperti biasanya individu-individu tersebut adalah orang-orang yang memiliki modal sosial jauh lebih besar dari yang lain. Pada titik inilah kemudian kebebasan yang berlebihan menjadi sarana menuju demokrasi elitis, yang sebenarnya telah bergeser dari watak dasar demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, ketika penekanan lebih besar pada aspek kesetaraan, dapat membatasi beberapa individu potensial yang sangat diperlukan bagi tumbuhnya kreativitas. Tanpa kreativitas sulit dibayangkan, akan terjadi inovasi dan pembaharuan, yang terjadi biasanya sebuah involusi dan stagnasi, seperti yang terjadi di Uni Soviet.
Dalam perspektif demokrasi deliberatif dijelaskan bahwa keputusan politik yang rasional dan baik setidaknya harus peduli kepentingan rakyat, berorientasi ke masa depan dan mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Apabila tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut akan berakibat pada kegagalan dalam pengambilan keputusan politik[6] Sebagaimana Habermas jelaskan, suatu konsensus dapat dianggap rasional, jika para peserta komunikasi dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim-klaim kesahihan tersebut secara bebas dan tanpa paksaaan.[7] Artinya suara banyak orang yang berpartisipasi dalam ruang publik harus menjadi pertimbangan utama dalam proses-proses pengambilan keputusan yang penting bagi publik itu sendiri. Deliberasi akan gagal dicapai apabila para pihak yang menjalankan memiliki agenda tersembunyi (hidden agenda), yang bertentangan dengan kepentingan publik. Sebagaimana dijelaskan Harbermas yang dikutip Pip Jones, bahwa ; “pihak-pihak yang saling berkomunikasi memiliki kesempatan yang setara untuk menyatakan pandangan mereka, selama mereka memperlakukan satu sama lain secara setara dan dengan jujur untuk mencapai kesepakatan, yang tidak mungkin kalau pertukaran berat sebelah atau di balik keinginan untuk bersepakat itu ada kecurangan.”[8] Penjelasan tersebut identik dengan konsep “pasar sempurna” dalam teori ekonomi, yang sangat diperlukan dalam mencapai tingkat kemakmuran bersama. Sebuah kondisi di mana proses pertukaran terjadi tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk para pemilik usaha melalui pembentukan kartel, atau mempraktekkan monopoli dan oligopoli.
Ketika pluralitas merupakan sebuah keniscayaan, di mana negara ditempatkan sebagai pasar politik yang menjaring permintaan kelompok-kelompok dan individu yang bersaing, maka akan segera muncul persoalan siapa yang harus diprioritaskan yang dianggap mewakili orang banyak tersebut. Dalam hal tersebut, Arend Lijphart menemukan adanya perbedaan cara pandang tentang pengertian kepentingan orang banyak tersebut, yang masing-masing diwakili oleh pendukung atau penganut model demokrasi mayoritarian dan model demokrasi konsensus. Para pendukung model demokrasi mayoritas memandang kepentingan orang banyak sebagai suara mayoritas, sedangkan pendukung model demokrasi konsensus memandang kepentingan orang banyak sebagai kepentingan individu-individu secara keseluruhan. Itulah sebabnya dalam model mayoritarian, pemenang suara mayoritas berhak mengklaim sebagai yang mewakili kepentingan orang banyak dan merealisasikan program-program politiknya atas nama kepentingan orang banyak tersebut. Sebaliknya dalam model konsensus, negara diidentikan sebagai suatu pasar politik yang menjaring permintaan kelompok-kelompok dan individu yang bersaing. Artinya kepentingan orang banyak dimaknai sebagai kepentingan kelompok-kelompok dan individu-individu yang berkompetisi dalam suatu tatanan demokrasi yang pluralistik.[9]
[1] Lihat, David Held, Models of Democracy, (Jakarta: The Akbar Tandjung Institute, 2007), hal.163.
[2] Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven: Yale University Press, 1971), hal. 1.
[3] David Betham & Kevin Boyle, David Betham & Kevin Boyle, 2000, Demokrasi: 80 Tanya Jawab, Yogyakarta: Kanisius, hal. 25.
[4] Maswadi Rauf, 1997, Teori Demokrasi dan Demokratisasi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Salemba Raya 6, hal. 5.
[5] Ibid, hal.5.
[6] David Held, op.cit, hal. 273.
[7] Lihat, F.Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam teori Diskursus Jurgen Habermas, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 37.
[8] Lihat, Pip Jones, Pengantar Teori-teori Sosial : Dari Fungsionalisme Hingga Post Modernisme, (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2009), hal. 238.
[9] David Held, op.cit, hal 185. Juga, Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik :Penelusuran Paradigma (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 262.
BACA JUGA:Sekolah Ristek HIMA PERSIS Jakarta Gandeng DPRD DKI Tingkatkan Kualitas SDM Kampus Swasta