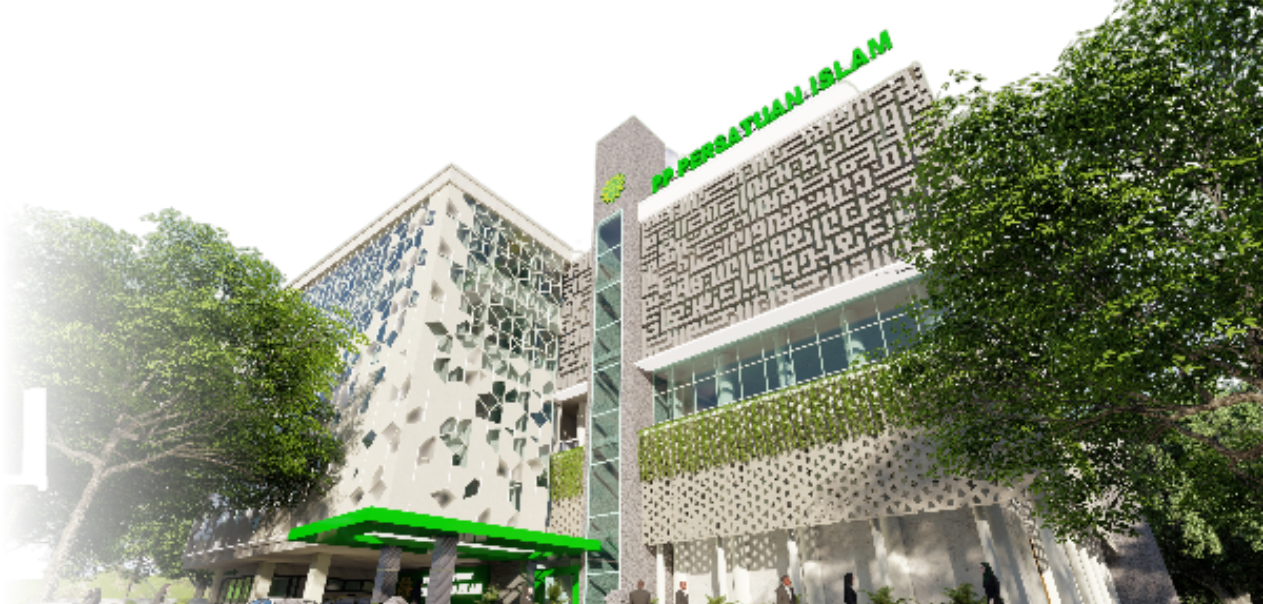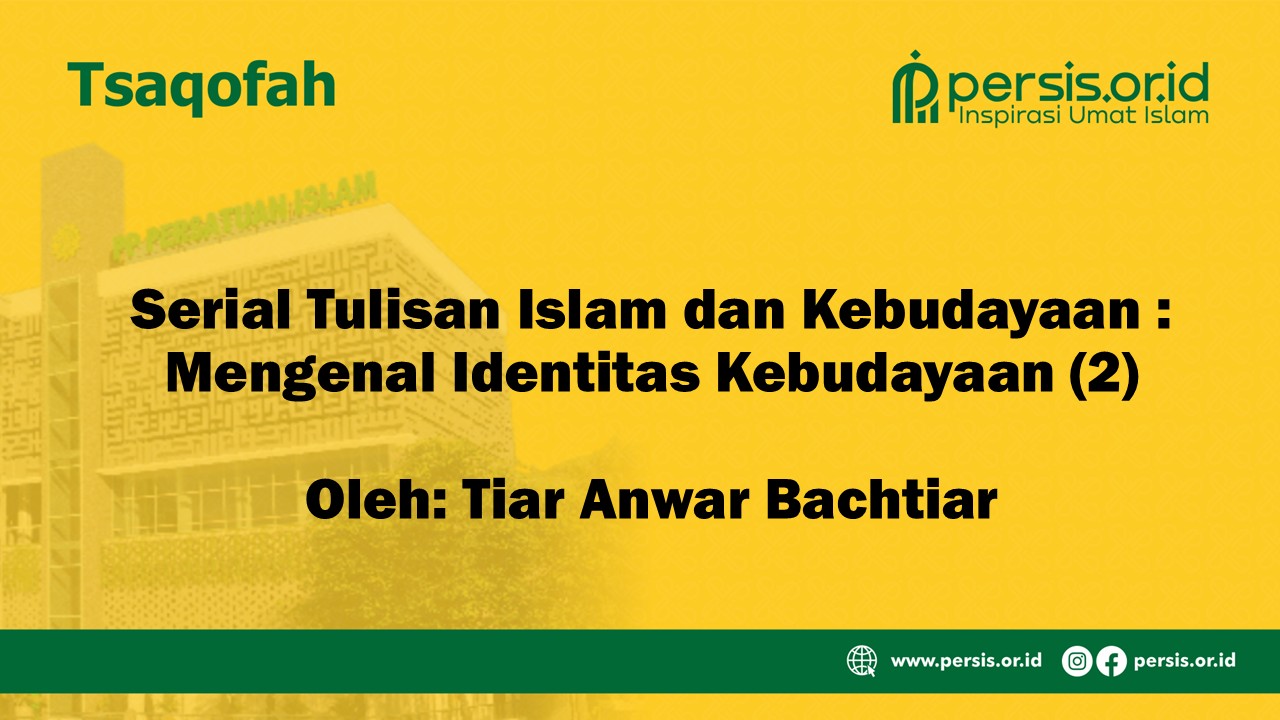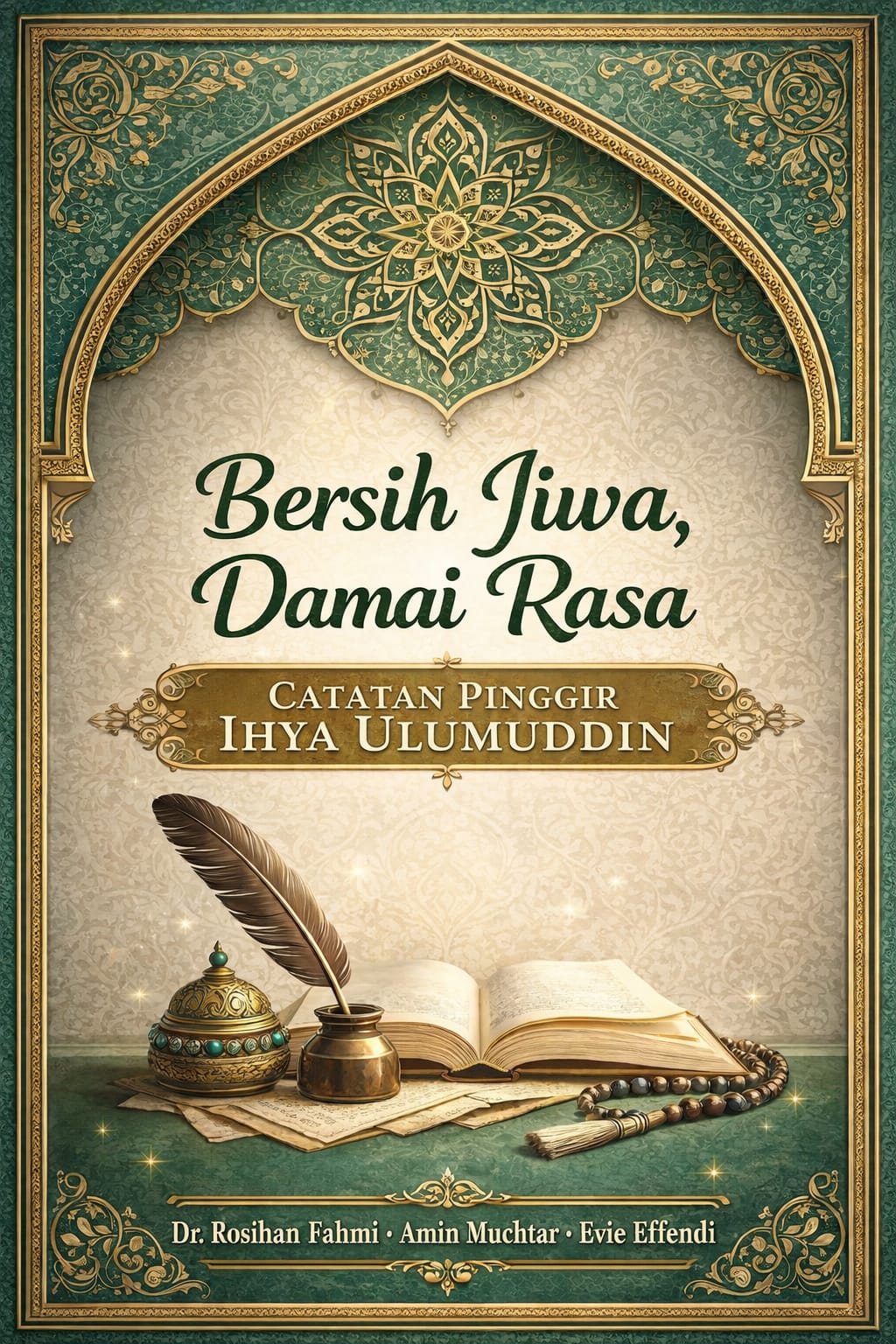Posisi wahyu sebagai unsur dasar pembentuk budaya Islam diafirmasi oleh Rasulullah Saw. sendiri dalam sabdanya, “Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak.” (HR Ahmad). Nabi Saw. adalah pembawa wahyu. Dengan wahyu yang dibawanya, ia bertugas untuk menyempurnakan perilaku manusia. Kata “akhlaq” dalam definisi yang dikenal dalam tradisi Islam adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang dari sana ia melakukan suatu perbuatan sadar yang bersifat spontan, tanpa pertimbangan dan pikiran panjang terlebih dahulu. Artinya akhlak itu menunjukkan sesuatu yang telah menjadi karakter seseorang dan menjadi dasar bagi perbuatan-perbuatannya. Istilah “akhlak” ini sangat relevan dengan kebudayaan yang bertumpu pada perilaku manusia yang telah menjadi karakter sehingga mudah dikerjakan secara berulang-ulang hingga membentuk kebiasaan (tradisi) bersama. Kebiasaan berulang-ulang dalam suatu komunitas inilah yang menjadi “kebudayaan” suatu masyarakat yang sumbernya adalah perilaku manusia pendukung kebudayaan tersebut.
Agama tidak berperan sebagai pembentuk perilaku manusia dari nol, melainkan menyempurnakan. Maknanya, manusia dengan bekal pikirannya dapat menentukan sendiri apa yang harus diperbuatnya. Agar perbuatan tersebut sempurna dan selalu berjalan dalam fitrah terbaik manusia, maka agama datang untuk menyempurnakan prosesnya. Contohnya dalam hal makanan. Karena manusia membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya, maka secara naluriah manusia akan mencari apa yang dapat dimakan di sekitarnya. Di pegunungan penuh hutan rimba, pemukimnya akan mencari tumbuhan atau hewan yang bisa dimakan. Ditemukanlah umbi-umbian hutan seperti gadung, dedauan, buah-buahan, dan berbagai hewan liar di hutan seperti ayam hutan, menjangan, babi hutan, dan sebagainya. Di pedesaan yang sudah mulai mengolah alam menjadi berbagai barang kebutuhan menyiapkan makanannya sendiri seperti menanam padi, sayuran, buah-buahan, dan memelihara sendiri sumber protein hewani seperti ikan, ayam, kambing, sapi, daan sebagainya. Di perkotaan orang menyiapkan banyak dana untuk membeli bahan makanan dari pedesaan. Begitulah seterusnya sampai masing-masing memiliki kebiasaan sendiri yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan makanan mereka untuk bertahan hidup. Di mana peran agama dalam hal ini? Agama berperan menyempurnakan prosesnya. Agama mengingatkan tentang fitrah manusia yang hanya dapat menerima makanan ke dalam tubuhnya yang halal dan thayyib. Keduanya berkaitan dengan pertumbuhan jasad dan ruh manusia. Makanan yang haram (non-halal) akan merusak tubuh dan ruh, sedangkan makanan non-thayyib adalah makanan yang akan merugikan kesehatan karena mengandung unsur yang buruk secara gizi. Dalam hal makanan ini sesungguhnya adalah masalah prinsip karena berkenaan dengan fitrah dasar penciptaan manusia. Bila ini diikuti, maka proses pemenuhan manusia atas kebutuhan makanannya akan sempurna sesuai dengan tuntutan asal penciptaan manusia itu sendiri.
Agama (Islam) tentu punya rasionalisasi atas apa yang ditawarkannya, bukan melulu doktrin tanpa alasan. Oleh sebab itu, di dalam perkembangan pengkajian ajaran Islam berkembang pengungkapan rasional atas setiap ajaran Islam yang disebut sebagai hikmah (hikmatut-tasyrî’). Sekalipun berpengaruhnya agama terhadap masyarakat tidak selalu harus membutuhkan alasan rasional semacam ini, namun pengungkapan hikmah ini secara kebudayaan menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki potensi yang kuat untuk menjadi basis terbangunnya suatu kebudayaan yang khas, bahkan dapat dikembangkan terus sampai pada level peradaban unggul dan maju karena sudah memiliki perangkat keilmuan yang kokoh.
Agama (Islam) beroperasi pada level gagasan sebagaimana kita ketahui dari sifat sumber ajaran agama ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. Dalam konteks kebudayaan, karakter dasar agama semacam ini langsung menyentuh pada aspek terdalam dari kebudayaan, yaitu “pikiran” yang membentuk sistem makna bagi suatu bangunan kebudayaan. Karena sifatnya yang seacam ini, ketika Islam mempengaruhi kebudayaan bukan hanya sebagai aksesoris dan tempelan, tapi membangun basis dalam berkebudayaan. Islam bagi kebudayaan tidak bersifat ornamental, melainkan fundamental. Islam membentuk untuk pertama kalinya worldview yang darinya segala realitas diproyeksikan. Ornamentasi kebudayaan Islam dapat berbeda dalam banyak hal dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kelompok kebudayaan ke kelompok yang lain; akan tetapi basis dasar pemaknaan dan rasionalisasinya memiliki kesamaan karena dibentuk oleh sumber yang sama, tetap, dan tidak berubah. Inilah sifat “penyempurnaan” Islam atas kebudayaan.
Karena sifat menempelnya agama (Islam) ke dalam kebudayaan semacam itu, maka Islam memiliki karakter shalih likulli zaman wa makân; bisa disesuaikan dengan kebudayaan di tempat mana saja di dunia dan pada kurun waktu kapan saja hingga hari kiamat. Ornamentasi kebudayaan di berbagai tempat tidak akan terganggu dengan kehadiran Islam selama memenuhi tuntutan prinsip “kesempurnaan” yang terkandung dalam ajaran Islam. Orang Arab boleh tetap menggunakan gamis sebagai pakaian keseharian yang dianggap paling sesuai dengan tuntutan lingkungan dan kebudayaannya sepanjang dapat menutup aurat dan tidak digunakan dengan kesombongan. Prinsip ini juga berlaku bagi orang Jawa yang lebih memilih kain lurik dan batik, bukan gamis. Bisa jadi, faktor ini pula yang menyebabkan Islam mudah diterima dan kuat dipegang sepanjang masa di berbagai kelompok kebudayaan.
BACA JUGA:Mengenal Identitas Kebudayaan (Bagian Satu)