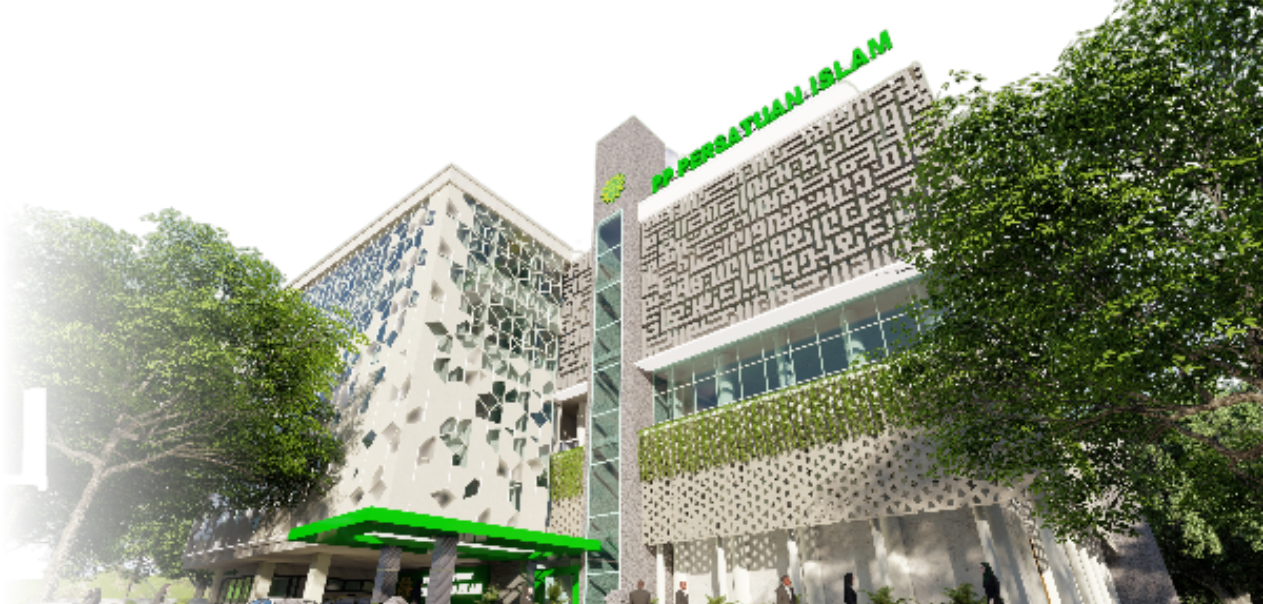Perubahan dan Rekayasa Kebudayaan
Tiar Anwar Bachtiar
Topik selanjutnya yang penting untuk diperbincangkan adalah tentang perubahan kebudayaan dan bagaimana kita dapat memungkinkan melakukan rekayasa terhadap kebudayaan agar sesuai dengan visi yang diinginkan oleh pelaku budaya. Bagian ini sangat penting apabila dikaitkan dengan Islam sebagai agama dakwah. Visi kedatangan Islam adalah melakukan perubahan perilaku manusia agar sesuai dengan tuntutan dan kehendak Allah Swt. (da’wah ilallâh). Perubahan kebudayaan menjadi salah satu yang niscaya sebagai bagian di dalamnya. Nanti dalam penjelasan bagian ini, kita akan memotret fenomena ideal bagaimana gagasan wahyu yang turun dari Allah Swt. secara efektif dapat mengubah kebudayaan masyarakat Jahiliyyah di tangan Rasulullah Saw., dan selanjutnya juga sangat kuat memengaruhi perubahan kebudayaan manusia lain di berbagai belahan dunia.
Kita akan memulai pembahasan dari paradoks-paradoks budaya. Budaya itu paling tidak memiliki empat paradoks. Pertama, di satu sisi budaya itu meneruskan apa yang sebelumnya sudah ada, tapi pada saat yang sama mengalami perubahan (continuous but changed). Kedua, di satu sisi budaya itu terikat oleh tempat aturan dan lainnya, tapi pada saat yang sama terus bergerak keluar dari ikatan-ikatan tersebut sehingga menimbulkan hal baru (bounded but mobile). Ketiga, di satu sisi budaya itu merupakan konsensus dan kesepakatan di antara para pendukungnya, tetapi pada saat yang sama terjadi kontestasi dalam berbagai unsurnya (concensual but contested). Keempat, di satu sisi kebudayaan itu memiliki unsur-unsur yang sama antara satu kebudayaan dengan yang lain, tapi pada saat yang sama memiliki variasi-variasi (shared but varies).
Karena paradoks-paradoks budaya memang nyata adanya seperti itu, maka selalu saja ada hal-hal yang berubah sebagai ciri utama dari kebudayaan, walaupun perubahan itu masih seputar hal-hal yang tetap yang terwariskan dari masa-masa sebelumnya. Misalnya, manusia sejak dahulu “berpakaian” sebagai kebutuhan kultural dari kehidupannya. Akan tetapi, bentuk pakaian ada perubahan-perubahan dan variasi-variasinya. Ada pakaian dari kulit kayu, kulit binatang, dedaunan, dan semisalnya. Ada bentuk pakaian terusan, celana, kemeja, dan lainnya. Semua perubahan dan variasi itu tetap masih berporos pada satu hal yang sama, yaitu “pakaian”. Belum ditemukan ada manusia yang sepenuhnya sepanjang hidup tidak berpakaian, walaupun ada orang yang mengaku “nudis” (kaum telanjang). Kaum nudis ini hanya dalam waktu-waktu tertentu saja bertelanjang. Selebihnya tetap berpakaian; bahkan lebih banyak berpakaiannya dibandingkan telanjangnya. Kekuasaan dalam relasi antar-manusia adalah hal yang niscaya dan tetap adanya. Akan tetapi, bagaimana bentuk relasi kekuasaan kemungkinan berbeda-beda dari zaman ke zaman atau dari satu kawasan ke kawasan lainnya; ada kekuasaan tribal di masyarakat sederhana, ada kerajaan, ada imperium, ada republik, dan sebagainya. Variasi-variasi tersebut tetap mengacu kepada hal yang sama, yaitu “kekuasaan” (relasi kuasa). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa perubahan-perubahan kebudayaan bukanlah sesuatu bersifat arbitrer (mana suka) tanpa pola. Perubahan selalu berporos pada hal-hal yang sudah tetap sebelumnya. Artinya, ada yang tidak berubah dari waktu ke waktu di tengah perubahan-perubahan yang terjadi.
Lalu bagaimana perubahan terjadi dalam kebudayaan? Berdasarkan teori-teori umum kebudayaan berubah karena faktor-faktor antara lain: bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, terjadinya pemberontakan atau revolusi, peperangan, kejadian-kejadian alam seperti banjir, gunung meletus, dan lainnya, serta pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pandangan semacam ini tentu bersifat fenomenologis; melihat perubahan dari relasi satu fenomena dengan fenomena lain yang tampak. Pandangan fenomenologis semacam ini akan bermakna apabila analisis dilanjutkan pada penggalian hal-hal yang menggerakkan fenomena tersebut, karena dalam pendekatan ini, setiap fenomena akan digerakkan oleh sesuatu yang ada di belakangnya (noumena). Inilah yang dikaji oleh para ahli kebudayaan pada tahap yang lebih mendalam, yaitu berusaha menemukan apa faktor utama yang menggerakkan tumbuhnya suatu kebudayaan dan perubahan yang terjadi padanya.
Kita ambil salah satu contoh tentang bertambahnya penduduk dapat menyebabkan terjadinya perubaan kebudayaan. Dalam pandangan yang kasat mata, kita dapat menyaksikan perbedaan sebuah kawasan dengan penduduk padat dan penduduk jarang. Kawasan padat bisa jadi dahulunya adalah kawasan yang jarang penduduknya. Karena di kawasan itu ada industri atau pusat keramaian lainnya, jadilah kawasan yang tadinya sepi penduduk menjadi ramai oleh pendatang. Bertambahnya jumlah penduduk sendiri akan mengubah pola kebiasaan hidup di kawasan tersebut; belum lagi ditambah pendatang baru yang membawa budaya lain dari tempat asalnya. Sewaktu penduduk masih sedikit, air dan sampah bukan masalah serius. Air tanah yang ada bisa jadi melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampah juga cukup dikubur dan dibakar. Masalah selesai. Ketika penduduk bertambah mau tidak mau harus ada pola baru memenuhi kebutuhan air warga. Air tanah mungkin sudah tidak lagi memadai. Perlu manajemen khusus pengelolaan air dari sumber yang lebih memadai. Mungkin akan muncul budaya baru memenuhi kebutuhan air: membayar air setiap bulan ke Perusahaan penyedia air. Demikian juga dengan sampah. Situasi ini memaksa masyarakat untuk memiliki “kebudayaan” baru mengelola sampah seperti mengolektifkan sampah kepada petugas kebersihan. Jika kebudayaan lama masih dipakai sangat mungkin akan terjadi kesemrawutan kawasan.
Fenomena yang tampak memang demikian. Akan tetapi bila ditelisik lebih mendalam akan muncul pertanyaan: mengapa orang-orang berpindah ke kawasan itu? mengapa melola air harus dikelola dengan model perusahaan? mengapa harus memakai manajeman dalam mengelola sampah? Dari manakah ilmu manajemen itu? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan mengarahkan jawabannya pada “pola pikir” yang mendorong manusia melakukan sesuatu, karena kebudayaan memang merupakan agregasi dari pikiran (what we think), tindakan (what we do), dan karya bendawi (what we make). Oleh sebab itu, tindakan-tindakan yang terlihat dan benda-benda yang dihasilkan oleh manusia pasti akan berasas pada pikiran tertentu. Begitu pula perubahan. Perubahan pola pembuatan rumah di kawasan yang semakin padat, perubahan perilaku karena semakin banyaknya penduduk, mengindikasikan adanya pola pikir dan mentalitas yang berubah. Dengan demikian untuk menjelaskan perubahan dalam kebudayaan harus juga melibatkan perubahan-perubahan pikiran, ide, gagasan, baik berupa norma, nilai, ideologi, maupun worldview. Akan tetapi, perubahan pola pikir ini sampai dari satu orang ke orang lain melalui wasilah yang bersifat fenomenologis. Pikiran baru tidak akan muncul, misalnya, bila tidak ada seorang berilmu yang menyampaikan ilmu tersebut, baik dalam sebuah forum, lembaga, atau interaksi simbolik lainnya. Gagasan baru juga tidak akan terlampau banyak digubris apabila tidak terlihat bagaimana gagasan itu mewujud dalam tindakan dan belum terlihat hasil bendawi dari gagasan tersebut. Oleh sebab itu, faktor-faktor perubahan dalam kebudayaan tidak dapat dipisahkan antara yang simbolik-fenomenologis dengan ideasional-maknawi.
Di manakah terkumpulnya kedua hal tersebut secara utuh dan bersamaan? Ada pada manusia dan tindakannya. Manusia adalah sosok lengkap yang dapat mewadahi gagasan dan simbolisasinya. Simbolisasi makna, ide, gagasan, pikiran, dan semua unsur dalaman dari suatu budaya dapat sepenuhnya dilakukan oleh manusia dalam bentuk tindakan dan penciptaan kriya-bendawi. Kebudayaan memang hakikatnya berbicara tentang manusia, bukan tentang sesuatu di luar manusia. Misalnya, mengaitkan terjadinya perubahan “perilaku manusia” akibat munculnya “teknologi” sebetulnya suatu pengaitan kausal yang cacat. Teknologi tidak pernah menjadi entitas otonom dalam suatu kontinum kebudayaan. Teknologi hanyalah ekses dari tindakan manusia juga. Sehingga yang sesungguhnya terjadi adalah: perubahan “perilaku manusia” disebabkan oleh “tindakan manusia” lainnya. Dari manusia kepada manusia, lalu timbul perubahan pada manusia juga.
Perhatikan pernyataan Allah Swt. dalam Al-Quran bahwa “sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum hingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS Ar-Ra’d [13]: 11). Allah mengaitkan perubahan-perubahan kebudayaan secara langsung dengan perilaku manusia. “Apa yang ada pada suatu kaum (ما بقوم)”adalah budaya karena menyangkut suatu yang menjadi milik komunitas (kaum). Perubahan pada komunitas itu hanya akan terjadi dengan perubahan individual pada anfus (pribadi-pribadi) dalam komunitas tersebut. Dengan kata lain, perubahan kebudayaan hanya akan terjadi ketika manusianya berubah. Sebab, pada manusia-lah seluruh unsur-unsur kebudayaan terinstalasi secara lengkap dan sempurna, bukan pada hal-hal lain di luar manusia.
Tidak mengherankan bila selanjutnya Allah Swt. yang mengutus para nabi untuk mengubah kebiasaan dan perilaku manusia adalah dengan perintah “dakwah” (QS An-Nahl [16]: 125] yang artinya “mengajak” kepada manusia. Dakwah bukanlah gedung-gedung megah menjulang tinggi bernama masjid, kantor, atau kelas. Dakwah juga bukan aula atau lapangan yang luas. Semua itu bisa sama sekali tidak memiliki arti bagi perubahan ketika unsur “ajakan” dari “manusia” kepada “manusia” tidak ada. Dakwah pun bukan “organisasi” yang terstruktur, walaupun banyak orang yang berdakwah dengan mengorganisasikan diri mereka secara baik dan rapi. Organisasi menjadi sama sekali tidak ada gunanya bila sudah tidak lagi ada fungsi “ajakan” dari “manusia” kepada “manusia”.
Metode utama yang paling relevan sepanjang zaman agar proses perubahan perilaku langsung pada tujuan intinya adalah dengan menciptakan “uswatun hasanah” (teladan terbaik). Oleh sebab itu, utusan-utusan Allah Swt. terlebih dahulu oleh Allah Swt. dijadikan sebagai uswatun hasanah. (QS Al-Ahzab [33]: 21). Selanjutnya mereka menjalankan tugas “mengajak” dengan hikmah (ilmu yang benar), nasihat yang baik, dan diskusi. Dengan menjadikan para Nabi ini sebagai “teladan”, maka proses perubahan mad’û menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Bila “ajakan” tidak disertai “teladan”, maka ajakan itu hanya akan berhenti pada perbincangan belaka, tidak akan berfungsi dalam melakukan perubahan kebudayaan secara fundamental. Mengapa begitu?
Jawabannya kembali lagi kepada karakter kebudayaan. Kebudayaan akan dipahami dan ditangkap dengan baik apabila direpresentasikan secara utuh, baik unsur intrinsik berupa makna dan gagasan maupun unsur simboliknya berupa tindakan dan karya. Sebagian kegagalan besar dalam dakwah adalah ketika pesan hanya direpresentasikan dalam bentuk narasi gagasan sehingga audiens (mad’û) tidak dapat menangkapnya secara utuh, karena sisa serpihan lainnya terdapat dalam narasi tindakan dan karya yang tidak terepresentasikan. Dalam istilah Arab disebut tindakan dan karya disebut sebagai lisân al-hal (narasi realitas). Padahal, narasi realitas (lisân al-hâl) ini justru memiliki kemampuan menggambarkan kebudayaan lebih baik dan lebih kuat dibandingkan narasi gagasan (lisân al-maqâl). Dalam pepatah Arab dikenal ungkapan. “Narasi tindakan lebih fasih daripada narasi ucapan” (لسان الحال أفصح من لسان المقال).
Dalam kenyataan di lapangan, kebudayaan itu akan cepat berubah dengan tindakan-tindakan nyata terlebih dahulu, sekalipun narasi gagasan disampaikan belakangan. Dahulu ketika Suharto ingin mengubah budaya bertani tradisional masyarakat dengan menerjunkan penyuluh-penyuluh pertanian yang terjun ke lapangan. Penyuluh tidak hanya dibekali tugas menyampaikan teori-teori pertanian baru kepada masyarakat. Para penyuluh ini ditugaskan untuk membuat lokasi pertanian percontohan (demplot) sambil memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaiman pertanian modern dijalankan. Ketika demplot yang dibuat oleh penyuluh hasilnya lebih bagus daripada yang dihasilkan petani, dengan mudah para petani mengikutinya. Hanya dalam kurun waktu 20 hingga 30-an budaya bertani orang Indonesia berubah seperti yang diinginkan Suharto. Apa yang diinginkan Suharto untuk melakukan swasembada pangan pun dapat terwujud sejak tahun 1995. Ini adalah best practice yang dapat disaksikan di Indonesia tentang bagaimana suatu perubahan kebudayaan yang direncanakan relatif berhasil dilakukan.
Setelah Reformasi, pertanian Indonesia tidak lagi memiliki visi yang jelas. Definisi “pertanian” modern yang dijalankan petani hari ini sesungguhnya sudah tidak lagi relevan dengan zaman yang sedang dihadapi para petani hari ini. Sayangnya, tidak ada lagi usaha kultural mengarahkan kembali para petani untuk melakukan lagi perubahan budaya menghadapi tantangan baru. Akibat gagal transformasi budaya pertanian di zaman ini banyak petani yang sudah tidak dapat lagi mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pertanian pun akhirnya menjadi ruang kultural bernilai rendah yang kian kemari kian ditinggalkan oleh masyarakat. Belum lagi ruang kultural yang tersisa pun semakin hancur oleh kepentingan oligarkhi produsen pupuk sintetis, produsen benih, dan pengimpor pangan yang hanya peduli pada keuntungan pribadi semata. Semakin rusaknya ruang budaya pertanian ini menyebabkan lahan-lahan pertanian banyak ditinggalkan. Masih agak beruntung difungsikan sebagai pemukiman. Sisanya terbiarkan tidak termanfaatkan sama sekali, karena petani tua pension sedangkan generasi muda tidak tertarik untuk bertani.
Di atas hanya contoh bagaimana perubahan kebudayaan terjadi. Pada kasus yang sangat jelas dalam konteks dakwah Islam terjadi pada dakwah Nabi Saw. Hanya dalam kurun waktu 23 tahun, masyarakat Jahiliyah berubah kebudayaannya dari segi keyakinan dan kepercayaan (agama). Penyembahan kepada berhala sebagai sumber segala kerusakan budaya pada masa Jahiliyah di Arab dapat digantikan dengan penyembahan pada Allah Swt. Lambat laun penyembahan kepada Alah Swt. (Tauhid) dapat mengarahkan umat Muhammad Saw. kepada perubahan-perubahan aspek kebudayaan lain dalam kehidupannya hingga lahirlah peradaban Islam.
Keberhasilan dakwah Rasulullah Saw. faktor utamanya adalah keteladanan, contoh nyata dalam perilaku keseharian yang disaksikan bersama oleh masyarakat. Rasulullah Saw. dalah hal menyampaikan pesan gagasan termasuk irit narasi lisan. Beliau diberi kemampuan jawâmi’ul kalim, mampu meringkas pesan yang luas dengan kalimat yang pendek-pendek. Hasilnya adalah hadis-hadis Nabi Saw. yang rata-rata berisi penjelasan pendek-pendek, terutama yang berupa perkataan Rasulullah Saw. Begitu juga Al-Quran yang berisi samudera ilmu tidak bertepi disampaikan dengan kalimat-kalimat yang ringkas tapi bernas.
Narasi lisan secara sengaja dilakukan tidak terlalu Panjang, karena ini bukan satu-satunya medium untuk menyampaikan pesan perubahan kepada masyarakat. Rasulullah Saw. lebih banyak mengandalkan keteladanan dalam segala hal. Beliau menjadi uswah hasanah sehingga muncul lain selain narasi lisan, yaitu narasi tindakan dan karya nyata. Dengan lebih dominannya narasi tindakan daripada narasi lisan, penangkapan pesan perubahan dapat diterima secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih utuh; apalagi dilengkapi dengan narasi lisan yang bernas. Itulah mengapa dakwah Islam di tangan Nabi Saw. dapat tersebar dan diterima dengan cepat; tentu sambil tidak menafikan kehendak Allah Swt. dalam semua proses ini.
Para da’i mandiri, gerakan-gerakan dakwah, dan lembaga-lembaga dakwah hendaknya memahami tabiat perubahan ini agar ketika merencanakan dakwah akan mengacu ke sana. Dakwah jangan terjebak hanya pada retorika dan media belaka. Dakwah mesti mendahulukan aspek keteladanan; setelah itu baru soal penyampaian pesan. Oleh sebab itu, pendidikan calon da’i harus menjadi perhatian utama. Kurikulumnya pun harus lebih menekankan pada aspek pembentukan kepribadian calon da’i agar lebih dahulu menjadi teladan untuk masyarakat nantinya. Ilmu-ilmu agama yang dipelajari oleh calon da’i harus lebih dahulu dipraktikkan dalam kehidupannya sebelum disampaikan kepada khalayak. Pendidikan da’i bukan kursus retorika dan public speaking. Pendidikan da’i adalah penempaan keilmuan yang benar, keadaban, dan amal shalih dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan da’i bukanlah fakultas dakwah di sebuah universitas, melainkan suatu pendidikan terencana secara integral dalam pembentukan manusia-manusia uswatun hasanah.
Da’i yang pada dirinya terintegrasi gagasan dan praktik akan mudah untuk melakukan penetrasi budaya karena apa yang menjadi tuntutan tabiat budaya dan perubahannya dipenuhi. Akan tetapi, karena suatu budaya baru akan bertemu dengan budaya lama, maka kemungkinan diterima atau ditolak oleh pelaku budaya lama dapat saja terjadi bergantung pada kondisi hatinya. Walaupun demikian, dengan representasi paripurna dalam menyampaikan dakwah melalui lisan dan perbuatan, dimungkinkan pesan dapat ditangkap lebih utuh dan lebih berpengaruh sangat besar dibandingkan bila hanya disampaikan secara lisan. Dengan penyampaian yang utuh, pada masa datang ketika hati mad’û dalam keadaan penuh kesadaran, pesan dakwah paripurna akan berbekas kuat dalam dirinya.
BACA JUGA:Mengenal Identitas Kebudayaan (Bagian Satu)