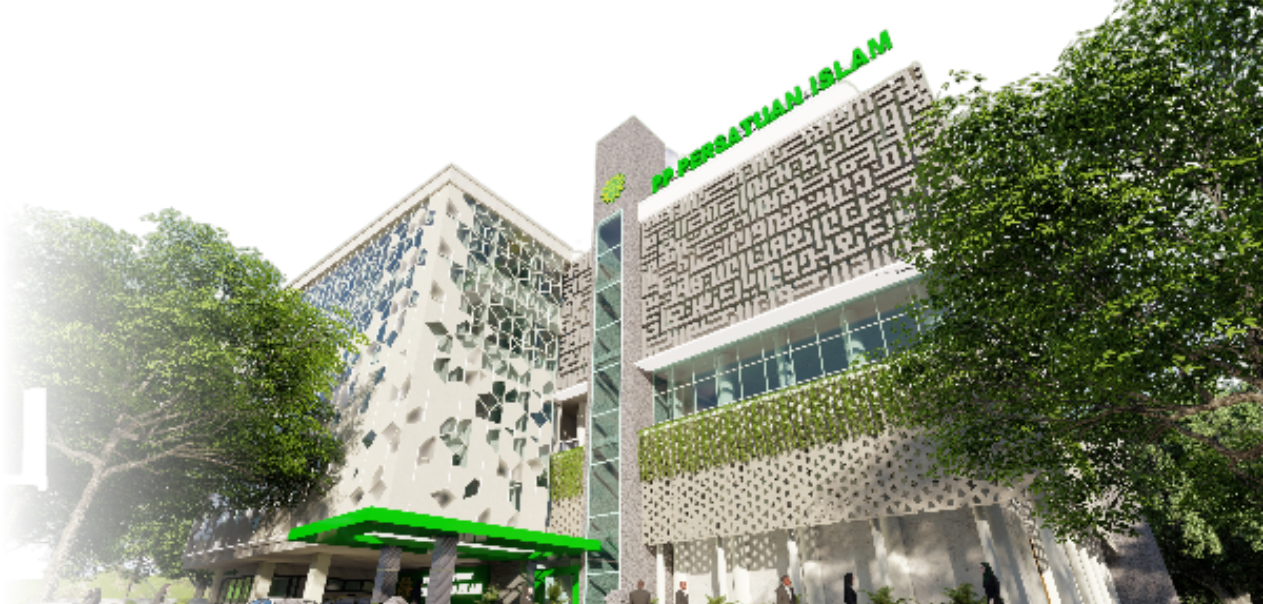Kepahlawanan, Nasionalisme, dan Islam dalam Sejarah Indonesia
Tiar Anwar Bachtiar
Setiap tanggal 10 November Presiden Indonesia selama bertahun-tahun sejak ditetapkannya tanggal ini sebagai hari pahlawan mengumumumkan siapa-siapa saja yang layak untuk menyandang gelar “pahlawan” secara resmi dari negara. Setiap tahun jumlah pahlawan terus bertambah karena pengajuan dari berbagai daerah terus berjalan. Sepertinya semakin banyak daerah, ormas, dan kelompok masyarakat tertentu yang ingin mengajukan tokohnya sebagai pahlawan nasional.
Mungkin sebagain orang yang berpikir kritis akan bertanya mengapa begitu banyak orang ditetapkan sebagai pahlawan? Apa sesungguhnya kepentingannya bagi negara? Secara sederhana pertanyaan ini dapat dijawab dengan menggunakan sudut pandang kepentingan nasionalisme Indonesia yang merupakan kekuatan ideologi yang memungkinkan terbentuknya negara ini. Sebagai negara yang terbentuk dari kekuatan nasionalisme ini, maka negara memerlukan berbagai anasir yang dapat memelihara dan memperkuat nasionalisme keindonesiaan ini. Salah satu yang cukup penting dilakukan adalah dengan mengakui tokoh-tokoh penting tertentu dalam sejarah sebagai “pahlawan”. Melalui proses penelaahaan berbagai sisi, baik historis maupun kepentingan politis-ideologis, tokoh tersebut akan ditetapkan sebagai orang yang layak menjadi pahlawan. Artinya, sosok tersebut layak untuk menjadi panutan bagi masyarakat dalam konteks kesetiaannya pada negara dan sumbangsihnya dalam membangun negara ini. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan contoh hidup bahwa negara ini layak untuk terus dipertahankan seperti dicontohkan oleh para pahlawan itu. Melalui contoh hidup inilah masyarakat akan semakin kuat pikirannya untuk mendukung keberadaan “Indonesia” sebagai negara. Semakin kuat dukungan rakyat, maka negara akan semakin kuat, karena rakyat akan semakin sukarela untuk membela eksistensi negara ini dari berbagai ancaman keruntuhannya.
Tidak ada alasan lain yang lebih mendasar dari penganugerahan gelar pahlawan dari sudut pandang negara selain hal di atas. Sebab, suatu negara model nation-state seperti Indonesia tidak memiliki kekuatan politik yang memaksa rakyatnya untuk setia dan patuh pada negara selain”kesadaran” mereka sendiri. Di dalam negara nasional (nation-state) sudah tidak dikenal lagi kekuatan penyangga suatu negara yang didasarkan pada kekuatan dinasti-dinasti tertentu yang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan politiknya melalui ekspansi militer atas kekuatan dinasti yang lain seperti pada masa-masa kerajaan dahulu. Pada masa lalu, di kawasan ini memang sudah pernah berdiri berbagai “negara-kerajaan” yang pembentukan kekuasaan politiknya semata-mata didasarkan pada kekuatan politik dinasti tertentu. Biasanya dinasti yang berkuasa ini adalah dinasti yang sanggup mengalahkan dinasti-dinasti lain di berbagai kawasan sehingga dapat membentuk suatu kekuasaan yang lebih besar. Semakin banyak penguasa-penguasa di berbagai daerah yang ditaklukkan, maka kerajaan itu akan semakin besar dan semakin kuat. Runtuhnya kerajaan itupun disebabkan dinasti penyangganya sudah tidak mampu lagi mempertahankan kekuatannya di hadapan kekuatan politik dinasti yang lain. Itulah yang dialami kerajaan-kerajaan di Indonesia yang akhirnya harus tumbang semua bertekuk lutut di hadapan kekuatan kerajaan Belanda. Belanda akhirnya menjadikan kerajaan-kerajaan taklukannya menjadi bagian dari Kerajaan Belanda dengan sebutan Netherland Indie (Hinda Belanda).
Sistem “negara-kerajaan” (monarkhi) seperti itu adalah sistem yang berlaku di seluruh dunia selama puluhan abad. Bahkan, kekhalifahan Islam sepeninggal Khulafaur-Rasyidin pun memilih untuk menggunakan sistem monarkhi ini untuk membangun kekuatan politik Islam hingga dapat berpengaruh di dunia sampai hampir 9 abad. Hingga kekhalifahan Islam terakhir di Turki (Usmani) pun, sistem monarkhi inilah yang dipergunakan. Sistem negara nasional (nation state) baru berdiri awal abad ke-20, tepatnya tahun 1920-an, setelah dihapusnya sama sekali sistem kekhalifan di Turki oleh Gerakan Turki Muda pimpinan Mustafa Kemal. Konsep kerajaan yang diberlakukan di dalam sejarah kekhalifahan Islam mungkin saja berbeda dengan yang berlaku di kerajaan-kerajaan Kristen, Hindu, Budha, atau lainnya; terutama dari segala worldview dalam memposisikan raja dan kekuasaan yang dipegangnya. Hanya saja, dari segi praktik politik semuanya sama, yaitu mengandalkan kekuatan politik yang dimiliki suatu dinasti tertentu untuk mengkonsolidasi kekuasaan membentuk suatu “negara-kerajaan”. Alat legitimasi kekuasaannyabukan kesadaran kolektif rakyat, melainkan anasir pembetuk kekuatan politik si pemegang kerajaan seperti kekuatan militer, ekonomi, dan jaringan pendukung pada level kepemimpinan yang lebih rendah.
Konsep ini mulai dikritik oleh para pemikir Eropa abad pencerahan seperti Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) yang memperkenalkan teori “kontak sosial”. Teori ini menggugah kesadaran masyarakat Eropa bahwa suatu negara dapat saja terbentuk atas dasar kehendak rakyatnya, bukan melulu karena keinginan elit politik yang tergabung dalam berbagai dinasti politik. Teori ini semakin diterima luas di tengah semakin kecewanya masyarakat terhadap raja-raja dan lingkaran dinastinya yang semakin tidak dapat menyejahterakan rakyatnya. Rakyat menginginkan penguasa baru, namun sudah tidak senang dengan dinasti-dinasti yang ada. Gagasan Rousseau kemudian menjadi alternatif bagi masyarakat. Sejak saat itulah, kekuasaan raja-raja benar-benar dipangkas sejak abad ke-19 oleh kekuatan kesadaran “nasional”. Proses menuju ke sana didahului dengan tunduknya para raja ini di bawah kendali para tuan tanah (borjuasi). Keberadaan para tuan tanah sebagai penguasa riil baru di Eropa telah memberikan jalan lapamng bagi lahirnya gagasan “nasionalisme” hingga akhirnya gagasan ini benar-benar menghapus sistem kekuasaan monarkhi di berbagai kawasan Eropa. Kalaupun masih ada raja di suatu negara, peran mereka direduksi hanya sebagai simbol seperti di Inggris dan Belanda. Di Prancis dan beberapa negara lain, kerajaan bahkan dihapuskan sama sekali. Penguasa baru muncul bukan lagi mengatasnamakan “dinasti”, melainkan atas nama dukungan rakyat yang menginginkan suatu pola baru dalam pemerintahan. Sejak abad ke-19 inilah secara perlahan dunia menyaksikan lahirnya suatu negara nasional di Eropa mulai dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Belanda, Spanyol, dan sebagainya.
Di dalam sejarah Islam, konsep negara nasional ini semula ditolak mentah-mentah. Pasalnya, gerakan nasionalisme ini digunakan oleh orang-orang Kristen di Balkan sebagai alasan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Usmani. Umat Islam dari Mesir dan Afrika Utara bahkan banyak yang ikut berperang menjawab panggilan Sultan Usmani melawan para pemberontak nasionalis-Kristen di Balkan. Namun, setelah kawasan Afrika Utara lepas dari tangan Usmani dan dikuasai negara-negara kolonial Eropa, nasionalisme justru digunakan oleh komunitas Islam di Afrika Utara ini untuk menentang dominasi asing Kristen. Nasionalisme yang terus meluas di kawasan Arab, terutama Mesir, Libya, Tunisia, dan Al-Jazair, dan Maroko yang dijajah Eropa gaungnya sampai juga ke Indonesia melalui para sarjana yang belajar di Mesir dan melalui jamaah haji yang bertemu para pemimpin Islam dari berbagai belahan dunia di Mekah. Situasi Indonesia yang tengah dijajah oleh Belanda menjadi faktor historis yang kuat bagi para pemimpin muda Muslim di awal abad ke-20 untuk mencetuskan gagasan nasionalisme Indonesia untuk lepas dari cengkeraman kolonialisme.
Gagasan para pemimpin muda Muslim ini gayung bersambut dengan gagasan para pemimpin muda yang belajar di Eropa atau di perguruan-perguruan Eropa di Indonesia. Kenyataan bahwa sudah tidak ada lagi kekuatan dinasti kerajaan manapun di Indonesia yang bisa diharapkan untuk melawan dominasi Belanda menyebabkan intelektual-intelektual muda ini, baik yang terpengaruh informasi dari kawasan Arab maupun Eropa, harus mencari alternatif kekuatan perlawanan baru. Ide nasionalisme adalah ide paling realistis yang dapat mereka gunakan untuk mengkonsolidasi dukungan rakyat melawan dominasi kolonial Belanda.
Hanya saja, persoalan serius yang dihadapi para aktivis ini adalah sejauh mana spektrum dukungan rakyat ini dapat diperoleh? Kekuasaan Belanda membentang dari Aceh hingga Papua. Sementara itu, kekuatan gerakan yang masih amat terbatas dan cenderung bergerak secara lokal. Budi Utomo (1908) membatasi keanggotaannya hanya bagi priyayi Jawa. Isu yang dimunculkan pun, dalam konteks penggalangan dukungan rakyat, hanya seputar bagaimana agar masyarakat Jawa dan Madura dapat lebih sejahtera setelah dimiskinkan oleh pemerintah kolonial. Paguyuban Pasundan (1912) betapapun sudah mulai berusaha berbicara mengenai isu kesejahteraan rakyat sebagai pintu masuk mengkonsolidasi dukungan politik rakyat, tetap spektrumnya hanya sebatas di kalangan etnik Sunda. Beberapa gerakan etnik lain seperti perkumpulan orang-orang China, Sumatera, Sulawesi, dan lainnya terbatas ruang geraknya oleh etnisitas masing-masing. Belum ditemukan benang merah yang bisa menggalang kesatuan di antara gerakan-gerakan yang terbatas itu sampai berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1911.
Sarekat Islam didirkan oleh para haji dan disokong oleh para sarjana jebolan Mesir (Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Haji Samanhoedi, dan lainnya). Mereka adalah orang-orang yang telah menerima gagasan nasionalisme saat mereka memperdalam ilmu di Mesir atau beribadah haji ke Mekah. Gagasan nasionalisme yang telah mereka pelajari itulah yang kemudian mendorong mereka mendirikan Sarekat Islam. Isu yang mereka munculkan ke tengah masyarakat adalah mengenai kesejahteraan rakyat pribumi yang tertindas oleh penguasa kolonial. Bahkan secara ekstrem petinggi-petinggi Sarekan Islam sudah mengusulkan self-bestuur (berpemerintahan sendiri) secara resmi dalam kongresnya tahun 1913 dan 1916. Ini adalah gagasan radikal yang cepat mendapat simpati masyarakat. Tidak heran bila dalam waktu singkat SI menjadi primadona. Dalam Kongres 1916 dilaporkan terdapat sekitar 2 juta anggota SI yang berasal dari berbagai daerah dan beragam etnik.
Pengalaman SI inilah yang telah memecah kebuntuan bagaimana menjembatani orang-orang Indonesia dari berbagai etnik untuk dapat bergabung bersama-sama melawan kolonialisme Belanda. Kemauan rakyat dari beragam etnik ini mendukung gerakan dan seruan Sarekat Islam, selain karena isu yang dibawa mewakili suara hati mereka, juga karena faktor “agama Islam” yang mereka anut. Kesamaan agama ini menjadi kesadaran transendental yang mampu mengatasi hambatan-hambatan perbedaan latar belakang etnik, budaya, dan pulau tempat tinggal masing-masing. Hubungan ini lebih dipermudah lagi telah biasanya digunakan bahasa Melayu pasar sebagai alat komunikasi masyarakat di kawasan ini. Oleh sebab itu, tidak bisa dimungkiri bahwa salah satu faktor pembangun nasionalisme Indonesia ini adalah faktor “ke-Islam-an”.
Koherensi sebagai “suatu bangsa” di tengah keragaman etnik semakin diperkuat dengan lahirnya berbagai gerakan Islam lain selain SI. Sebut saja Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Ittihad Al-Islamiyah, Persyarikatan Ulama, Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), dan lainnya. Gerakan-gerakan Islam ini pada umumnya bergerak melampau batas-batas etnik. Semakin intensif gerakan-gerakan Islam ini mengkonsolidasikan dirinya, semakin terkikis primordialisme etnis yang akan menghambat integrasi menjadi “Indonesia”. Itu artinya bahan-bahan potensial untuk mewujudkan kesadaran nasional sebagai “bangsa Indonesia” yang belum pernah ada preseden sebelumnya semakin kuat.
Mungkin muncul pertanyaan, bukankah dengan melabeli gerakan dengan nama “Islam” malah menciptakan segregasi baru alias menciptakan kelompok primordial seperti kelompok etnik. Bedanya kelompok etnik mendasarkan primordialismenya pada kultur-kesukuan, sedangkan gerakan Islam berdasarkan “agama”. Sama-sama primordialis. Pandangan ini bisa benar apabila jumlah penganut agama yang berbeda-beda seimbang. Misalnya penduduk Muslim hanya 40 persen, Katolik 10 persen, Kristen 20 persen, Hindu 10 persen, Budha 10 persen, lainnya 10 persen. Bila komposisinya seperti ini, maka labelisasi agama justru akan menciptakan segregasi baru di tengah masyarakat. Akan tetapi realitas di Indonesia berlainan sama sekali. Pada awal abad ke-20 jumlah penganut Islam mencapai angka hampir 95 persen. Dengan angka ini menjadi tidak relevan mengatakan membawa nama “Islam” yang dipercayai oleh hampir seluruh penduduk sebagai segregasi. Justru lebih masuk akal membawa nama Islam adalah faktor “pemersatu” seperti dijelaskan di atas.
Alasan selanjutnya bahwa membawa nama “Islam” tidak berdampak memecah-belah, melainkan mempersatukan, karena Islam tidak pernah memiliki ajaran yang menyuruh umatnya untuk hidup dalam satu kawasan tertentu secara eksklusif tanpa percampuran dengan orang lain yang berbeda agama dan keyakinan. Sejak diutus di Mekah hingga hijrah ke Madinah bahkan Rasulullah Saw. memberikan teladan utama bagaimana hidup berdampingan dengan orang-orang yang berlainan keyakinan. Di Mekah Rasulullah Saw. mencontohkan bagaimana hidup menjadi minoritas yang dikuasai kaum kafir Quraisy. Di Madinah beliau mencontohkan menjadi penguasa dengan dukungan mayoritas penduduk Madinah. Semua yang berbeda keyakinan, baik musyrikin maupun Yahudi, dapat hidup di Madinah. Diusirnya Yahudi dari Madinah bukan karena perbedaan agama, melainkan karena pelanggaran kesepakatan hidup bersama yang dilakukan warga Yahudi di Madinah. Sepeninggal Rasul Saw. pun kaum Muslim di berbagai belahan dunia sanggup hidup di tengah-tengah masyarakat plural, baik sebagai penguasa maupun rakyat biasa. Itu artinya kaum Muslim adalah komunitas yang paling siap untuk menjalin kehidupan bersama dengan siapapun, tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Oleh sebab itu, menjadi tidak relevan meletakkan “Islam” sebagai ajaran yang primiordialis yang memecah belak dan mengotak-ngotakkan masyarakat.
Terakhir, di dalam Islam ada perintah untuk hidup “berjamaah”. Banyak sabda Nabi Saw. yang secara tegas memerintahkan untuk itu. Misalnya sabda Nabi Saw., “Kalian harus hidup berjamaah dan menghindari perpecahan” (HR Al-Bukhori); “Berdua lebih baik daripada sendirian, bertiga lebih baik daripada berdua, berempat lebih baik dari bertiga; maka hendaklah kalian hidup berjamaah, karena sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (Allah Swt.).” (HR Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari). Bagi umat Islam, hal yang merupakan perintah Allah Swt. adalah hidup berjamaah bersama dengan yang lain, bukan hidup individualis dan berpecah-belah. Oleh sebab itu, munculnya gerakan-gerakan Islam sesungguhnya dalam usaha untuk menyatukan masyarakat yang bersar-serak untuk kemudian bersama gerakan yang lain berusaha membentuk suatu persatuan yang lebih besar dan lebih luas. Lagi pula gerakan-gerakan Islam di Indonesia tidak ada yang membuat gerakan Islam hanya untuk daerah tertentu saja, melainkan untuk seluruh kawasan Indonesia sehingga tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa gerakan-gerakan Islam ini akan memecah belah masyarakat Indonesia.
Oleh sebab itu, membangun narasi nasionalisme Indonesia melalui para pahlawan yang ditetapkan negara jangan sampai menafikan narasi ke-Islam-an ini. Tokoh-tokoh seperti HOS Tjokroaminoto, Agus Salim, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy’ari, Wahid Hasyim, Abdul Halim, Ahmad Sanusi, M. Natsir, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Mudakkir, dan lainnya narasi kepahlawanannya tidak boleh dilepaskan dari asal-usulnya sebagai tokoh-tokoh gerakan Islam yang sepanjang hayat mereka berjuang untuk menegakkan agamanya. Mereka bukan hanya sekedar pejuang Indonesia, tetapi juga pejuang agama. Apabila mereka diakui menjadi bagian dari pahlawan Indonesia, maka berarti harus diakui bahwa unsur penting pembangun nasionalisme Indonesia adalah Islam. Oleh sebab itu, menyerang Islam dengan isu-isu terorisme, radikalisme, intoleransi, ant-NKRI, anti-Pancasila adalah tindakan yang kontra produktif dalam membangun narasi dan mengokohkan nasionalisme Indonesia. Sebaliknya, negara harus semakin intensif menggali khazanah Islam di Indonesia untuk memperkaya ikatan nasionalisme baru yang lebih relevan dalam menghadapi situasi zaman yang semakin terdesak oleh globalisme.
Ada banyak aspek dalam Islam dan gerakan-gerakan yang diusungnya yang potensinya sangat besar untuk memelihara persatuan Indonesia sebagai indikator kuatnya nasionalisme Indonesia. Pertama, dari segi gerakan organisasi-organisasi Islam, baik yang berdiri sejak awal abad ke-20 maupun yang baru, tidak ada yang menampakkan chauvinisme kesukuan atau kedaerahan. Semuanya bersifat nasional. Kita bisa menyaksikannya saat gerakan-gerakan Islam ini mengadakan even-even besar seperti muktamar atau kongres. Peserta yang hadir datang dari berbagai daerah dan berasal dari beragam etnik. Akan tetapi. Saat mereka bersama tidak ada isu-isu kedaerahan yang dimunculkan. Semua mewacanakan hal-hal yang lebih dari urusan-urusan kedaerahan. Gerakan-gerakan Islam hingga saat ini masih sangat kokoh mentransendensikan perasaan dan kepentingan kedaerahan atau kesukuan masing-masing. Secara tidak langsung kenyataan ini menyiratkan bahwa gerakan-gerakan Islam ini telah ikut melestarikan perasaan “keindonesiaan” di dalam pikiran dan hati para anggota dan pimpinananya. Ini adalah modal yang sangat berharga yang harus dipelihara oleh negara bila ingin tetap mempertahankan suatu negara nasional “Indonesia” ini.
Kedua, aspirasi-aspirasi berbagai gerakan Islam yang berasal dari ajaran agamanya bagi kemajuan negara tidak ada yang diwujudkan dalam konteks separatisme. Separatisme hingga saat ini adalah tema yang sangat asing dalam perbincangan gerakan-gerakan Islam. Sebab, memunculkan isu seperatisme sama saja dengan menghancurkan gerakan itu sendiri yang sudah sejak awal bersifat nasional. Oleh sebab itu, gerakan kontra-negara yang bertujuan untuk membuat negara yang baru hampir tidak punya preseden dalam sejarah gerakan-gerakan Islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Adapun kasus seperti munculnya gerakan Negara Islam Indonesia (NII) adalah kasus khusus dengan latar beakang sejarah mandiri yang kalau kita dedahkan sebetulnya gerakan ini masih sangat merindukan semangat nasionalisme keindonesiaan. Oleh sebab itu, gerakan yang diusung pun masih membawa lekat nama “Indonesia”. Kasus ini berbeda sama sekali dengan kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terang-terangan ingin menghapus nama “Indonesia” dalam pikiran dan gerakan mereka.
Ketiga, dalam menjalankan program-programnya, gerakan-gerakan Islam ini selalu berusaha untuk melakukannya lintas etnik, lintas daerah, bahkan lintas pulau. Gerakan-gerakan dakwah, baik yang di perkotaan maupun di pedalaman, tidak pernah mempersoalkan latar belakang etnik. Perasaan keislaman dan niat untuk menyampaikan ajaran Islam dalam dakwah kepada semua umat manusia sungguh-sungguh sangat berhasil tanpa kecurigaan mengikis perasaan etnisitas dan primordialisme kedaerahan. Gerakan dakwah ini juga berhasil memobilasi pertemuan orang dari beragam etnik yang memungkinkan terciptanya komunikasi lintas-etnik dan lintas-daerah yang sangat dibutuhkan untuk terus memupuk kesadaran “keindonesiaan”, walaupun pada umumnya yang dibicarakan adalah masalah agama.
Keempat, semangat gerakan-gerakan Islam untuk mengembangkan pendidikan melalui pembangunan lembaga-lembaga pendidikan atau pemberian beasiswa kepada para kadernya untuk bersekolah di mana saja telah memperlihatkan secara nyata bahwa tidak ada keraguan sama sekali dari gerakan-gerakan ini untuk menjadi bagian dari “warga Indonesia”. Sebab, kemauan gerakan-gerakan Islam ini mengajarkan Islam dengan pola pendidikan khas Indonesia akan menjadi salah satu alat yang akan semakin menguatkan perasaan “keindonesiaan” itu. Ketika mereka bertemu dengan lembaga pendidikan lain di luar Indonesia segera akan terasa bahwa mereka adalah “Indonesia”. Kita bisa menyaksikan ini pada sekolah-sekolah Muhammadiyah, pesantren-pesantren NU, sekolah-sekolah Persis, dan sebagainya.
Keempat hal di atas hanyalah sebagian kecil yang bisa dicontohkan dari potensi-potensi besar yang bisa disumbangkan oleh gerakan-gerakan Islam pada nasionalisme Indonesia. Seandainya negara malah mengambil jarak atau memusuhi gerakan-gerakan Islam ini dengan melabelinya sebagai “teroris”, “radikalis”, atau lainnya justru yang akan rugi negara sendiri. Negara akan kehilangan banyak sumbangan bagi penguatan nasionalisme keindonesiaan ini. Memang ada Islamisme yang melekat dan tidak dipisahkan dari gerakan-gerakan ini, namun percayalah bahkan watak Islam bukan agama yang memecah belah, melainkan agama yang mempersatukan. Sejarah telah membuktikan terlalu banyak akan hal ini. Wallahu A’lamu bi Al-Shawwab.
BACA JUGA:Tokoh Pendidikan PERSIS, Rahmah El Yunusiyah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional