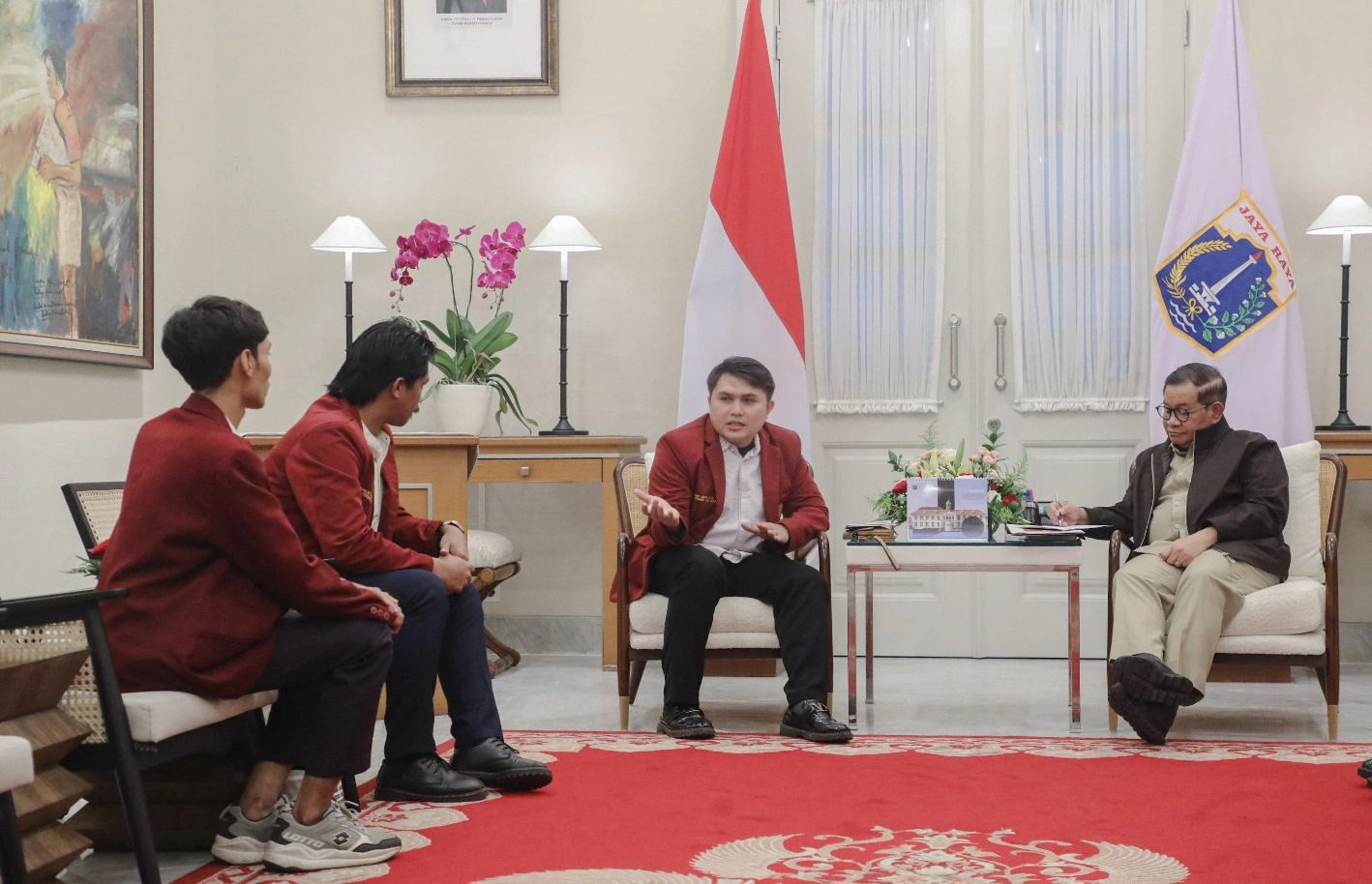Dr. Tiar Anwar Bachtiar
Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakt dan Kelembagaan (HMK) Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis)
Membincangkan Pancasila sesungguhnya harus selalu dilakukan untuk semakin sering menyegarkan kembali kesadaran dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini sangat penting untuk mengingat dan menyadari kembali tujuan bersama membangun “Indonesia” yang disepakati berdiri sejak 17 Agustus 1945 lalu. Seringkali, keberadaan Indonesia ini dianggap sebagai sesuatu yang teken for granted, ada dengan sendirinya, tanpa sejarah, tanpa kesepakatan, dan akhirnya dianggap selalu akan ada. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian.
Salah satu yang menjadi bagian dari sejarah bangsa ini yang cukup fundamental adalah “Pancasila”. Pancasila yang berarti “lima sila” ini telah disepakati bersama sebagai falsafah dan bangsa dasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Kesepakatan ini lahir dari suatu kesadaran dari semua elemen bangsa untuk hidup bersama membangun negara dan bangsa secara bersama-sama.
Kesejarahan Pancasila
Pancasila mula-mula berasal dari suatu dokumen yang ditandatangai oleh anggota-anggota Badan Penyelidik Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Sukarno. Dokumen itu kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Lahirnya Piagam Jakarta ini diawali oleh sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang ini dibahas beberapa agenda. Salah satu agenda penting dan memerlukan pembahasan tambahan adalah tentang dasar negara. Beberapa anggota menyampaikan pandangan mereka tentang dasar negara Indonesia. Mula-mula Moch. Yamin menyampaikan pandangannya. Ia mengusulkan lima dasar negara. Karena dalam sidang itu Moch. Yamin yang pertama mengusulkan lima sila itu, Yamin mengklaim bahwa Pancasila ini awalnya adalah cetusan idenya.
Pada tanggal 30 Mei giliran wakil Islam, Ki Bagus Hadikusumo yang juga ketua PB Muhammadiyah menyampaikan pidatonya. Berikutnya Prof. Soepomo pada pidatonya tanggal 31 Mei menyampaikan gagasannya. Sama Pada hari terakhir persidangan 1 Juni, giliran Sukarno yang tampil ke muka menyampaikan gagasannya. Pada pidato inilah Sukarno memperkenalkan istilah “Pancasila”, “Trisila”, dan “Ekasila” yang ia usulkan sebagai dasar negara Indonesia.
Belum ada kesepakatan final tentang dasar negara ini hingga akhir persidangan tanggal 1 Juni. Akhirnya, ditunjuk tim khusus berjumlah 8 orang yang diketuai Sukarno untuk membahas formulasi dasar negara berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan para peserta sidang sebelumnya. Tim ini tidak kunjung mencapai kata sepakat hingga terjadi perombakan tim menjadi 9 orang dengan tetap diketuai Sukarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 Tim Sembilan dapat merampungkan tugasnya menyusun draft untuk disampaikan pada Sidang Periode Kedua 10 sd 17 Juli 1945. Draft inilah yang disebut sebagai Piagam Jakarta yang dibacakan Sukarno di hadapan sidang pada tanggal 10 Juli 1945. Hingga akhir persidangan hasil Tim Sembilan pimpinan Sukarno itu disepakati sebagaimana adanya dan diletakkan sebagai pembukaan UUD yang juga telah rampung dibahas pada tanggal 17 Juli saat itu.
Pada tanggal 12 Agustus 1945 memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sukarno ditunjuk sebagai ketua bersama Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat sebagai wakilnya. Akan tetapi, panitia ini dipilih berdasarkan perwakilan daerah, bukan representasi ideologi seperti pada saat sidang-sidang BPUPK sehingga banyak wakil umat Islam yang tidak ada. Kalangan Islam hanya diwakili Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Teuku Moh. Hasan, dan Kasman Singodimedjo. Sementara sisanya mewakili kalangan nasionalis, Kristen, dan Hindu. Hanya saja, sebelum Kemerdekaan benar-benar diberikan oleh Jepang, tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada Sekutu dan harus segera angkat kaki dari Indonesia. Peristiwa ini kemudian disusul dengan drama penculikan Sukarno yang dipaksa oleh kalangan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan yang dapat dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945.
PPKI pun segera bersidang sehari berikutnya tanggal 18 Agustus. Pada sidang inilah terjadi perubahan terakhir UUD yang telah dihasilkan oleh BPUPK sebulan sebelumnya. Perubahan terjadi pada pembukaan yang memuat “Pancasila”. Tujuh kata dalam sila pertama, yaitu “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan yang kelihatan sepele tetapi berdampak sangat luas.
Perubahan yang singkat ini, menurut pengakuan Hatta dalam Memoir Mohammad Hatta, sore hari sebelum rapat PPKI dia kedatangan seorang perwira Angkatan Laut (AL) Jepang atas permohonan Nishijama, asisten Laksamana Maeda. Perwira ini memberitahukan bahwa orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia bagian Timur sangat berkeberatan dengan klausul Islam (tujuh kata) dalam Pembukaan karena dianggap sebagai diskriminasi. Jika kalimat ini tetap dimasukkan, katanya, mereka lebih suka berada di luar Republik Indonesia.
Oleh sebab itu, Hatta kemudian berusaha mendekati tokoh-tokoh Islam membicarakan masalah ini. Teuku Hasan setuju. Kasman yang baru mendapat undangan kelihatan tidak siap sepenuhnya dengan ide ini. Wahid Hasjim tengah pergi ke Surabaya. Tersisa Ki Bagus Hadikusumo. Ia dibujuk sedemikian rupa untuk menerima. Dengan alasan demi persatuan bangsa dan alassan sifat kesementaraan UUD ini, maka Ki Bagus Hadikusumo mau menerimanya. Lagi pula ia diyakinkan bahwa makna “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak lain adalah “Tauhid”. Kasman sendiri yang ikut dalam rapat amat memaklumi situasi kejiwaannya. Orang-orang Kristen sangat pandai memanfaatkan situasi yang tengah sangat genting saat semua orang ingin segera melihat wujud kemerdekaan dan ingin bersatu, maka desakan-desakan yang dilakukan Hatta atas nama persatuan bangsa dapat diamini dengan mudah.
Yang merasa paling dikecewakan atas perubahan ini adalah kelompok Islam. Mereka merasa bahwa gentlemen agreement yang sudah disepakati bersama dimentahkan hanya dalam ruang dialog yang lebih sempit di PPKI. Pada saat sidang BPUPKI, anggotanya sebanyak 62 orang mewakili banyak kalangan. Sementara saat sidang perdana PPKI, anggotanya hanya 26 orang. Itupun tidak hadir semua dalam sidang. Walaupun demikian, sebagai warga bangsa yang baik, umat Islam tetap menghormati keptusan itu.
Naskah UUD 1945 hasil kesepakatan 18 Agustus itu sempat mengalami perubahan beberapa kali, yaitu pada tahun 1947 ketika Indonesia berubah menjadi negara serikat, kemudian berubah lagi tahun 1950 ketika RIS berubah menjadi NKRI. Semua perubahan itu bersifat sementara pada mulanya karena akan dibahas UUD yang definitif dalam sidang khusus Konstituante yang terlaksana tahun 1957-1959. Namun sayang, akhirnya Konstituante pun gagal menghasilkan UUD baru, karena secara paksa dibubarkan Sukarno melalui Dekrit 5 Juli 1959.
Semenjak berlaku Dekrit 5 Juli 1959 semua perundang-undangan yang mengganti UUD 1945, yaitu UUD RIS dan UUD Sementara tahun 1950 yang berlaku setelah Mosi Integral Natsir, dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Dasar yang telah 90 persen dirampungkan oleh Konstituante pun gugur. Akhirnya, Dekrit memberikan jalan lempang berlakunya kembali UUD 1945 versi kesepakatan 18 Agustus. Namun, dalam teks berlakunya kembali UUD 1945 ini terdapat klausul yang merupakan bentuk akomodasi Sukarno terhadap kelompok Islam yang telah dikecewakan semenjak peristiwa 18 Agustus 1945 dan gagalnya Konstituante. Klausul itu berbunyi sebagai: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”
Klausul ini secara tegas memberikan ruang terhadap berlakunya jiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 untuk mengakhiri kontroversi berubahnya tujuh kata pada tanggal 18 Agustus. Kasman Singodimedjo, yang terlibat dalam lobi-lobi tanggal 18 Agustus 1945 di PPKI, menyatakan, bahwa Dekrit 5 Juli 1959 bersifat “einmalig”, artinya berlaku untuk selama-lamanya (tidak dapat dicabut). “Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi sehidup semati dengan Undang-undang Dasar 1945 itu, bahkan merupakan jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut,” tulis Kasman dalam bukunya, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
Dengan demikian, cukup jelas bahwa semenjak berlakunya Dekrit 5 Juli 1959 sampai saat ini, keberadaan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 memiliki kekuatan hukum mengikat di negeri ini. Sekalipun demikian, banyak pihak yang berupaya menutup-nutupi kenyataan ini dengan memberikan argumentasi yang seringkali keluar dari konteks hukum ini. Padahal, tidak berapa lama setelah Dekrit, ditetapkan berbagai keputusan yang mengacu pada diakuinya Piagam Jakarta ini.
Bila semua pihak konsisten dengan apa yang telah terjadi pada bangsa ini, maka semua pihak semestinya sudah menghentikan perdebatan tentang keabsahan Pancasila dan semangat Piagam Jakarta. Sampai saat ini belum ada klausul yang mencabut kembali Dekit yang dikeluarkan Sukarno 50 tahun lalu itu. Bahkan, sampai UUD 1945 itu diamandemen sampai empat kali sejak tahun 1999 sampai 2002, klausul Dekrit yang mendasari berlakunya kembali UUD 1945 tidak dipermasalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa gentlements agreement tetap berlaku dan harus menjadi landasan dalam membangun negara dan bangsa ini ke depan.
Menggali Semangat Pancasila
Bila kita mengacu pada semangat sejarah Pancasila, maka secara prinsipil ada beberapa hal yang harus menjadi catatan penting bagi kita sebagai pelanjut amanah keberlangusngan negara tercinta ini. Pertama, Pancasila harus diletakkan sebagai gentlemens agreement. Artinya, Pancasila tidak perlu dikultuskan dan dimitoskan sebagai sesuatu yang memiliki semacam kekuatan “magis”. Biarkanlah Pancasila sebagaimana sedia kala sebagai sebuah kesepakatan yang dicapai oleh seluruh elemen bangsa dalam menyelenggarakan negara ini. Bila ini sebuah kesepakatan, maka yang diperlukan untuk menjaganya adalah komitmen bersama untuk memelihara apa yang telah menjadi kesepekatan bersama itu.
Kedua, sebagai dasar negara yang berasal dari sebuah kesepakatan, Pancasila harus diberi makna secara terbuka. Sebuah kesepakatan adalah milik bersama. Setiap upaya untuk memaksakan suatu tafsir atas kesepakatan itu kepada pihak lain sesungguhnya sudah merupakan bagian dari pelanggaran atas kesepakatan itu; dan hampir bisa dipastikan akan menuai kegagalan. Kesalahan terbesar Orde Baru dalam memelihara Pancasila adalah memaksakan Pancasila dijadikan sebagai Asas Tunggal dengan tafsir tunggal P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pemaksaan ini dapat ditafsirkan sebagai usaha untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Jelas, upaya semacam ini menuai protes dari berbagai kalangan dan akhirnya berujung pada situasi yang hampir chaotic di akhir kekuasaan Orde Baru. Upaya-upaya ideologisasi Pancasila secara tertutup dalam bentuk apapun justru hanya akan memecah belah bangsa, bukan mempererat persatuan. Padahal, fungsi Pancasila adalah sebagai gentlemens agreement, bukan memecah belah. Apalagi proses ideologisasi ini secara sengaja dibuat untuk menyingkirkan satu kekuatan kelompok tertentu yang ikut menjadi penyangga lahirnya bangsa ini. Ujungnya pasti akan berakibat terbelahnya bangsa ini.
Ketiga, yang paling penting untuk mewujudkan semangat Pancasila sebagai kesepakatan bersama adalah implementasinya pada perumusan perundang-undangan dan segala aturan legal-formal di negeri ini. Dalam hal ini, seperti pidato Sukarno 1 Juni 1945, Pancasila berfungsi sebagai “philosophisce groonslag.” Sejak awal Indonesia diselenggarakan sebagai negara hukum (recht-staat), bukan negara kekuasaan (maacht-staat). Oleh sebab itu, yang paling penting dalam pelaksanaan Pancasila adalah implikasinya pada hukum, bukan pada ideologi orang per orang di negeri ini. Perundang-undangan di bawahnya-lah yang harus terus dievaluasi agar tidak terlepas dari semangat Pancasila.