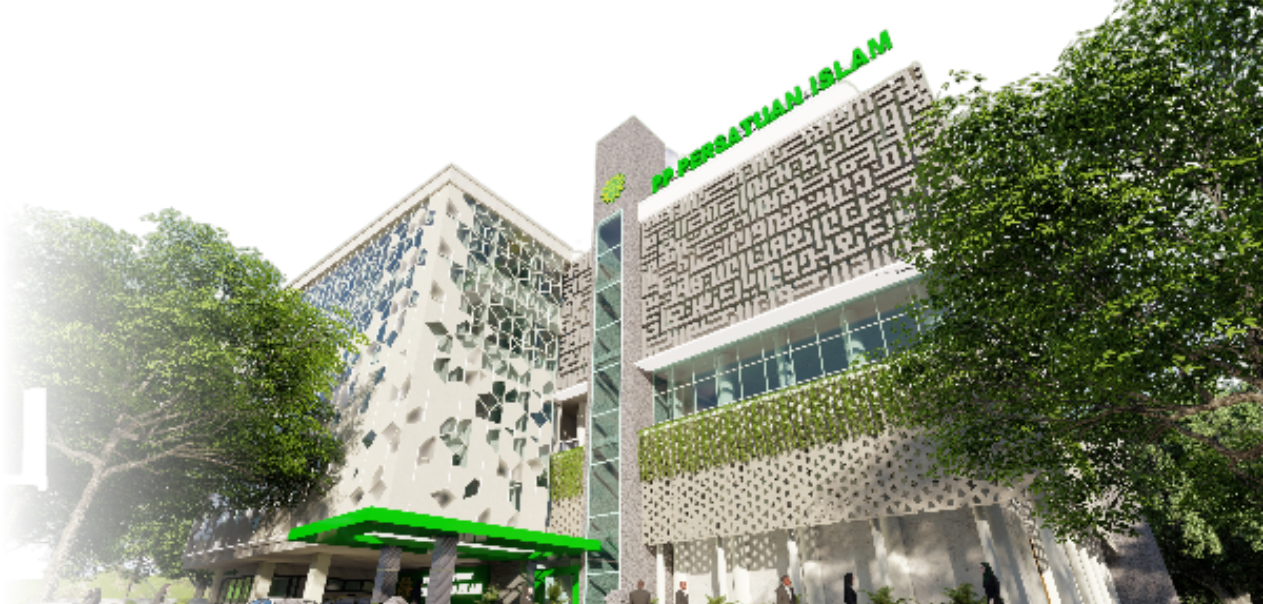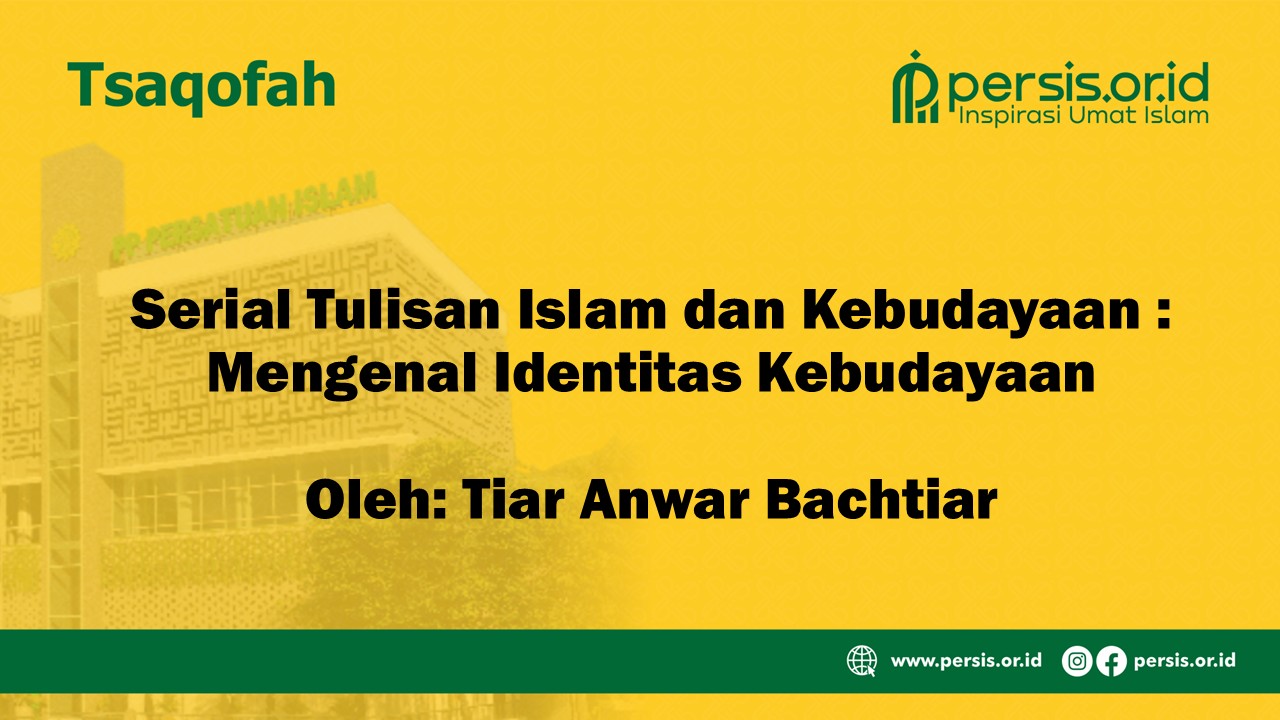Ketika berbicara mengenai “budaya” atau “kebudayaan” salah satu kesulitan yang dihadapi adalah mendefinisikannya. Ada banyak sekali definisi kebudayaan yang diungkapkan oleh para ahli. Ada yang mengkontraskan “budaya” (culture) dengan “alam” (nature). Segala perilaku yang dipelajari (learned behavior) adalah budaya, sedangkan perilaku yang tidak dipelajari, bisa begitu saja, bukan merupakan budaya atau dianggap alamiah. Ada yang menganggap budaya sebagai suatu sistem tertentu dalam kehidupan manusia di samping ada sistem lain seperti ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Pada definisi pertama kebudayaan bersifat all embracing mencakup semua produk yang bukan alami, atau produk yang dihasilkan oleh usaha manusia. Dalam definisi ini ekonomi, politik, sistem sosial, produk seni, pengetahuan, dan sebagainya adalah bagian dari “kebudayaan”. Sedangkan pada definisi yang kedua, budaya dianggap sebagai satu aspek tersendiri dalam kehidupan manusia disamping aspek lainnya seperti ekonomi, dan politik. Dalam definisi ini, kebudayaan bersifat parsial. Kelihatan seperti bertentangan, tetapi sebetulnya masih dapat dikompromikan.
Ada hal-hal yang mempertemukan kedua definisi tersebut, yaitu wujud budaya yang bersifat simbolik dan “makna” yang terkandung di dalam hal-hal yang simbolik tersebut. “Makna” dan “simbol” menjadi kata kunci utama untuk memahami budaya dan mempertemukan berbagai definisi. Kita ambil contoh suatu yang hari ini menjadi bagian dari kebudayaan kita di Indonesia, yaitu “pemilihan umum”. Pemilu telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita di Indonesia ini semenjak tahun 1955. Ini artinya telah menjadi budaya. Dalam budaya ini tersimpan “makna” dan “simbol” sekaligus. Simbolnya berbentuk: ide demokrasi, mobilisasi manusia ke tempat pemungutan suara, kertas suara, dan lainnya. Simbol-simbol tersebut menyiratkan adanya “makna” yang sering disebut sebagai “modernisme politik” yang merupakan tata nilai baru berasal dari Eropa setelah abad ke-16 yang kemudian berpengaruh ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Modernisme dalam bidang politik ini mengajarkan nilai “kesetaraan hak setiap manusia dalam hal kekuasaan, baik untuk menjadi pemimpin maupun yang dipimpin.” Tata nilai baru ini merupakan hasil diskursus panjang di antara para pemikir masa itu. Tata nilai ini kemudian dibuat simbolisasinya, yaitu “pemilihan umum”. Ketika di suatu tempat “pemilihan umum” sudah dijalankan, apalagi dijadikan kebiasaan, maka berarti telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Bila sebelumnya telah ada tata cara lain yang berbeda dengan pemilihan umum ini, maka tata nilai baru ini berarti telah menggeser yang lama. Tata nilai baru itu disebut “sistem budaya” dan simbolisasinya pun sesungguhnya merupakan “produk budaya”. Artinya kedua-duanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan.
Kebudayaan didefinisikan sebagai suatu sistem tertentu yang berbeda dari sistem politik, ekonomi, sosial, dan lainnya berasal dari definisi masyhur Clifford Geertz. Dalam salah satu bukunya The Interpretation of Culture (1973: 89) ia menyebut budaya sebagai: “suatu sistem konsepsi-konsepsi terwariskan yang diungkapkan dalam bentuk simbolik yang dengannya manusia berkomunikasi, melanggengkan, serta mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan (a system of inherited cenceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life).” Dalam definisi ini, dipahami bahwa budaya bersifat abstrak berupa konsepsi dalam pikiran manusia yang terwariskan, bisa berasal dari generasi sebelumnya atau hasil belajar, yang diwujudkan dalam berbagai simbol. Konsepsi abstrak tersebut membentuk suatu “sistem” tersendiri yang berpengaruh pada banyak aspek dalam kehidupan.
Dalam definisi ini, kebudayaan dianggap sebagai suatu sistem khusus yang membatasinya sebagai sistem “kebudayaan” yang dibedakan dari sistem politik, ekonomi, sosial, agama, dan lainnya. Karakter yang membatasinya seperti penjelasan di atas, yaitu “sistem konsepsi atau makna yang mewujud dalam simbol” dan kemudian menjadi pegangan masyarakat lalu diwariskan secara turun-temurun hingga membentuk suatu “tradisi” tertentu dalam banyak aspek kehidupan. Bagi Geertz, sistem budaya adalah aspek “dalaman” yang membentuk nilai, sedangkan aspek luarannya membentuk sistem-sistem yang bersifat kongkrit seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem teknologi, dan sebagainya.
Untuk memudahkan pemahaman berdasarkan definisi ini kita coba bedakan antara “politik” dengan “budaya politik”. “Politik” adalah segala tindakan yang berhubungan dengan kekuasaan. Relasi-relasi kekuasaan ini semuanya disebut “politik”. Raja Arab Saudi dengan Presiden Amerika, kerajaan dan republik, pemilihan umum dan pemilihan putra mahkota, semuanya merupakan bagian dari politik, karena esensi dari semuanya sama, yaitu “berelasi dengan kekuasaan”. Lalu apa yang masuk dalam ketegori “budaya politik”? Adanya perbedaan simbol pemimpin antara “raja” dan “presiden” menyiratkan adanya perbedaan pemaknaan terhadap relasi-relasi kuasa tersebut. Raja yang bersifat dinastik memiliki alasan ideal mengapa memilih untuk menjalankan kuasa dengan cara seperti itu: membentuk kekuatan dinasti, mengontrol negara secara absolut oleh dinasti, dan tidak memberikan ruang kepada publik untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan politik. Tata nilai yang disimbolkan dalam bentuk “kerajaan” merupakan “budaya politik”. Budaya politik ini sering disebut “budaya (politik) monarkhi”. Budaya monarkhi ini telah membedakan praktik politik “kerajaan” dengan praktik politik yang simbolisasinya bernama “presiden”. Idenya berbeda, simbolisasi sistem dan penanda fisiknya pun berbeda hingga relasi ini membentuk suatu budaya politik tertentu yang umum disebut “budaya (politik) modern”. Kalau begitu, kerajaan dan republik, walaupun sama-sama politik, lahir dari budaya politik yang berbeda. Dari contoh ini kita bisa memahami bahwa di satu sisi istilah “politik” lebih umum dari “budaya”, tapi di sisi lain “budaya” lebih umum dari “politik”. Ini menandakan bahwa masing-masing dari kedua istilah terebut memiliki ruangnya sendiri-sendiri. Hal ini berlaku juga saat budaya disandingkan dengan istilah “ekonomi”, “agama”, “kesenian”, dan lainnya.
Berdasarkan penjelasan di atas, juga dapat dipahami bahwa apabila kita berurusan dengan “budaya”, maka ide atau gagasan menjadi sangat sentral. Akan tetapi, harus dipahami juga bahwa tanpa simbolisasi, ide, gagasan, dan tata nilai menjadi tidak memiliki eksistensi dan tidak pernah akan menjadi kebudayaan yang utuh. Oleh sebab itu, aspek simbolik dari gagasan merupakan hal yang utama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan. Simbolisasi budaya dapat berbentuk hubungan antar-manusia (sistem sosial) atau benda-benda yang digunakan manusia dalam kehidupan kesehariannya. Oleh sebab itu, dalam kebudayaan, antara “simbol” dan “makna” tidak dapat dipisahkan. Keduanya secara bersamaan membentuk kebudayaan manusia. Simbol tanpa makna atau makna tanpa simbol adalah kepincangan.
Memahami budaya tidak bisa hanya dipahami deskripsi simbolisnya. Simbol hanya penanda yang menyimpan makna tertentu yang dijelaskan dalam sistem ide (gagasan) budaya tersebut. Bahkan menjadi sangat lucu ketika ada anjuran, bahkan menjadi peraturan di daerah tententu, untuk menghidupkan budaya semata-mata hanya menampakkan simbolnya seperti menggunakan pakaian tertentu, warna tertentu, makan makanan tertentu, dan lainnya tanpa memedulikan pemahaman atas ide di balik simbol-simbol tersebut dan relevansinya dengan situasi terkini yang dihadapi manusia. Akhirnya anjuran menghidupkanbudaya tertentu malah berubah menjadi tontonan tanpa makna yang menyebabkan budaya tersebut semakin cepat mati.
Hal yang serupa juga terjadi pada mereka yang hanya mengeksplorasi ide-ide tanpa merelasikannya dengan wilayah-wilayah simbolik. Ide-ide hanya menjadi bahan pikiran sendiri, tapi tidak bisa menjadi milik masyarakat. Masyarakat menganggap ide-ide tersebut sebagai sesuatu yang tidak realistis dan hanya berlaku di alam khayal. Mewujudkan ide menjadi simbol yang kongkrit memudahkan masyarakat untuk memahami dan kemudian menerima atau menolak ide tersebut. Seseorang yang berpikir tentang kebudayaan selalu melihat gagasan bersama wujud simbolnya, dan simbol bersama dengan ide yang terkandung di dalamnya. Sementara yang mengeksplorasi ide-ide hanya sebagai “ide” semata bukan menekuni budaya, melainkan hanya menekuni aspek “pemikiran”. Betul bahwa pemikiran ini adalah bahan baku bagi budaya, tetapi bila belum diwujudkan simbolnya lalu diterima luas oleh masyarakat dan dipraktikkan berulang-ulang secara sukarela membentuk suatu kebiasaan simbolik tertentu, maka ide tersebut belum masuk menjadi bagian dari suatu bentang kebudayaan.
Berdasarkan realitas seperti di atas, secara secara antopologis kebudayaan didefinisikan misalnya oleh Kuntjaraningrat (1985: 180) dalam Perngantar Ilmu Antropologi sebagai “…keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.” Kebudayaan harus dilihat pada aspek simbolnya terlebih dahulu, baik berbentuk tindakan berpola atau artefak berpola, yang padanya terkandung konsepsi pemikiran (pemaknaan). Makna dan simbol tersebut kedua-duanya merupakan produk “kebudayaan”.
Dalam penjelasan lain Magetsari dalam buku Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya (Hidayat [ed.], 2018: 14) menyebutkan bahwa kebudayaan adalah “keseluruhan pengetahuan, pengalaman, sikap bagaimana berperilaku, yang dianut serta diajarkan turun-temurun oleh anggota masyarakat tertentu. Kebudayaan dapat diartikan sebagai cetak biru bagaimana anggota masyarakat seyogiayanya bersikap dalam tindak tanduknya agar ia diakui sebagai anggota masyarakat di lingkungan sosial budayanya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan pengikat bagi anggotanya tetapi juga sekaligus pembeda antara masyarakat dari lingkungan sosial budaya yang satu dengan lainnya. Di samping itu, budaya juga membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang dihadapi.” Dalam penjelasan ini semakin jelas bahwa budaya sesungguhnya bersifat “abstrak” (meaning) yang dapat dilihat perwujudan simboliknya dalam ide-ide, relasi-relasi sosial, dan artefak bendawi yang menyatu dengan lainnya dalam kehidupan masyarakat.
Dapat pula disimpulkan secara sederhara bahwa kebudayaan adalah what we make (apa yang kita buat) yang melahirkan budaya benda; what we do (apa yang kita perbuat) yang menghasilkan relasi dan struktur sosial; dan what we think (apa yang kita pikirkan) yang membentuk norma, nilai, ideologi, dan worldview. Ketiganya akan berkelindan dalam cultural frame (tindakan budaya yang tampak) berupa simbol, ritual (kegiatan yang berulang-ulang dilakukan), dan struktur sosial. Karena yang tampak dan berinteraksi langsung dengan manusia adalah cultural frame, maka kebudayaan hanya dapat dipahami melalui simbol-simbol, ritual-ritual, dan struktur sosial. Ketiganya merupakan agregasi kultural yang bagian-bagiannya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Memahami kebudayaan adalah memahami relasi di antara unsur-unsur tersebut yang berguna untuk mengarahkan kebudayaan ke arah yang lebih maslahat untuk kehidupan manusia.
BACA JUGA:Hukum Bermakmum kepada Musafir lalu Melanjutkan dengan Imam Muqim: Bagaimana Tata Caranya?