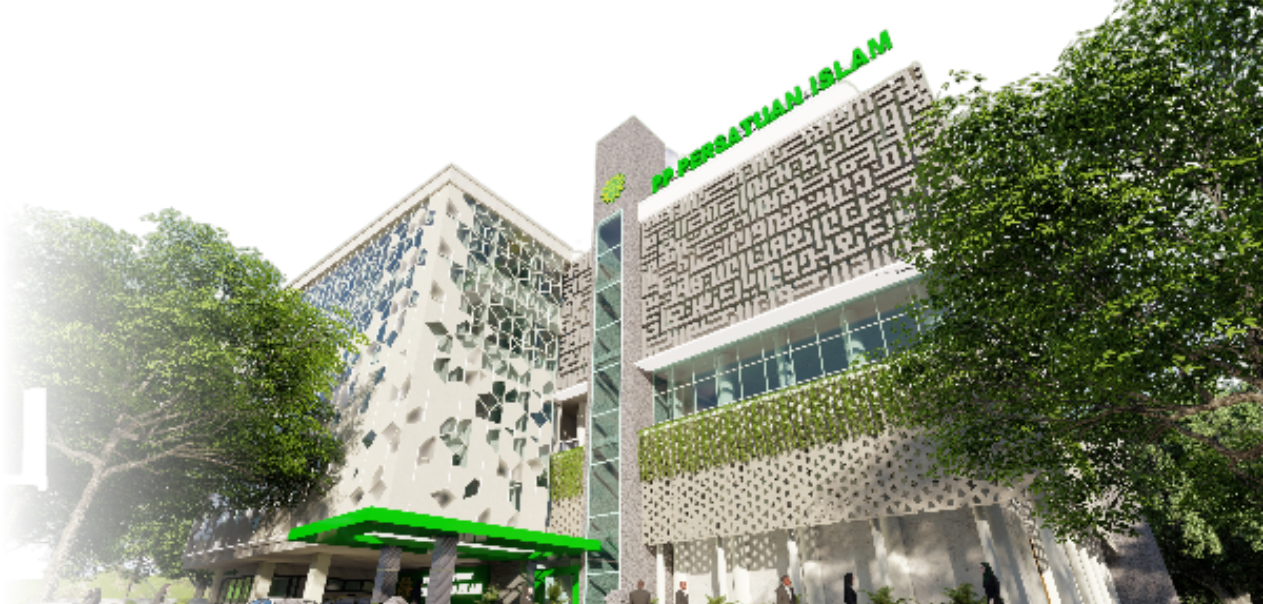Signifikansi Sekolah Persatuan Islam:
Sebuah Retrospeksi
“Dina pingpinan Djrg. H. Zamzam, pagoejoeban Persatoean Islam geus bisa ngajakeun
sakola Frobel, H.I.S., djeung Mulo nu make dadasar Kaislaman.
Moega-moega ieu sakola tambah-tambah kamadjoeanana!”
—Koran Sipatahoenan, 27 Djanoeari 1933 M.
Pengantar
Suatu hari, saya berbincang dengan seorang ustaz. Tepatnya, seorang mubalig Persatuan Islam. Ia ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Namun, tidak sembarang lembaga pendidikan. “Harus lembaga penddikan pesantren,” katanya. Baginya, pesantren adalah ciri khas lembaga Pendidikan Persatuan Islam. Seolah, jika mendirikan model pendidikan lain—yakni, yang kemudian sering disebut “sekolah umum”—maka itu adalah tindakan yang keluar dari chittah perjuangan Persatuan Islam.
Model pendidikan pesantren di bawah naungan Jamiyah Persatuan Islam seolah menjadi “doktrin” tersendiri. Setiap aktivis Jamiyah berlomba mendirikan Pesantren Persatuan Islam. Apalagi jika sang aktivis itu sebelumnya adalah alumnus Pesantren Persatuan Islam itu sendiri. Seolah menjadi kewajiban bagi dirinya untuk mendirikan (lagi) pesantren, bukan model pendidikan lainnya. Sampai-sampai ia memaksakan diri mendirikan lembaga pendidikan pesantren, walaupun tidak memenuhi prasyarat pondok pesantren.
Gara-gara itu bahkan muncul isu “pendidikan asli” Persatuan Islam. Dengan kata lain, pendidikan Persatuan Islam yang murni pesantren, tidak dicampur-campur. Hal ini bagian dari respon—sebagian—warga Jamiyah terhadap fenomena terjadinya “persilangan pendidikan” antara pesantren vis-à-vis pendidikan umum. Seolah ingin memutar jarum jam sejarah.
Tak dapat dipungkiri, fakta menunjukkan model pendidikan yang tumbuh-menjamur di Jamiyah Persatuan Islam adalah pesantren. Bukan berarti tidak ada Sekolah Persatuan Islam. Namun demikian, jumlah—dan sekaligus menunjukkan eksistensi—Sekolah Persatuan Islam sangatlah minor dibandingkan dengan Pesantren Persatuan Islam. Bahkan, ada sekolah namun tetap diberi nama pesantren. Atau paling tidak: “Sekolah plus Pesantren”. Seolah-olah “sekolah” saja tidak cukup. Tidakkah semua itu menunjukkan pandangan minor warga Persatuan Islam terhadap eksistensi sekolah?
Bukan berarti hal itu adalah salah. Ikhtiar mendirikan pesantren jelas sebuah tindakan terpuji. Namun menjadikannya sebagai sebuah doktrin—menjadi sebuah “kewajiban” tersendiri—jelas itu berlebihan, bahkan cenderung salah kaprah. Model Pendidikan Pesantren atau Sekolah adalah urusan pilihan strategi. Tergantung mana yang lebih dibutuhkan dalam konteks ruang dan waktu. Pada waktu atau tempat yang berbeda bisa jadi pilihan-pilihan terkait model pendidikan tersebut berbeda pula dan sekaligus mengalami perubahan (transformasi).
Maka, timbul pertanyaan-pertanyaan: Pertama, mengapa eksistensi sekolah menjadi minor daripada pesantren pada warga jamiyah Persatuan Islam? Apakah itu memang dari asalnya begitu? Menilik pada Sejarah Pendidikan Persatuan Islam, sebenarnya sejak kapan fenomena itu bermula?
Kedua, pertanyaan yang lebih krusial: Sebenarnya eksistensi Sekolah Persatuan Islam ditujukan untuk apa? Apakah Sekolah Persatuan Islam muncul hanya karena permintaan pasar? Ataukah di balik Sekolah Persatuan Islam itu ada gagasan yang visioner?
Tinjauan Sejarah
Lembaga pendidikan yang mula-mula didirikan dan dibangun oleh Jamiyah Persatuan Islam adalah model pendidikan kursus agama—yang waktu itu tahun 1923 diistilahkan “Lezing Igama”. Para pesertanya adalah orang-orang dewasa (periode awal 1923-1926) dan kemudian berkembang para pemuda terpelajar, seperti Fachroedin Alkahiri, M. Natsir, Bahtiar Efendi (ketiganya siswa Algemene Midleberen School atau AMS jenjang sekolah menengah), serta Indra Tjaya dan Ibrahim (keduanya mahasiswa Technisiche Hogeschool atau THS yang sekarang menjadi ITB) pada periode 1927-1929. Dari kursus agama ini berkembang menjadi madrasah diniyah yang diperuntukkan bagi anak-anak pada awal 1930-an.
Baik sistem kursus agama untuk orang dewasa ataupun madrasah diniyah untuk anak-anak, kedua sistem itu adalah model pendidikan non-formal. Barulah pada tahun 1932, Jamiyah PERSIS mendirikan lembaga pendidikan formal. Pada saat itu, sistem pendidikan yang dipilih Persatuan Islam untuk dikembangkan lebih lanjut bukanlah pesantren ataupun madrasah, namun justru model pendidikan sekolah Belanda (pendidikan umum). Mengapa demikian? Tentu menarik untuk dikaji konteks peristiwanya.
Pada bulan Maret 1932, Jamiyah Persatuan Islam menyelenggarakan pertemuan kaum muslimin di Bandung dengan mengangkat persoalan pendidikan bagi generasi muda Islam sebagai tema sentralnya. Pertemuan itu melahirkan suatu badan yang diberi nama Komite Pendidikan Islam atau yang lebih dikenal dengan akronim “Pendis.” Ketika Mohamad Natsir diwawancarai oleh Ajip Rosidi (1990: 169), ia menekankan bahwa “usaha yang dilakukan badan itu ialah mengadakan dan mengembangkan pelajaran ilmu-ilmu modern dengan pelajaran dan pendidikan Islam dalam arti yang seluas-luasnya.”
Jelas, program pendidikan Komite Pendis yang dibangun Jamiyah sungguhlah visioner. Lembaga pendidikan didirikan bukan sekedar memenuhi kebutuhan pasar. Lebih dari itu, ia dibangun dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan melalui pembaruan kurikulum pendidikan. Pembaruan kurikulum pendidikan itu bermuara pada penanaman “ruh Islam” pada setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada para siswa sekolah. Jelas, karena pada sekolah Belanda waktu itu pembelajaran ilmu terpisah—dengan kata lain, sengaja dipisahkan—dengan agama (sistem pendidikan sekularistik).
Bagi Persatuan Islam, pendidikan umum yang dikembangkan Pemerintah Kolonial Belanda mempunyai kelemahan sekaligus kesalahan yang fatal. Ia hanya menjadikan para siswanya sebagai “calon pekerja” yang akan “makan gaji”. Itu sama saja menciptakan sistem ketergantungan dan “mentalitas buruh” yang akut pada peserta didik pada umumnya. Oleh karena itu, visi pendidikan umum Sekolah Pendis juga memuat “pengaturan segala didikan yang akan diberikan itu menjaga anak-anak muslim jangan sampai bergantung kepada makan gaji atau perburuhan waktu sudah keluar dari sekolah, melainkan sebisa-bisanya bekerja dengan tenaga sendiri” (Rosidi, 1990: 169). Sekolah Pendis, dalam bahasa Prof. Abudin Nata (2005: 73), “mengelola sistem pendidikan yang dapat melahirkan lulusan yang memiliki kepribadian yang mandiri dan terampil.”
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas antara lain dilakukan melalui pendirian sekolah-sekolah, mulai dari frobel school (jenjang TK), Holland Inlander School (HIS jenjang sekolah dasar), dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO jenjang sekolah menengah pertama). Dikembangkan pula model pertukangan, perdagangan, internaat (asrama), kursus-kursus, dan ceramah-ceramah. Melalui sistem ini, sifat sekolah Pendis adalah “mengatur pelajaran sebisa-bisanya menurut kecakapan dan bakatnya murid masing-masing dengan memperhatikan sifat dan tabi’at murid.” Sehingga dapat “menanamkan bibit keinsyafan dan kepercayaan kepada kekuatan yang diberikan Allah kepada dirinya masing-masing.”
Sekolah Pendis pun segera berkembang. Baru beberapa tahun berjalan, ia sudah mendapat apresiasi yang tinggi. Tidak haya respon positif masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah Pendis. Elite-elite masyarakat Bandung pun mengapresiasi atas kinerja positif Jamiyah Persatuan Islam terkait dengan peran pembangunan pendidikan umum di Bandung. Dengan terang-benderang, Koran Sipatahoenan memuji KHM. Zamzam sebagai Ketua Persatuan Islam, karena mempunyai sekolah-sekolah unggulan—jenjang Frobel, HIS dan MULO—yang berbasis pada nilai-nilai Islam di Kota Bandung (Sipatahoenan, 27 Djanoeari 1933).
Yang diserahi amanah Jamiyah untuk mengurusi Sekolah Pendis ini adalah M. Natsir, sebagai Direktur Pendidikan Islam. Makanya, Pendis dengan Natsir menjadi identik. Peran sentral Natsir tidaklah sekedar dalam urusan manajerial. Lebih dari itu, Natsir membangun fundamen ideologi sekolah Pendis. Sebagai raising star Jamiyah, Natsir membentangkan pada Konferensi Persatuan Islam di Bogor, 17 Juni 1934, apa yang disebutnya: “Islamietisch Paedagogische Ideaal.” Lebih tepatnya—dalam brosur yang dimuat di Capita Selecta jilid I (1956: 84)—yaitu: “…Islamietisch Paedagogische Ideaal jang gemerlapan jang harus memberi suar kepada tiap-tiap pendidik Muslimin dalam mengemudikan perahu pendidikannya.”
Menariknya, Natsir tidak terjebak dalam urusan dikotomi antara pendidikan Barat vis-à-vis pendidikan Timur. Bahkan, kata Natsir (1956: 84-85),
“seorang pendidik Islam tidak usah memperdalam-dalam dan meperbesar-besarkan antagonisme (pertentangan) antara Barat dengan Timur itu. Islam hanja mengenal antagonisme antara hak dan batil. Semua jang hak akan ia terima, biarpun datangnja dari Barat. Semua jang batil ia singkirkan, walaupun datangnja dari Timur.”
Oleh karena itu, yang paling penting adalah pendidikan integral-harmonis antara fisik dan spiritual untuk kesempurnaan hidup. Menurut Natsir, untuk membentuk satu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan hidup setidaknya mengandung dua perkara. Pertama, arah pendidikan yang sesuai dengan tujuan hidup. Kedua, asas pendidikan sebagai dasarnya, yaitu memperhambakan diri hanya kepada Allah, yakni tauhid. Natsir (1956: 82-83) menjelaskan:
“Akan memperhambakan diri kepada Allah, akan mendjadi hamba Allah, inilah tudjuan hidup kita diatas dunia ini. Dan lantaran itu, inilah pula tudjuan didikan jang wadjib kita berikan kepada anak-anak kita, jang lagi sedang menghadapi kehidupan…Hamba Allah ialah orang jang ditinggikan deradjatnja sebagai pemimpin untuk manusia.” Dengan kata lain, mereka divisikan untuk menjadi khalifah di muka bumi.
Untuk itu, pendidikan haruslah seimbang—dan sekaligus diintegrasikan—antara unsur intelektualisme (duniawiyah) dan spiritualisme (akhirat). Keseimbangan antara, apa yang disebut Natsir, “kebesaran dunia dan kemenangan achirat.” Karena hakikat penghambaan kepada Allah bukankah suatu penghambaan yang memberikan keuntungan kepada yang disembah, tetapi penghambaan yang mendatangkan kebahagiaan kepada yang menyembah.
Apakah ideologi sekolah Pendis ini berhasil diterapkan pada para siswanya? Testimoni dari beberapa siswa sekolah Pendis menjadi buktinya. Sekolah Pendis bagi M. Rusyad Nurdin, siswa pertama sekolah itu, adalah “…sistem pendidikan yang menitikberatkan kepada pembentukan pribadi yang berdaya fikir berkesinambungan dengan hati nuraninya, seimbang daya cipta dan taat tawakalnya kepada Allah subhanahu wata’ala” (Noer, 2007). Lain lagi siswa Pendis pada waktu telah ada Pesantren Persatuan Islam, yakni testimoni Entang Sulaiman. Katanya:
“…isuk-isuk sakola umum di HIS Pendidikan Islam, pasosore di Pasantren Persis…Resep sakola bari mesantren teh. Piraku henteu rek resep atuh da sakola di HIS, Hollandsch Inlandsche School tea. Pimanaeun harita mah anak guru desa pantar Uu make bisa nyakolakeun ka sakola kitu di Bandung '' (Entang Sulaiman, t.t.: 12). Selain terlihat perbedaan antara sekolah Pendis dengan Pesantren, testimoni ini juga sekaligus menunjukkan kebanggaan terhadap mutu sekolah itu sendiri. Para siswa Sekolah Pendis tumbuh menjadi manusia yang penuh harga diri dan mandiri.
Renungan Hari Ini
Ketika Pesantren Persatuan Islam didirikan di Kota Bandung pada tahun 1936, Sekolah Pendis telah tersebar di berbagai kota, bahkan hingga ke Jakarta, Bogor dan Gorontalo di Pulau Sulawesi. Jika kita merefleksi pada hari ini, maka fenomena yang terjadi adalah sebaliknya. Pesantren Persatuan Islam tersebar di mana-mana, sementara Sekolah Persatuan Islam hanya ada di satu dua titik. Mengapa bisa terjadi seperti itu?
Padahal, secara strategis, seyogyanya pendidikan umum lah yang bersifat dan menjadi pola pendidikan massal (untuk umum). Jamiyah menyediakan layanan pendidikan umum yang bisa dinikmati oleh tiap orang, yang menginginkan anak-anaknya merenda masa depan sebagai seorang profesional yang mandiri namun dengan kepribadian yang Islamis. Sementara itu, pendidikan pesantren jelas merupakan pendidikan khusus dan bahkan menjadi model pendidikan kader bagi Jamiyah Persatuan Islam.
Ketika Ustaz A. Hassan membangun Pesantren Persatuan Islam, maka hadir Ustaz E. Abdurrahman sebagai penerusnya. Bahkan Ustaz E. Abdurrahman berhasil membangun formulasi pendidikan Pesantren Persatuan Islam. Pada tahun 1952, Ustaz E. Abdurrahman merumuskan empat Qismu: yakni Ibtidaiyyah, Tsanawiyyah, Mu’allimin dan Mu’allimat. Pesantren Persatuan islam pun berkembang pesat sekaligus terjadi afinitas: antara perkembangan pesantren pada satu sisi dan pertumbuhan cabang Jamiyah di sisi lain. Maka, pesantren dan Jamiyah berjalin-kelindan bagai dua sisi mata uang.
Lain halnya dengan Sekolah Pendis. Sejak Natsir dan kawan-kawan para pengelola Pendis terjun ke dunia politik (Partai Masyumi), maka sekolah itu pun mati suri. Sejak dibubarkan Balatentara Jepang pada 1942, Sekolah Pendis tidak pernah dibangun lagi. Kekosongan penerus Natsir menyebabkan model sekolah umum di jam'iyyah Persatuan islam nyaris tidak lagi mempunyai tempat dan posisi yang berarti. Tiada lagi tokoh Jamiyah yang mampu memvisikan Sekolah Persatuan Islam sehingga bisa “seimbang” posisinya dengan Pesantren Persatuan Islam. Salah satu faktornya adalah karena historical disrupted pada tubuh Jamiyah puritan ini.
Tantangan terbesar bagi para aktivis Sekolah Persatuan Islam adalah menghadirkan kembali sosok yang bisa membangun sekolah yang visioner. Jika perlu, bukan sekolah yang menjadi subordinat dari pesantren. Malah, jika memang dengan framework yang jelas dan komprehensif, bisa saja ada dan muncul Sekolah yang berbasis pondok. Sudah adakah hari ini sosok pemikir baru dari para pengelola Sekolah Persatuan Islam?
Wallahu a’lam.
BACA JUGA:Aba Natsir: Guru Politik Umat Islam