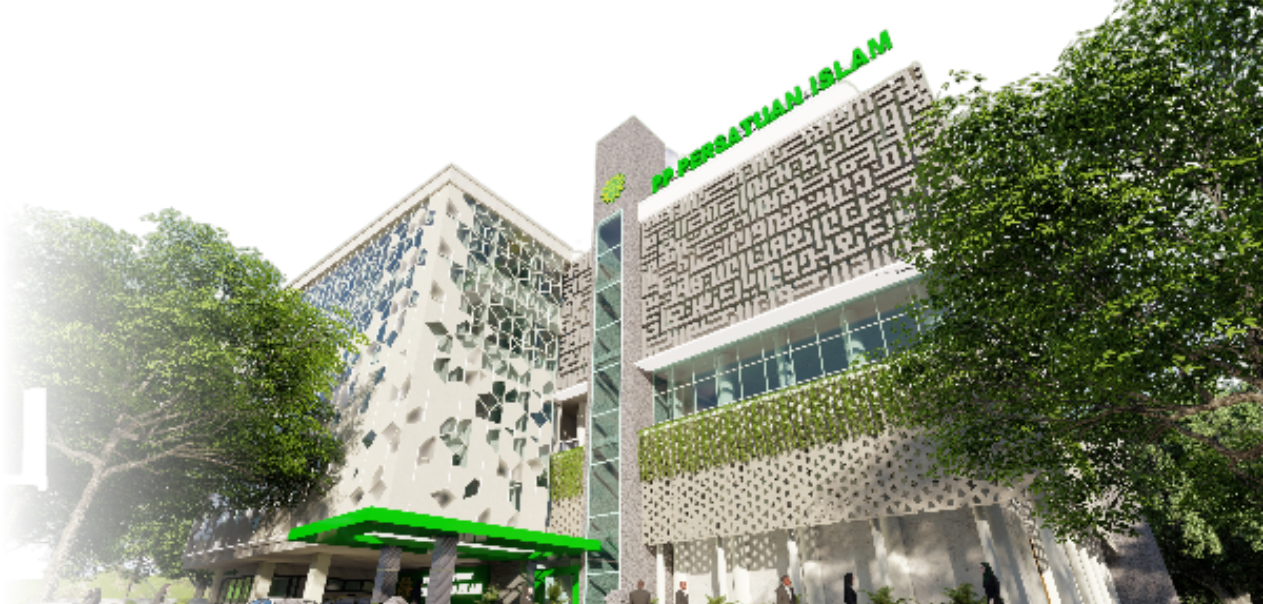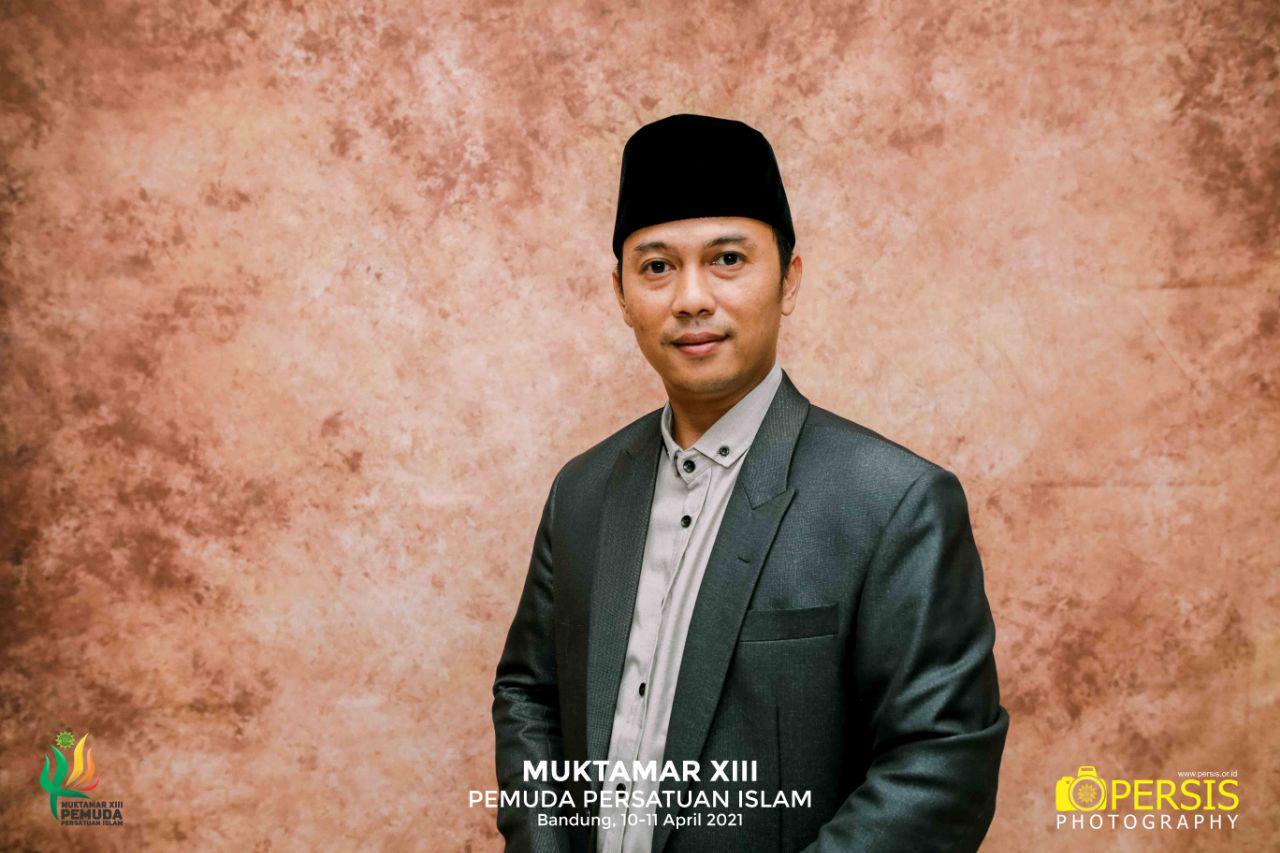Dalam dinamika kehidupan berjama’ah, etika spiritual menjadi fondasi utama yang menentukan arah, tujuan, dan keberkahan perjuangan. Berjama’ah bukan sekadar aktivitas kolektif, melainkan manifestasi dari ibadah yang menuntut keikhlasan, rasa takut kepada Allah (khasyyah), serta pengendalian diri agar tidak tergelincir pada kepentingan duniawi. Seperti ditegaskan oleh al-Qur’an, seorang mukmin sejati tetap merasa khawatir terhadap murka Allah meskipun telah beramal saleh.
Kesadaran inilah yang membentuk sikap tawadhu’, muhasabah, dan ihsan dalam berorganisasi, sehingga perjuangan berjama’ah selalu terikat dengan nilai-nilai ilahiah dan tidak kehilangan arah spiritualnya.
Allah berfirman:
إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
“Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka.” (QS. Al-Mu’minun: 57)
Tafsiran ayat ini menyebutkan: “Yakni keadaan mereka yang selalu mengerjakan perbuatan yang baik dan beriman serta mengamalkan perbuatan yang saleh, juga mereka takut kepada Allah dan selalu dicekam oleh rasa khawatir akan tertimpa tipu daya Allah.”1
Makna ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman yang sejati memiliki rasa takut (khasyyah) kepada Allah meskipun mereka sudah berbuat baik, beriman, dan beramal saleh. Rasa takut ini bukan karena tidak percaya pada rahmat Allah, tetapi sebagai bentuk penghormatan, ketundukan, dan kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan-Nya. Dalam konteks organisasi, hal ini menjadi nilai etika spiritual utama: bahwa setiap kader muslim dalam berorganisasi harus menanamkan rasa takut kepada Allah agar tetap ikhlas, tidak menyimpang dari tujuan yang benar, dan tidak tergelincir dalam kesombongan, riya’, atau penyimpangan amanah.
Spirit Muhasabah dan Rasa Khawatir akan Tipu Daya Allah
Penafsiran dari ayat ini dijelaskan oleh para ulama salaf. Imam Al-Qurthubi menukil penafsiran: “Mereka adalah orang-orang yang, meski sudah beramal saleh, tetap merasa takut kepada Allah, merasa cemas terhadap makar (tipu daya) Allah terhadap mereka.”2
Sementara itu, Al-Hasan Al-Bashri berkata:
إِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إِحْسَانًا وَشَفَقَةً، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا
“Sesungguhnya seorang mukmin itu menggabungkan antara kebaikan dan rasa takut (khasyyah), sedangkan orang munafik menggabungkan antara keburukan dan rasa aman (dari siksa Allah).”3
Ini menjadi nilai spiritual penting dalam organisasi: bahwa kader muda Islam tidak boleh merasa aman dari kesalahan, justru harus selalu melakukan muhasabah (introspeksi diri) agar tidak terjerumus dalam keburukan yang dibungkus oleh formalitas kebaikan. Dengan rasa takut yang sehat ini, mereka akan lebih berhati-hati dalam memegang amanah, dalam membuat keputusan strategis, dan dalam menjaga ukhuwah.
Komitmen kepada Amal Saleh yang Konsisten dan Tawadhu’
Ayat ini menunjukkan bahwa takut kepada Allah justru dimiliki oleh mereka yang beriman dan beramal saleh, bukan hanya orang-orang yang lalai. Artinya, dalam kondisi telah berbuat baik pun, seorang muslim tidak boleh merasa cukup atau puas.
Ini mencerminkan sikap tawadhu’ (rendah hati) dan komitmen terhadap amal saleh secara konsisten. Para ulama mendefinisikan tawadhu’ sebagai sikap batin yang lahir dalam bentuk rendah hati, tidak merasa lebih mulia dari orang lain, dan selalu menerima kebenaran. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa tawadhu’ adalah “suatu keadaan jiwa yang membuat seseorang tidak melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan menerima kebenaran dari siapa pun yang membawanya.”4 Ibn al-Qayyim menambahkan, “tawadhu’ adalah merendahkan diri terhadap kebenaran dan tunduk kepadanya, serta menerimanya dari siapa pun yang mengatakannya.”5
Dalam organisasi Islam, kader-kader seharusnya tidak merasa cukup dengan jasa atau kontribusi yang telah diberikan, tapi tetap rendah hati dan terus memperbaiki diri. Sikap ini akan menghindarkan dari ujub, sombong, atau merasa paling berjasa dalam perjuangan.
Menjaga Spirit Ihsan: Berbuat Baik dengan Kesadaran Ilahi
Al-Hasan al-Bashri menekankan bahwa seorang mukmin itu menggabungkan antara ihsan (berbuat baik) dengan rasa takut. Ini adalah konsep ihsan yang dijelaskan Nabi ﷺ dalam hadis: “Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak bisa melihat-Nya maka yakinlah bahwa Dia melihatmu.”6
Dalam konteks organisasi, nilai ihsan berarti bahwa kader Islam harus menjalankan tugas, proyek, atau tanggung jawabnya dengan kesungguhan, profesionalisme, dan kesadaran akan pengawasan Allah, bukan semata-mata untuk pujian atau kedudukan.
Kesimpulan
Dengan mengacu pada QS. Al-Mu’minun: 57, serta komentar para ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Bashri, maka dapat dirumuskan bahwa etika spiritual kader Islam dalam berorganisasi meliputi:
- Takwa dan khasyyah sebagai landasan keikhlasan dan amanah.
- Muhasabah terus-menerus, menjauhi sikap merasa aman dari penyimpangan.
- Tawadhu’ dan komitmen terhadap amal saleh, tanpa merasa puas atas prestasi.
- Spirit ihsan dalam menjalankan setiap peran organisasi.
- Wara’ dan hati-hati, agar tidak mencampuradukkan dakwah dengan ambisi dunia.
Nilai-nilai ini adalah pondasi ruhiyah yang kuat agar perjuangan organisasi Islam, khususnya bagi para kader muda, tetap berada di jalan yang lurus dan diberkahi oleh Allah ﷻ.
Catatan Kaki
- Isma‘il ibn ‘Umar ibn Katsir al-Dimasyqi. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim. Juz 5. Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1999, hlm. 476.
- Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, Juz 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 108;
- Isma‘il ibn ‘Umar ibn Katsir al-Dimasyqi. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim. Juz 5. hlm. 476.
- Abu Ḥamid al-Ghazali, Iḥya’ ‘Ulum al-Din, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), 353.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Madarij al-Salikin bayna Manazil Iyyaka Na‘budu wa Iyyaka Nasta‘in, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 329.
- Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, no. 50; Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, no. 9..
BACA JUGA:Khutbah Jumat: Agar Rumah Tangga Diberkahi Allah