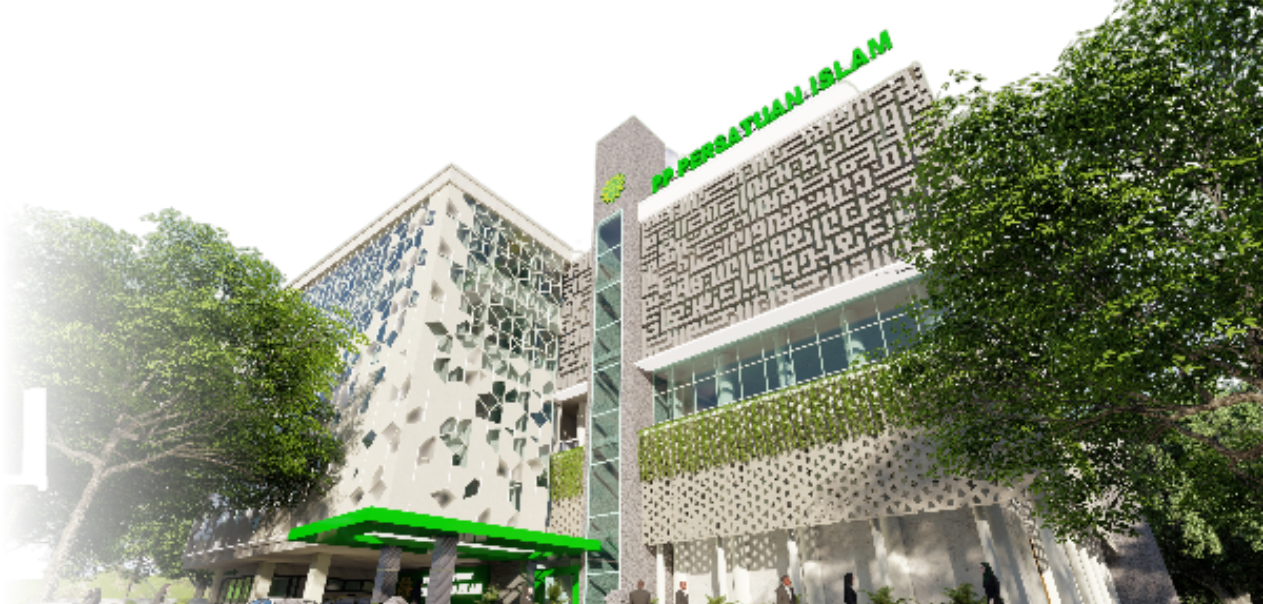Tiga hal di atas, yaitu simbol, ritual, dan struktur sosial adalah perwujudan agrerasi kebudayaan yang selalu akan ada sepanjang kehidupan manusia. Seorang da’i yang hendak menyampaikan pesan-pesan Allah Swt. untuk mengawal kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan Allah Swt. juga tidak akan lepas dari ketiga ruang agrerasi kultural di atas. Da’i yang berusaha menentang atau menghancurkan ketiga hal di atas bukan mendapatkan keberhasilan dalam dakwah, justru malah sebaliknya. Banyak ajakan dakwah yang terpental padahal pesannya sangat baik karena saat berinteraksi dengan mad’û tidak memperhatikan aspek kultural di atas. Misalnya, ada da’i yang ingin menyampaikan bahwa minuman keras itu haram. Lalu ia masuk ke Duty Free Bandara yang banyak menjual minuman keras. Ia teriakkan larangan itu dengan lantang di sana sambil mengambil dan membuang botol-botol miras di sana. Tindakan semacam ini hampir bisa dipastikan tidak akan membuat took miras itu tiba-tiba menghentikan jualannya. Yang akan terjadi, penjaga toko akan memanggil security lalu di da’i itu akan diseret keluar; bahkan bisa-bisa dituntut ke pengadilan karena dianggap berbuat keonaran. Pesan agamanya baik, tetapi karena dakwahnya tidak dilakukan dengan pengenalan aspek kultural seperti masalah struktur di Bandara, misalnya, akhirnya dakwahnya berakhir dengan kegagalan.
Rasulullah Saw. sebagai teladan kita semua di dalam berdakwah telah mencontohkan bagaimana beliau sangat faham dengan persoalan kultural di masyarakat Arab Mekah dan Madinah yang dihadapinya. Oleh karenanya, beliau selalu melakukan tindakan yang tepat atas bimbingan Allah Swt. Untuk menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka’bah sangat Rasul Saw. sadari tidak mungkin dapat dilakukannya langsung pada saat beliau masih berdakwah di Mekah. Posisinya adalah orang biasa saja, bukan penguasa di Mekah yang memiliki kekuasaan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Beliau baru dapat menghancurkannya setelah Futuh Mekah yang menempatkannya sebagai penguasa baru di Mekah pada tahun ke-8 dari Hijrahnya beliau.
Berkaitan dengan ritual, Nabi Saw. juga tidak menghapuskan ritual-ritual yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Mekah saat itu. Yang dilakukannya adalah memasukkan pemikiran dan nilai-nilai baru pada setiap ritual tersebut untuk menyempurnakan prosesnya agar lebih memberi maslahat. Contohnya pernikahan. Secara syar’i pernikahan sah hanya dengan menyelenggarakan akad nikah antara pengantin laki-laki dengan wali pengantin Perempuan, lalu diberikan mahar dan disaksikan oleh dua orang saksi. Akan tetapi, pernikahan dalam kehidupan seorang manusia adalah suatu passage (peralihan) langka. Ada yang sepanjang hidup mungkin hanya melakukannya sekali. Wajar bila kemudian dibuat ritual pernikahan di luar akad nikah yang syar’i yang disebut “walimah” dalam tradisi Arab. Nabi Saw. menegaskan dukungan agar diselenggarakan walimah seperti dalam hadis popular riwayat Imam Bukhori nari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah Saw. berkata kepadanya setelah melaksanakan akad nikah, “Buatlah pesta walimah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.” Walimah tetap dipertahankan, tetapi Rasulullah Saw. mengajarkan nilai kesederhanaan seperti mencontohkan walimah beliau sendiri hanya dengan menyiapkan makanan sisa bekal di perjalanan, karena pernikahannya dilakukan salam perjalanan. Ini adalah walimah yang lebih sederhana dari yang beliau perintahkan kepada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Orang sekaya Abdurrahman bin Auf hanya disuruh menyembelih satu kambing. Beliau sendiri hanya membagika sisa kismis dan keju dari bekal perjalannya. Nabi melakukan itu untuk merasionalisasi walimah agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan lain setelah walimah. Walimah yang tidak memperhatikan aspek kemampuan dan kesederhanaan sering menimbulkan dampak hutang atau kesulitan ekonimi sesudahnya. Di sinilah nilai baru yang diajarkan Nabi Saw. diwujudkan dalam tindakan yang langsung dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Esensi ritual passage-nya tetap dijaga, tapi dampak ikutannya dikendalikan. Inilah diantara contoh bagaimana dakwah Rasulullah Saw. memperhatikan aspek agregasi kultural dalam kehidupan manusia.
Kalau kita pernah mendengar istilah “dakwah budaya” atau “dakwah kultural” sesungguhnya ini adalah istilah yang tidak telalu tepat. Seolah-olah “dakwah budaya” ini hanyalah satu bagian dari beragam jenis dakwah lain. Mungkin selain ada dakwah budaya, ada juga dakwah politik, dakwah ekonomi, dakwah pendidikan, dakwah kesenian, atau yang lainnya. Kalau ini dakwah budaya dipersepsikan seperti itu yang akan sulit adalah mencari bentuknya. Mungkin dakwah politik bentuknya adalah dengan membentuk partai politik dan menyuarakan kepentingan Islam dalam kekuasaan. Dakwah pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam. Dakwah kesenian dengan menciptakan seni-seni Islami. Lalu kalau dakwah kebudayaan apa wujudnya? Jawabannya pasti membingungkan saat dikaitkan dengan definisi kebudayaan yang sangat luas itu. Sejatinya dakwah dan kebudayaan ini saling berhimpitan. Bila budaya itu berujud relasi kuasa yang disebut politik, maka di dalamnya akan ada pesan-pesan dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Saw. Bila budaya berwujud seni sebagai ekspresi estetis manusia, maka ada pesan dakwah juga di sana. Artinya “dakwah” dan “budaya” adalah persenyawaan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam berbagai perwujudun kehidupan manusia.
Oleh sebab itu, kesadaran kebudayaan bagi seorang da’i adalah kemestian yang tidak dapat ditawar. Seorang da’i yang hanya paham pesan-pesan syari’at tapi tidak mengenal budaya tempat ia hidup, cenderung akan membenturkan agama dengan kebudayaan. Padahal, mungkin yang dibenturkan adalah satu budaya dengan budaya lain. Misalnya, dalam syariat diperintahkan untuk menutup aurat. Perintah dalam Al-Quran untuk perempuan adalah menggunakan jenis pakaian bernama “jilbab” (j. jalâbib) seperti termaktub dalam QS Al-Ahzab [33]: 59. Jika merujuk paad jenis namanya, jilbab ini adalah penutup kepala yang lebih kecil dari ridâ’ (selendang) tapi lebih besar dari khimar (kerudung). Dengan perintah ini, apakah perempuan hanya boleh menggunakan “jilbab” untuk menutup kepalanya yang merupakan aurat itu? Tidak bolehkah menggunakan kain sarung khas Indonesia seperti yang dipakai perempuan di Lombok Nusa Tenggara Barat? Kalau kita tidak memiliki kesadaran kebudayaan, mungkin jawabnya tidak boleh karena “nash” tidak mengatakan menutupnya dengan kain sarung; hanya dengan “jilbab”. Karena ketiadaan kesadaran kebudayaan, muncullah simbolisasi keshalehan dengan menggunakan gamis dan sorban yang sering dipakai orang Arab. Padahal, di Arab sendiri banyak pencopet yang memakai gamis dan sorban.
Mungkin istilah yang lebih tepat adalah “dakwah berwawasan budaya”. Maknanya suatu proses dakwah yang memperhatikan aspek-aspek kebudayaan yang hidup di tempat dakwah dijalankan, terutama memperhatikan simbol-simbol yang dipahami masyarakat setempat, ritual-ritual yang biasa dijalankan, dan struktur-struktur sosial yang berlaku. Di sanalah akan teragregasi aspek-aspek kultural: what we think, what we do, dan what we make sehingga dakwah akan secara tepat dapat masuk ke dalam aspek-aspek kultural tersebut tanpa menimbulkan gejolak yang berlebihan dan tanpa merusak dakwah itu sendiri.
Dakwah memang akan juga bertemu dengan aspek-aspek kebudayaan yang benar-benar bertentangan dengan syariat seperti Nabi Saw. yang bertemu dengan kebiasaan Jahiliyah menyembah berhala, meminum khamr, berzina, membunuh, dan merendahkan perempuan. Aspek-aspek kebudayaan seperti itu sebetulnya dalam konteks kebudayaan sendiri dan dalam konteks kemanusiaan merupakan ekspresi kultural yang rendah; apalagi dalam konteks syariat yang memang datang untuk mewujudkan maslahat dan menghapuskan mafsadat (keburukan). Kebudayaan yang bertentangan syariat jelas merupakan objek budaya yang harus diubah. Namun, untuk sampai ke sana perlu diperhatikan tidak aspek simbolik, ritual, dan struktural di atas agar prosesnya tepat dan presisi. Demikian yang selalu dilakukan Rasulullah Saw. ketika akan melakukan dakwah mengubah suatu keadaan kultural tertentu seperti dicontohkan dalam kasus penghancuran patung-patung berhala di sekeliling Ka’bah di atas.
Dalam contoh kasus lain ketika Rasulullah Saw. berhadapan dengan maraknya perzinaan di Mekah pada masa Jahiliyah. Perzinaan merupakan ekspresi kultural yang merusak, baik pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Banyak sekali kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan karenanya. Di hadapan masyarakat Arab yang kelihatannya libido seksualnya tinggi, menghadapi perzinaan tidak cukup hanya dengan himbauan atau larangan keras berupa hukuman rajam dan cambuk. Harus ada alternatif penyaluran hasrat libidinal ini yang lebih maslahat dan tidak merusak. Untuk itu, kemudian Allah Swt. menetapkan kemudahan dalam pernikahan dan membolehkan seorang lelaki menikah hingga empat istri. Jika inipun masih buntu, maka dapat dibuka pintu milkul-yamîn; seseorang boleh mengambil budak perempuan untuk digauli, tapi dengan menetapkan syarat yang ketat hingga tidak menempatkan budak perempuan ini seperti pelacur. Pernikahan dan milkul-yamin yang dijamin kebolehannya oleh syariat merupakan pilihan kultural yang realistis dan maslahat ketika perzinaan dihapuskan. Karena ada alternatif kebudayaan inilah, ketika larangan zina sangat ketat hingga dibebani hukuman yang sangat berat hingga dirajam sampai mati, orang-orang tidak sampai kehilangan alternatif penyaluran kebutuhan eksistensialnya sebagai manusia. Inilah wawasan kebudayaan yang luas, mendalam, dan bijaksana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.
BACA JUGA:Islam, Agama, dan Kebudayaan (Bagian Dua)